TRANSFORMASI SISTEMIK HUKUM PIDANA INDONESIA
(Dari KUHP Lama ke KUHP Baru – Mental Map, Kebaharuan, dan Implikasi Praktis)
Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M. Kn.*) dan Andi Hakim Lubis**)
 Dialektika Kodifikasi Pidana dan Ujian Konstitusional Negara Hukum
Dialektika Kodifikasi Pidana dan Ujian Konstitusional Negara Hukum
Indonesia sedang berada pada titik balik sejarah hukum pidana. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru (UU No.  20 Tahun 2025) menandai berakhirnya rezim hukum pidana kolonial sekaligus membuka babak kodifikasi nasional yang lebih kontekstual, modern, dan berorientasi pada nilai Pancasila. Namun, transisi ini tidak berlangsung dalam ruang hampa. Gelombang uji materiil di Mahkamah Konstitusi sejak awal 2026 menunjukkan bahwa perubahan hukum selalu beriringan dengan dialektika konstitusional, menguji sejauh mana ambisi pembaruan selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
20 Tahun 2025) menandai berakhirnya rezim hukum pidana kolonial sekaligus membuka babak kodifikasi nasional yang lebih kontekstual, modern, dan berorientasi pada nilai Pancasila. Namun, transisi ini tidak berlangsung dalam ruang hampa. Gelombang uji materiil di Mahkamah Konstitusi sejak awal 2026 menunjukkan bahwa perubahan hukum selalu beriringan dengan dialektika konstitusional, menguji sejauh mana ambisi pembaruan selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Secara konseptual, KUHP dan KUHAP Baru menghadirkan pergeseran paradigma dari hukum represif-pelaku-sentris menuju hukum preventif-restoratif-masyarakat-sentris. Perluasan subjek hukum, pengakuan terhadap kejahatan struktural dan digital, serta fleksibilitas sanksi menegaskan orientasi baru yang lebih humanis dan adaptif. Prinsip jus restaurativum ante jus retributivum dan salus populi suprema lex esto dibaca ulang dalam konteks kekinian: kepentingan umum tidak lagi dimaknai semata sebagai ketertiban negara, melainkan keseimbangan antara keamanan publik, martabat individu, dan pemulihan sosial. Pada titik ini, hukum pidana diposisikan bukan sekadar sebagai instrumen pemidanaan, tetapi sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) yang berkeadilan.
Namun demikian, realitas pengujian konstitusional—baik terhadap pasal penghinaan, penyebaran berita bohong, pidana mati, maupun kewenangan penyitaan data elektronik—menunjukkan adanya ruang tafsir yang dipersepsikan berpotensi mencederai asas legalitas dan due process of law. Adagium ubi ius incertum, ibi ius nullum kembali relevan: ketidakpastian norma dapat berujung pada ketidakadilan. Di sinilah Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis sebagai the guardian of the constitution, memastikan agar ius constitutum tidak menyimpang dari jaminan konstitusional, khususnya hak privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.
Pengantar kajian ini menempatkan KUHP dan KUHAP Baru sebagai satu ekosistem hukum yang hidup, diuji tidak hanya di atas kertas, tetapi juga di ruang publik dan forum yudisial. Uji materiil yang berlangsung bukan sekadar resistensi terhadap perubahan, melainkan mekanisme checks and balances yang esensial dalam negara demokratis. Dengan demikian, pembahasan ini mengajak pembaca melihat pembaruan hukum pidana secara utuh: sebagai proyek kebangsaan yang progresif, namun harus terus dituntun oleh nalar konstitusional agar transformasi hukum benar-benar bermuara pada keadilan substantif dan kepastian hukum yang beradab.
Menuju Era Modernisasi Hukum Pidana
Hukum pidana Indonesia memasuki era transformatif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah lebih dari tujuh dekade menggunakan Wetboek van Strafrecht yang diwariskan Belanda, bangsa ini menapaki fase modernisasi melalui lahirnya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023/2026) dan KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025). Transformasi ini tidak sekadar revisi pasal demi pasal, melainkan revolusi paradigmatik: dari sistem represif-pelaku-sentris yang formalistik menuju hukum preventif-restoratif-masyarakat-sentris, yang menempatkan kepentingan sosial, hak individu, dan harmoni komunitas sebagai pijakan utama. Dalam perspektif ius integrum nusantara, KUHP Baru menegaskan bahwa hukum pidana adalah instrumen keadilan substantif sekaligus sarana pembangunan moral dan sosial.
Transformasi hukum pidana Indonesia kini mencapai titik yang sangat progresif melalui integrasi antara sanksi korporasi yang lebih berat dan prosedur digitalisasi penegakan hukum.
Kehadiran KUHP dan KUHAP Baru berfungsi sebagai architectural blueprint bagi sistem hukum pidana modern. Filosofi, prosedur, dan sanksi diharmonisasikan untuk menjawab kompleksitas kejahatan kontemporer: dari korupsi lintas korporasi hingga cybercrime global. Asas legalitas, lex mitior, postulat restorative justice, serta adagium klasik seperti jus restaurativum ante jus retributivum dan salus populi suprema lex esto tidak sekadar simbolik, tetapi menjadi pedoman normatif yang menyeluruh bagi aparat hukum, hakim, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Narasi hukum ini, jika dipetakan secara mental map, menggambarkan KUHP Lama sebagai pohon tua yang kaku dan KUHP Baru sebagai pohon modern: bercabang luas, berdaun lebat, berbuah keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pokok pembahasan ini disusun untuk menampilkan transformasi sistemik hukum pidana Indonesia secara koheren. Pendekatan ini menyintesiskan filosofi, subjek-objek-perbuatan, sanksi, integrasi normatif, serta refleksi konstitusional dan empiris, sekaligus memberikan policy-oriented insight bagi praktik hukum modern. Dengan membaca KUHP Baru sebagai ekosistem hukum pidana, pembaca dapat memahami bagaimana norma substantif, prosedur, dan prinsip keadilan berpadu, membentuk sistem adaptif yang responsif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan global.
Fondasi Filosofis: Ius Integrum Nusantara dan Paradigma Baru
Adagium klasik fiat iustitia, ruat caelum menegaskan relevansi keadilan substantif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. KUHP Baru menghadirkan historical discontinuity yang terukur, menandai peralihan dari hukum kolonial yang dominan bersifat formalistik menuju sistem hukum nasional yang integratif, humanis, dan adaptif. Filosofi ius integrum nusantara menekankan keseimbangan antara nilai lokal (customary law), prinsip universal HAM (jus cogens), dan hukum positif nasional, menjadikan hukum pidana instrumen pembangunan sosial sekaligus pengayom hak asasi individu.
Secara historis, KUHP kolonial menempatkan perbuatan pidana semata sebagai pelanggaran norma tertulis dengan fokus pada actus reus dan sanksi represif. Sementara korban dan konteks sosial terabaikan, prinsip nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege hanya menjadi formalitas teknis. KUHP Baru menegaskan bahwa kepastian hukum (legal certainty) tetap dipegang, namun kini dilengkapi dengan lex mitior, hukum hidup (lex non scripta), dan pengakuan terhadap kearifan lokal. Aspek deterministik ini, bersanding dengan responsivitas sosial, menegaskan orientasi substantif KUHP Baru: hukum pidana harus menyeimbangkan pelaku, korban, dan masyarakat.
Paradigma baru ini tercermin dalam pertanggungjawaban pidana yang memadukan unsur subjektif (mens rea) dan objektif (actus reus). KUHP Baru menekankan pertimbangan niat, kesadaran, kapasitas pelaku, dan dampak sosial. Pendekatan ini menjamin keadilan distributif, yang menekankan evaluasi niat dan efek sosial sebagai bagian dari pertimbangan sanksi pidana. KUHP dan KUHAP Baru membentuk kerangka integratif, di mana norma substantif berpadu dengan prosedur transparan dan akuntabel, termasuk pengakuan alat bukti digital, persidangan daring, dan perlindungan hak korban (due process of law).
Transformasi Subjek, Objek, dan Perbuatan
KUHP Baru secara signifikan memperluas subjek hukum: anak, kelompok rentan, pejabat publik, dan korporasi kini menjadi entitas pertanggungjawaban pidana. Objek hukum tidak lagi sempit; hak asasi manusia, martabat individu, lingkungan hidup, kesusilaan, dan ruang digital diakui sebagai perlindungan legal. Transformasi perbuatan pidana dari fisik ke struktural menandai pengakuan terhadap kejahatan korporasi, tindak pidana ekonomi, dan kejahatan siber, di mana actus reus dan mens rea dievaluasi secara kontekstual. Misalnya, konsep pertanggungjawaban korporasi dan restitusi memang diakomodasi dalam KUHP Baru, mencerminkan orientasi “social harm”, tetapi pengaturannya tersebar di pasal-pasal lain:
- Pertanggungjawaban Korporasi: diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana oleh Korporasi, yang dimulai dari Pasal 45 dan seterusnya. Pasal 45 ayat (1) menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana.
- Restitusi dan Ganti Rugi: KUHP Baru mengutamakan pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, termasuk melalui pidana tambahan berupa pembayaran restitusi atau ganti rugi. Ini merupakan bagian dari “tindakan” yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, termasuk korporasi.
Jadi, sementara semangat “social harm” dan mekanisme untuk meminta ganti rugi publik ada dalam KUHP baru, dan KUHP Baru menekankan pertanggungjawaban korporasi sekaligus restitusi terhadap kerugian publik, mencerminkan orientasi social harm yang adaptif.
Pendekatan ini menegaskan prinsip salus populi suprema lex esto: kepentingan publik menjadi batas utama dalam menegakkan hukum, tanpa mengorbankan hak individu. KUHP Baru juga memberikan fleksibilitas sanksi—penjara, denda, kerja sosial, rehabilitasi, larangan tertentu, dan restitusi—menggeser orientasi dari pemidanaan formalistik menuju multi-modal, humanis, dan adaptif. Prinsip jus restaurativum ante jus retributivum menegaskan bahwa pemulihan sosial lebih utama daripada balas dendam hukum, selaras dengan praktik restorative justice modern.
Integrasi Normatif dan Sistemik: KUHP dan KUHAP Baru sebagai Ekosistem Hukum
KUHP Baru tidak berdiri sendiri; ia terintegrasi dengan UU terkait, yurisprudensi, dan praktik penegakan hukum modern. Pendekatan ini membentuk sistem pidana nasional yang koheren. Misalnya, pengaturan pidana korupsi, perlindungan anak, dan cybercrime lintas negara diharmonisasikan dengan UU Anti Korupsi, UU Perlindungan Anak, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. KUHAP Baru memastikan prosedur penegakan hukum adil, akuntabel, dan transparan, termasuk mekanisme praperadilan, persidangan daring, dan pengakuan alat bukti digital.
Prinsip four point determination—berat perbuatan, niat pelaku, dampak terhadap korban, dan efek preventif—menjadi kerangka operasional dalam menentukan sanksi. Hal ini terlihat dalam Penerapan Pasal 473 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengatur tentang perkosaan dan kekerasan seksual, serta Pasal 603 hingga 606 mengenai tindak pidana korupsi, menandai transformasi besar dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, pengaturan mengenai pemalsuan dokumen dan integritas surat yang tertuang dalam Pasal 391 hingga 400 mempertegas komitmen negara dalam menjaga ketertiban hukum di era modern. Melalui pembaruan ini, hukum pidana nasional kini berfungsi tidak sekadar sebagai instrumen penghukuman, melainkan juga sebagai sarana perlindungan bagi korban dan pemulihan kerugian sosial. Dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan preventif, regulasi tersebut bertujuan untuk membangun efek jera yang nyata sekaligus menciptakan keseimbangan antara kepentingan hukum negara dengan hak-hak asasi individu.
Analisis Substantif: Pasal-Pasal dan Sanksi yang Humanis dan Futuristik
Salah satu inovasi paling menonjol dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) adalah fleksibilitas sanksi pidana. Berbeda dengan KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) yang seringkali menekankan hukuman penjara dan denda sebagai pilihan tunggal (one-size-fits-all punishment), KUHP Baru mengenalkan pendekatan multi-modal melalui beragam jenis sanksi dan penempatan restorative justice sebagai pilar utama. Pendekatan ini mencakup pidana pokok seperti penjara dan denda, serta pidana tambahan dan alternatif seperti pidana kerja sosial (Pasal 85) dan pidana pengawasan (Pasal 75).
Pasal-pasal kunci di dalamnya mendukung penerapan keadilan restoratif. Sebagai contoh, Pasal 54 memberikan dasar bagi hakim untuk menerapkan pemaafan hakim (judicial pardon) untuk perkara ringan, di mana pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan pidana meskipun perbuatannya terbukti melanggar hukum, dengan mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku atau adanya pemulihan keadaan. Sementara itu, prinsip mempertimbangkan konteks sosial dan kapasitas pelaku ditekankan dalam rumusan tujuan dan pedoman pemidanaan secara umum (Pasal 51-54). Prinsip ini menegaskan adagium klasik yang diinterpretasikan modern: jus restaurativum ante jus retributivum, yakni pemulihan sosial didahulukan atas pembalasan hukum.
Selain fleksibilitas sanksi, KUHP Baru mengakomodasi kejahatan non-fisik dan struktural. Misalnya, tindak pidana korporasi, cybercrime, pelanggaran privasi digital, dan kejahatan berbasis relasi kuasa kini diakui sebagai delik, yang sebelumnya tidak tersentuh dalam KUHP Lama. Subjek hukum diperluas, termasuk anak-anak, kelompok rentan, pejabat publik, dan korporasi. Objek hukum meliputi hak asasi manusia, martabat individu, lingkungan hidup, dan ruang digital. Hal ini menegaskan filosofi salus populi suprema lex esto: kepentingan publik kini mencakup kesejahteraan individu, korban, dan komunitas, bukan sekadar kepatuhan terhadap norma formal.
Evolusi hukum pidana Indonesia mencapai puncaknya dengan berlakunya KUHP Nasional (UU 1/2023) dan KUHAP Baru (UU 20/2025) secara serentak pada Januari 2026. Inovasi fundamental terlihat pada pengaturan pertanggungjawaban korporasi (Pasal 45–50 KUHP Baru), di mana entitas bisnis kini dapat dimintai pertanggungjawaban langsung atas kejahatan ekonomi, termasuk kewajiban restitusi bagi korban. Kehadiran KUHAP Baru menegaskan transformasi digital dalam peradilan melalui pengakuan alat bukti elektronik serta legalitas persidangan daring dan pemanggilan elektronik. Sinergi kedua kitab undang-undang ini menciptakan sistem pidana yang futuristik dan responsif terhadap kejahatan teknologi lintas batas, tanpa sedikit pun mengesampingkan prinsip due process of law.
Transformasi hukum pidana Indonesia kini mencapai titik yang sangat progresif melalui integrasi antara sanksi korporasi yang lebih berat dan prosedur digitalisasi penegakan hukum. Dalam sistem KUHP Nasional, korporasi tidak lagi sekadar subjek hukum formal, melainkan entitas yang memikul tanggung jawab sosial dan finansial yang luas. Jika sebuah korporasi terbukti melakukan tindak pidana, hakim tidak hanya dapat menjatuhkan pidana denda sebagai hukuman pokok, tetapi juga berbagai pidana tambahan yang bersifat korektif dan preventif. Pidana tambahan ini mencakup kewajiban restitusi kepada korban, pembiayaan perbaikan akibat tindak pidana, hingga sanksi reputasional melalui pengumuman putusan hakim. Dalam kasus yang lebih ekstrem, negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilalihan manajemen, pencabutan izin usaha, bahkan pembubaran korporasi secara permanen.
Sejalan dengan ketegasan sanksi tersebut, KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) menyediakan instrumen penegakan hukum yang futuristik, terutama dalam menangani aset digital yang sering menjadi instrumen kejahatan korporasi modern. Mekanisme penyitaan kini tidak lagi terbatas pada barang fisik, tetapi menjangkau informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti utama. Penyidik kini dibekali otoritas untuk melakukan penggeledahan sistem elektronik dan penyitaan aset digital, seperti aset kripto atau saldo pada dompet elektronik, dengan cara mengunci akses, menggandakan data, atau memindahkan private keys ke dalam kontrol negara.
Prosedur ini dirancang sangat efisien; dalam kondisi mendesak di mana aset digital berisiko dipindahkan dalam hitungan detik, penyidik dapat melakukan tindakan pengamanan terlebih dahulu sebelum melaporkannya kepada pengadilan. Melalui kombinasi sanksi korporasi yang beragam dan prosedur penyitaan digital yang taktis, hukum pidana Indonesia kini mampu beroperasi secara responsif di tengah kompleksitas ekonomi digital, memastikan bahwa pemulihan kerugian negara dan korban tetap menjadi prioritas utama tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum.
Penerapan KUHP Nasional (UU 1/2023) dan KUHAP Baru (UU 20/2025) yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 telah memperluas cakupan sanksi bagi korporasi serta mempermodern teknik penyidikan, khususnya untuk aset digital, yaitu:
- Daftar Pidana Tambahan Khusus Korporasi
Dalam sistem hukum yang baru, korporasi tidak hanya dijatuhi pidana denda (pidana pokok), tetapi juga serangkaian pidana tambahan yang bertujuan untuk pemulihan dan efek jera yang lebih luas. Selain itu, setidaknya terdapat sekitar 12 jenis pidana tambahan bagi korporasi, di antaranya:
- Pembayaran Restitusi: Kewajiban membayar ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya.
- Perbaikan Akibat Tindak Pidana: Melakukan tindakan konkret untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan.
- Pengambilalihan Korporasi: Dalam kondisi tertentu, manajemen korporasi bisa diambil alih sementara oleh negara.
- Pencabutan Izin Usaha: Baik sebagian maupun seluruhnya secara permanen.
- Pelarangan Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu: Membatasi operasional perusahaan di bidang yang menjadi celah kejahatan.
- Penutupan Seluruh atau Sebagian Tempat Usaha: Penghentian operasional fisik di lokasi tertentu.
- Pengumuman Putusan Hakim: Kewajiban mempublikasikan putusan pengadilan agar masyarakat mengetahui kejahatan tersebut (sanksi reputasi).
- Pembubaran Korporasi: Sanksi terberat berupa pembekuan total entitas hukum korporasi.
- Mekanisme Penyitaan Aset Digital dalam KUHAP Baru
KUHAP Baru (UU 20/2025) secara progresif mengatur penanganan barang bukti yang bersifat tidak berwujud (intangible) seperti mata uang kripto, data elektronik, dan aset digital lainnya. Mekanismenya meliputi:
- Perluasan Definisi Alat Bukti: Pasal 184 kini diperluas untuk mengakui secara penuh informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah tanpa perlu bergantung pada UU ITE lagi.
- Penyitaan Data & Akun: Penyidik diberikan wewenang untuk melakukan penggeledahan sistem elektronik dan melakukan penyitaan dengan cara menggandakan data, mengunci akses, atau memindahkan aset digital (seperti private keys dompet kripto) ke penyimpanan milik negara.
- Penyitaan dalam Keadaan Mendesak: Untuk mencegah penghapusan data atau transfer aset digital secara instan, penyidik dapat melakukan tindakan tanpa izin pengadilan terlebih dahulu, dengan kewajiban melapor dalam waktu singkat setelah tindakan dilakukan.
- Pemanfaatan Teknik Investigasi Khusus: Penggunaan teknologi pelacakan (tracking) untuk mengikuti aliran transaksi digital dalam kasus korporasi dan pencucian uang lintas batas.
Perlu dicatat bahwa saat ini pemerintah juga tengah memfinalisasi RUU Perampasan Aset untuk melengkapi mekanisme ini agar aset yang tidak wajar dapat disita meski tanpa melalui putusan pidana penuh (non-conviction based asset forfeiture)
Contoh konkrit terlihat pada Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP Baru yang mengatur pertanggungjawaban korporasi, dan pasal-pasal tersebut (dan bab terkait) secara eksplisit menyatakan bahwa pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi. Dalam kasus penggelapan dana publik oleh perusahaan cangkang, pelaku individu maupun entitas korporasi dapat dikenai pidana, diwajibkan melakukan restitusi, dan diawasi secara administratif (tindakan tata tertib).
KUHP Baru juga menegaskan prosedur penegakan yang modern. Meskipun pengakuan alat bukti digital sudah diakui melalui UU ITE dan peraturan pelaksanaannya (seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik), KUHP Baru mengadopsi sistem pembuktian terbuka yang memungkinkan perluasan alat bukti yang sah di luar yang disebutkan limitatif dalam KUHAP lama (Pasal 184 KUHAP). Dengan demikian, sistem pidana Indonesia menjadi futuristik sekaligus responsif, mampu menanggapi kejahatan lintas batas dan teknologi tanpa mengorbankan prinsip due process.
Perspektif Konstitusional: Harmonisasi dengan UUD 1945 dan HAM
KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) tidak hanya memperbarui norma hukum pidana; ia juga merespons tuntutan konstitusional dan mengadopsi paradigma modern. Reformasi ini menegaskan keselarasan dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 28D dan Pasal 28G UUD 1945, yang menjamin hak atas kepastian dan perlindungan hukum serta hak atas perlindungan diri pribadi dan martabat. Dengan mengadopsi paradigma keadilan preventif dan restoratif, KUHP baru memastikan hak dan kepentingan korban menjadi perhatian utama, sekaligus mendorong pengurangan penggunaan hukuman penjara yang represif secara berlebihan bagi pelaku, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak atau tindak pidana ringan, melalui penerapan sanksi alternatif.
Rekonstruksi hukum yang mencerminkan semangat dan paradigma baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. KUHP baru mengadopsi pendekatan modern yang berfokus pada keadilan restoratif dan proporsionalitas, yang selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan konstitusi Indonesia, dan berikut penjelasannya:
- Pasal 28D UUD 1945 menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. KUHP baru sejalan dengan ini melalui penekanan pada asas legalitas yang lebih jelas dan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa.
- Pasal 28G UUD 1945 menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Ini berkaitan dengan penekanan KUHP pada perlindungan korban dan martabat manusia, serta mengurangi hukuman represif yang berlebihan.
- Paradigma preventif-restoratif diakui sebagai pendekatan utama, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan mengedepankan solusi di luar proses peradilan formal untuk kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan anak atau pelanggaran ringan.
- Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan bagi korban dan perlakuan yang proporsional bagi pelaku, menghindari pemidanaan yang semata-mata bersifat pembalasan
Prinsip konstitusional ini tercermin dalam integrasi KUHP Baru dengan UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan Seksual, UU Cybercrime, dan UU Lingkungan Hidup. Harmonisasi ini mencegah tumpang tindih norma (lex specialis derogat legi generali), sekaligus memperkuat legitimasi hukum pidana nasional di ranah HAM dan standar internasional. Dalam konteks uji materi, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa kepastian hukum harus berimbang dengan keadilan substantif; KUHP Baru menjawab ini melalui struktur normatif dan prosedur yang fleksibel, humanis, dan adaptif.
KUHP Baru secara eksplisit mempertimbangkan aspek perlindungan kelompok rentan: anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Perlindungan khusus bagi korban kekerasan, dengan mekanisme pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, dan restitusi, diatur dalam bab dan pasal-pasal yang tersebar, seperti ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 2 dan berbagai pasal dalam Bab XIII tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia. Pendekatan ini mengubah paradigma hukum pidana dari sekadar menghukum ke arah pemulihan harmoni sosial, konsisten dengan prinsip salus populi suprema lex esto.
Implikasi Praktis: Aparat Hukum, Hakim, dan Kebijakan Publik
Transformasi KUHP dan KUHAP Baru membawa implikasi praktis yang luas. Pertama, bagi aparat penegak hukum, pendekatan multi-modal memerlukan kapasitas evaluasi konteks sosial dan niat pelaku, bukan hanya penerapan teks hukum mekanistik. Kedua, bagi hakim, prinsip four point determination—berat perbuatan, niat pelaku, dampak terhadap korban, dan efek preventif—menjadi landasan dalam menentukan sanksi yang proporsional dan humanis. Misalnya, kasus penggelapan dana sekolah kini mempertimbangkan rehabilitasi, restitusi, dan pengawasan sosial, bukan sekadar penjara.
Ketiga, bagi pembuat kebijakan, KUHP Baru menyediakan kerangka legal untuk menanggapi kejahatan modern, termasuk siber, lingkungan, dan korupsi struktural. Pendekatan ini memungkinkan desain kebijakan yang berbasis evidence-informed law, di mana sanksi dan prosedur hukum dapat disesuaikan dengan efektivitas pencegahan dan pemulihan sosial. Keempat, masyarakat dan korban mendapatkan peran lebih aktif dalam proses hukum, melalui restorative justice, mediasi, dan hak pendampingan. Pendekatan ini memadukan kepastian hukum dengan kemanfaatan sosial (social utility), selaras dengan filosofi Ius Integrum Nusantara.
Mental Map KUHP Baru: Ekosistem Hukum yang Hidup
Secara konseptual, KUHP Baru dapat dibayangkan sebagai ekosistem hukum: norma substantif, prosedur penegakan, sanksi fleksibel, dan prinsip hukum membentuk jaringan yang saling terkait. Subjek hukum meliputi individu, kelompok rentan, dan korporasi; objek hukum mencakup hak asasi, martabat, lingkungan, dan ruang digital; perbuatan pidana meluas dari fisik ke struktural dan non-fisik; sanksi fleksibel, humanis, dan restoratif; prosedur transparan dan akuntabel melalui KUHAP Baru. Ekosistem ini menegaskan integrasi norma, prosedur, dan nilai sosial, membentuk hukum pidana yang adaptif, koheren, dan futuristik.
KUHP Baru sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana
KUHP Baru bukan sekadar revisi pasal, melainkan rekonstruksi sistemik hukum pidana Indonesia. Transformasi ini menegaskan paradigma baru: hukum pidana sebagai instrumen preventif, restoratif, dan humanis; integrasi KUHP-KUHAP sebagai ekosistem normatif; dan sanksi yang fleksibel, proporsional, serta kontekstual. Adagium klasik diinterpretasikan ulang: jus restaurativum ante jus retributivum menekankan pemulihan sosial, sementara salus populi suprema lex esto memastikan keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu. Filosofi Ius Integrum Nusantara menjadi fondasi normatif, prosedural, dan sistemik yang menghubungkan masa lalu, kebutuhan kontemporer, dan tantangan masa depan.
Kajian ini mengilustrasikan dan membayangkan KUHP Baru sebagai pohon hukum modern: kokoh, bercabang luas, berbuah keadilan, dan berdaun perlindungan bagi semua subjek hukum. Sistem ini tidak hanya deterministik, tetapi juga responsif, humanis, dan adaptif, menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia kini mampu menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan hak, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban. Novelty ini bersifat normatif, substantif, dan sistemik, menjadikan KUHP Baru fondasi hukum pidana yang futuristik, harmonis, dan selaras dengan aspirasi keadilan manusiawi.
Transformasi Sistemik Hukum Pidana Indonesia
Hukum pidana Indonesia sedang memasuki babak baru. Setelah lebih dari tujuh dekade menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir dari warisan kolonial Belanda, Indonesia akhirnya menapaki era modernisasi hukum pidana dengan lahirnya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023 jo. UU No. 1 Tahun 2026) dan KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025). Transformasi ini bukan sekadar perubahan pasal demi pasal, melainkan pergeseran paradigma hukum yang fundamental: dari sistem represif, formalistik, dan pelaku-sentris menuju hukum yang humanis, proporsional, dan berpijak pada nilai Pancasila.
Sejak karakter hukum hingga konstruksi pasal, dari rekonstruksi nilai hingga kerangka keadilan, setiap lapisan KUHP Baru dirancang untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan hak individu, mengakomodasi perkembangan teknologi, dan merespons tuntutan keadilan sosial. Asas legalitas, prinsip proporsionalitas, postulat restorative justice, dan adagium modern seperti jus restaurativum ante jus retributivum menjadi fondasi sekaligus panduan moral dan praktis bagi aparat hukum, masyarakat, dan lembaga peradilan.
Pokok pembahasan ini menguraikan transformasi secara sistemik, dari akar hukum hingga implementasi praktis, termasuk perlindungan kelompok rentan, harmonisasi dengan hukum internasional, integrasi norma dengan UU khusus, hingga modernisasi proses peradilan. Disusun sebagai naratif mental map, pembaca dapat membayangkan KUHP Lama sebagai pohon tua yang kaku, dan KUHP Baru sebagai pohon modern yang kokoh, bercabang luas, berdaun lebat, dan berbuah bagi kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Tiga fokus utama pembahasan adalah:
- Transformasi sistemik → pergeseran paradigma, filosofi, dan praktik hukum.
- Perbandingan KUHP Lama vs Baru → seluruh pokok bahasan historis, struktural, dan kontemporer.
- Mental map dan kebaharuan → menyajikan alur konseptual, inovasi hukum, dan implikasi praktis.
Dengan perspektif ini, pembahasan tidak sekadar membandingkan pasal-pasal, tetapi menekankan kebaharuan sistemik, implikasi praktis, dan peluang KUHP Baru untuk menjadi fondasi hukum pidana yang adaptif, humanis, dan selaras dengan standar global.
Fondasi Filosofis dan Perspektif Ius Integrum Nusantara
“Fiat iustitia, ruat caelum”—biarlah keadilan ditegakkan, meski langit runtuh. Adagium klasik ini tidak sekadar simbolik; ia menjadi pijakan filosofis yang menemukan relevansi kontekstual dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Keadilan tidak lagi direduksi pada tindakan menghukum, melainkan dipahami sebagai instrumen integral untuk melindungi, memulihkan, dan menyeimbangkan hak serta kewajiban seluruh subjek hukum.
Lahirnya KUHP Baru dan KUHAP Baru menandai fase transformatif: peralihan dari hukum pidana kolonial yang formalistik menuju sistem nasional yang integratif, humanis, dan adaptif, yang dapat dibaca melalui paradigma Ius Integrum Nusantara (IIN). Sejak masa kemerdekaan, Indonesia menghadapi ketegangan historis antara kepastian hukum dan keadilan substantif. KUHP kolonial (Wetboek van Strafrecht 1918, diadopsi pascakemerdekaan) menempatkan perbuatan pidana sebagai pelanggaran norma tertulis semata, dengan fokus pada actus reus dan sanksi represif—penjara atau hukuman mati—sementara korban dan konteks sosial nyaris diabaikan. Paradigma ini menegaskan prinsip command of the sovereign, di mana hukum pidana berfungsi sebagai instrumen dominasi negara, bukan sarana pembangunan sosial. Adagium nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege menjadi pedoman semata, tanpa menyesuaikan diri dengan perkembangan nilai lokal maupun universal.
KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menghadirkan historical discontinuity yang terukur. Pasal 1–3 menegaskan bahwa asas legalitas tetap berlaku, tetapi diperluas melalui pengakuan terhadap lex mitior (Pasal 3) dan hukum hidup (lex non scripta), termasuk kearifan lokal dan norma sosial yang berkembang (Pasal 2). Dengan demikian, kepastian hukum dipertahankan secara deterministik, tetapi normatifnya kini dialogis: norma tidak hanya ditaati, tetapi juga diinterpretasikan dalam konteks sosial, budaya, dan moral masyarakat Indonesia. Prinsip ini selaras dengan filosofi IIN (Integratif, Instrumental, Normatif), yang menempatkan hukum pidana sebagai instrumen keadilan substantif yang menyeimbangkan tiga dimensi: nilai lokal (customary law), norma universal (HAM dan prinsip jus cogens), serta hukum positif nasional.
Dimensi deterministik IIN tercermin pada struktur KUHP Baru yang sistematis dan prediktif. Misalnya, pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi (seperti Pasal 686 dan seterusnya) dan tindak pidana ekonomi tidak hanya menegaskan unsur delik dan sanksi, tetapi juga memperluas pertanggungjawaban hingga ke korporasi dan restitusi kerugian negara. Sementara itu, aspek futuristik tampak dalam penyesuaian terhadap kejahatan siber, perdagangan manusia lintas negara, dan kejahatan transnasional (seperti diatur dalam Bab XXVIII), yang menunjukkan bahwa hukum pidana kini mampu merespons kompleksitas sosial, teknologi, dan ekonomi modern tanpa kehilangan orientasi nilai konstitusional.
Pergeseran paradigma ini juga menempatkan unsur subjektif (mens rea) sejajar dengan unsur objektif (actus reus). KUHP Baru, yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan niat, kesadaran, kapasitas bertanggung jawab, dan konteks sosial pelaku, yang tercermin antara lain dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akurasi yuridis, tetapi juga menjamin keadilan distributif, di mana pelaku, korban, dan masyarakat memperoleh perlakuan yang proporsional. Konsep ini tercermin dalam semangat yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkembang, yang menekankan pentingnya menilai niat dan dampak sosial dalam menentukan sanksi pidana, bukan sekadar menghukum secara mekanistik.
Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, KUHP Baru tidak berdiri sendiri; ia terhubung secara integral dengan KUHAP, yang saat ini telah diperbarui menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU ini menetapkan prosedur penegakan hukum secara transparan, adil, dan akuntabel. KUHAP Baru memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif (misalnya dalam mekanisme restorative justice untuk tindak pidana tertentu), memperkuat mekanisme praperadilan, dan menegaskan hak atas pendampingan hukum. Dalam konteks modern, pasal-pasal yang mengakui alat bukti digital dan mekanisme persidangan daring memastikan bahwa prosedur hukum tetap relevan dengan era digital, sekaligus mempertahankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas (due process), yaitu dengan memperhatikan:
- Konsep mens rea dan actus reus: KUHP Baru secara eksplisit menegaskan prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” (nulla poena sine culpa) dan memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana (sistem dualistis), yang menempatkan unsur subjektif sebagai syarat mutlak.
- Pertimbangan niat, kapasitas, dan konteks sosial: KUHP Baru mengadopsi paradigma pemidanaan yang lebih modern dan restoratif, dengan tujuan tidak hanya pembalasan tetapi juga pencegahan, rehabilitasi, dan penyelesaian konflik, yang memerlukan pertimbangan konteks yang lebih luas.
- “KUHAP Baru” dan isinya: Indonesia kini memiliki UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang menggantikan UU No. 8 Tahun 1981. Narasi mengenai partisipasi korban, penguatan praperadilan, hak pendampingan, dan alat bukti digital adalah benar adanya dan merupakan bagian dari pembaruan substansial dalam hukum acara pidana Indonesia.
Integrasi Substansi dan Prosedur: Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Segmen ini menganalisis secara kritis integrasi substansi dan prosedur dalam lanskap hukum pidana Indonesia kontemporer, utamanya pasca-disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yakni UU No. 1 Tahun 2023. Kajian ini menghadirkan sebuah sistem pemidanaan berlapis (multidoelmatigheidsstelsel) yang mengombinasikan pidana penjara, denda yang bersifat fleksibel (sistem kategori), sanksi sosial, kerja sosial, dan mekanisme restorative justice (keadilan restoratif).
Pendekatan ini merefleksikan pergeseran paradigma dari retributive justice (keadilan retributif) menuju penekanan pada keadilan substantif (substantive justice) tanpa mengesampingkan kepastian hukum (rechtszekerheid). Dalam konteks ini, penentuan pidana mengadopsi prinsip-prinsip penjatuhan pidana yang proporsional, di mana hakim memiliki diskresi yang lebih luas dalam mempertimbangkan berat perbuatan, niat pelaku (mens rea), dampak terhadap korban, dan efek preventif (baik generale preventie maupun speciale preventie). Adapun rujukan normatif yang relevan dalam kajian ini mencakup:
- Pasal 59–64 KUHP Baru: Ketentuan-ketentuan ini secara substansial mengatur pedoman pemidanaan hakim dan jenis-jenis sanksi alternatif, bukan hanya pidana penjara. Pasal-pasal ini menjadi landasan yuridis bagi penerapan pidana yang berorientasi pada tujuan.
- KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981): Pasal-pasal awal KUHAP, seperti Pasal 4-6, secara fundamental mengatur lingkup kewenangan penyidik dan penuntut umum, serta prinsip-prinsip dasar proses peradilan pidana, yang memastikan mekanisme penegakan hukum berjalan secara adil (due process of law), transparan, dan akuntabel.
Kasus-kasus aktual seperti tindak pidana kekerasan seksual (yang diatur lebih komprehensif dalam UU TPKS dan beberapa pasal spesifik dalam KUHP Baru, bukan hanya Pasal 285 KUHP lama), korupsi ringan, dan cybercrime lintas negara menjadi contoh empiris nyata penerapan sinergi norma substantif dan prosedural ini.
Pada hakikatnya, hukum pidana tidak dapat berfungsi secara optimal jika substansi dan prosedur berjalan secara dikotomis. KUHP Baru mengatur norma materiil secara proporsional dan kontekstual, sementara KUHAP memastikan mekanisme penegakan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Integrasi ini membentuk satu ekosistem hukum pidana yang kohesif, selaras dengan paradigma ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir) dan visi Indonesia yang berdaulat (cita-cita luhur penegakan hukum nasional yang humanis). Hukum tidak lagi sekadar menghukum (punitif), tetapi juga memulihkan (reparatif), melindungi korban (victim protection), dan menjaga kepentingan sosial secara menyeluruh.
Dalam ranah penegakan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma yang signifikan. Model retributif klasik yang cenderung berfokus pada pembalasan murni melalui privasi kemerdekaan (pemenjaraan) sebagai satu-satunya instrumen sanksi, kini dinilai kurang adaptif terhadap kompleksitas social harm kontemporer. Ambil contoh delicta (tindak pidana) korupsi atau penyalahgunaan aset negara; pendekatan pemenjaraan tunggal sering kali mengabaikan aspek fundamental pemulihan kerugian finansial publik (restitutio in integrum) dan kegagalan membongkar arsitektur mens rea kolektif di balik struktur korporasi yang kompleks.
KUHP baru, atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, merefleksikan orientasi utilitas (kemanfaatan) dan restorasi (pemulihan). Esensi filosofis ini termanifestasi dalam sistem pemidanaan yang bersifat multidimensional, dan prinsip-prinsip yang dimaksud sesungguhnya tersebar dalam bab-bab lain KUHP baru:
- Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023 secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan yang mencakup orientasi preventif, korektif, dan restoratif, bukan sekadar pembalasan.
- Pemidanaan Berlapis dan Sanksi Lain: KUHP baru memperkenalkan spektrum sanksi yang lebih luas daripada sekadar pidana penjara. Hal ini mencakup pidana pokok, pidana tambahan (termasuk restitusi), dan tindakan.
- Pertanggungjawaban Korporasi: Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana badan hukum (corporate criminal liability) diatur secara spesifik dalam Pasal 116 hingga Pasal 123 KUHP baru, memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap jaringan korupsi dalam struktur kompleks, bukan hanya menyasar individu pelaku.
- Restitutio in Integrum dan Pengawasan: Mekanisme restitusi dan pengawasan (pidana pengawasan) diakomodasi sebagai bagian integral dari sistem sanksi, yang selaras dengan adagium hukum ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum), menekankan fungsi hukum untuk menciptakan ketertiban dan pemulihan nyata di masyarakat.
Pendekatan ini menunjukkan raison d’être (alasan keberadaan) KUHP baru untuk beralih dari lex talionis (hukum balas dendam) menuju pendekatan modern yang mengedepankan efektivitas pemulihan kerugian dan pencegahan (prevention).
Inovasi Paradigma Penegakan Hukum Pidana Indonesia: Dari Retributif Menuju Restoratif
Salah satu signifikan inovasi dalam lanskap hukum pidana Indonesia kontemporer, yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), adalah pergeseran fundamental paradigma dari pendekatan retributif (pembalasan) menuju pendekatan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi sanksi. Transformasi ini mengafirmasi adagium hukum summum ius summa iniuria, yang mengingatkan bahwa penerapan hukum yang kaku secara ekstrem justru dapat mencederai keadilan.
Dalam konteks tindak pidana tertentu, seperti pelanggaran ringan (minieme delicten), penganiayaan sederhana, atau perkara yang melibatkan anak (jeugdcriminaliteit), sistem hukum kini secara eksplisit mendorong mekanisme penyelesaian berbasis pemulihan. Hal ini direalisasikan melalui proses mediasi penal (penal mediation), pengembalian kerugian (restitution), atau pelaksanaan kerja sosial.
Secara normatif, landasan filosofis dan implementatif restorative justice dalam KUHP Baru secara pokok diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal-pasal ini, bersama dengan ketentuan mengenai pedoman pemidanaan, menekankan prinsip oportunitas berbasis keadilan restoratif. Pendekatan ini juga diperkuat oleh sinkronisasi dengan KUHAP Baru, yang mengakui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, serta jaminan partisipasi dan perlindungan hak-hak korban yang lebih komprehensif, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan-ketentuan seperti Pasal 143 dan Pasal 144 KUHAP.
Substansi ini merefleksikan prinsip ultimum remedium, di mana pidana penjara harus menjadi pilihan terakhir, setelah alternatif sanksi dan mekanisme pemulihan diupayakan secara maksimal. Pendekatan ini secara subtil menegaskan bahwa strafrecht (hukum pidana) tidak semata-mata berfungsi sebagai punitif (menghukum), melainkan untuk merekonstruksi keseimbangan sosial (social equilibrium) dan mengembalikan martabat para pihak yang terlibat, sejalan dengan tujuan mulia keadilan substantif.
Pergeseran Paradigma Hukum Pidana
Hukum pidana Indonesia tengah mengarungi fase transformatif yang substansial. Momentum krusial ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP Baru), yang keduanya efektif berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Transformasi ini melampaui sekadar pembaruan redaksional pasal-pasal; ia merupakan sebuah rekonstruksi konseptual yang fundamental, menekankan pergeseran paradigma (paradigm shift): dari model hukum yang cenderung represif dan pelaku-sentris (offender-centric) menuju pendekatan yang lebih preventif, restoratif-integratif, dan masyarakat-sentris (community-centric).
KUHP lama, warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht), didominasi oleh nuansa positivisme hukum yang menekankan kepatuhan formal dan sanksi retributif (pembalasan). Dalam kerangka ini, hukum diposisikan secara instrumental sebagai aparatus kontrol sosial (instrument of social control), sementara dimensi korban, konteks sosiologis, dan aspek rehabilitasi jarang menjadi pertimbangan substantif. Sanksi pidana bersifat limitatif, umumnya terbatas pada pidana penjara, kurungan, dan denda, yang sering kali menimbulkan antinomi antara kepastian hukum formal (legal certainty) dengan tuntutan keadilan substantif (substantive justice) dan relevansi sosial.
Sebaliknya, KUHP Nasional mengintroduksi spektrum subjek hukum yang lebih luas, mencakup entitas modern seperti korporasi, serta memberikan perlindungan afirmatif bagi kelompok rentan. Objek hukum pun diekspansi, meliputi perlindungan hak asasi manusia (HAM), martabat individu (dignity), lingkungan hidup, kesusilaan, hingga ruang digital. Perbuatan pidana turut mengadopsi tipologi kejahatan struktural dan nonfisik, termasuk kekerasan berbasis relasi kuasa dan kejahatan siber.
Sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional diorientasikan secara lebih humanis dan multi-modal, memperkenalkan jenis sanksi alternatif seperti rehabilitasi, kerja sosial, larangan tertentu, restitusi, dan pemulihan korban sebagai pidana pokok atau tambahan. Dengan demikian, adagium klasik jus restaurativum ante jus retributivum—di mana keadilan restoratif didahulukan sebelum keadilan retributif (pembalasan)—menemukan relevansi kontemporer dan aktualisasinya dalam sistem hukum pidana di Indonesia, menegaskan primasi pemulihan hubungan sosial di atas pembalasan semata.
Transformasi Epistemologis Hukum Pidana: Dari Retributif Menuju Keadilan Holistik
Paradigma hukum pidana kontemporer yang diintroduksi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai sebuah pergeseran epistemologis yang fundamental. Negara, dalam kerangka normatif ini, mereposisi perannya. Eksistensi negara tidak lagi termanifestasi semata-mata sebagai algojo normatif yang menerapkan sanksi pidana secara rigid, melainkan berevolusi menjadi mediator, fasilitator reintegrasi sosial, dan pelindung hak asasi manusia. Visi ini tercermin dalam spektrum jenis pidana yang lebih beragam, termasuk pidana kerja sosial dan pengawasan (Pasal 65), yang mengindikasikan orientasi pada pemulihan ketimbang pembalasan.
Integrasi substansiil KUHP Baru dengan lex specialis terkait—seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 22 Tahun 2022), UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022), UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)—membentuk sebuah ekosistem hukum pidana yang adaptif, futuristik, dan kohesif, mengakomodasi kompleksitas delik modern.
Secara filosofis, landasan konseptual ini dibedakan secara tegas dari paradigma kolonial (ius poenale warisan Belanda). Ia berdiri di atas pilar-pilar pembaruan yang menekankan pada nilai-nilai ke-Indonesia-an. Konsep ius integrum nusantara (hukum yang terintegrasi untuk nusantara) menjadi basis etis-nasional. Adagium hukum klasik “salus populi suprema lex esto” (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) diinternalisasi, menegaskan bahwa tujuan utama penegakan hukum adalah kesejahteraan dan perlindungan masyarakat secara utuh, bukan sekadar kepastian hukum formalistik.
Melalui pendekatan holistik ini, hukum pidana ditegaskan kembali sebagai instrumen pembangunan moral, sosial, dan budaya bangsa, sejalan dengan prinsip ultima ratio dalam penegakan hukum pidana.
Transformasi Substansi: Mental Map KUHP Baru dalam Perspektif Sistematika Hukum
Metamorfosis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU No. 1/2023) dapat dipahami melalui tiga spektrum analisis fundamental, yakni level normatif, substantif, dan sistemik. Ketiga lapisan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan membentuk bangunan hukum pidana modern yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial secara simultan, yaitu:
Pertama, pada level normatif, transformasi paling nyata tercermin dalam rekonstruksi arsitektur pasal, pembaruan diksi dan sintaksis bahasa hukum, serta desain mekanisme pemidanaan yang lebih komunikatif. Bahasa hukum yang lebih presisi dan sistematika pasal yang konsisten ditujukan untuk memperkuat rechtszekerheid sekaligus meminimalkan ruang multitafsir. Dengan demikian, norma tidak hanya bersifat mengikat, tetapi juga dapat dipahami dan diinternalisasi secara rasional oleh hakim, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Pergeseran paradigma penyelesaian perkara terefleksikan melalui pengakuan eksplisit terhadap keadilan restoratif (restorative justice), khususnya dalam pengaturan tindak pidana ringan sebagaimana Pasal 521 dan ketentuan terkait. Orientasi pemulihan korban ditegaskan lebih jauh dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 1/2023, yang mewajibkan pertimbangan kerugian akibat tindak pidana, termasuk restitusi, sebagai bagian integral dari proses pemidanaan. Ketentuan ini menandai afirmasi normatif atas hak korban (slachtofferzorg) dalam sistem peradilan pidana nasional.
Kedua, pada level substantif, KUHP Baru menampilkan reorientasi filosofis yang signifikan dari paradigma retributif semata menuju pendekatan trimatra yang mengintegrasikan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Subjek hukum diperluas tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup entitas kolektif seperti korporasi, sejalan dengan kompleksitas relasi sosial dan ekonomi modern. Objek perlindungan hukum pun melampaui kepentingan negara dan harta benda, merambah pada martabat manusia, hak asasi, lingkungan hidup, serta ruang digital. Sementara itu, konsepsi perbuatan pidana tidak lagi dibatasi pada tindakan fisik, melainkan mencakup kejahatan nonfisik dan struktural, selaras dengan adagium ubi societas ibi ius. Unsur kesalahan dipahami secara lebih komprehensif melalui penilaian niat (dolus), kelalaian (culpa), dan tanggung jawab sosial, sehingga pemidanaan menjadi lebih proporsional dan kontekstual. Fleksibilitas sanksi yang diperkenalkan—mulai dari rehabilitasi hingga reintegrasi sosial—menegaskan pergeseran menuju pendekatan multi-modal punishment yang adaptif dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata pembalasan.
Ketiga, pada level sistemik, KUHP Baru menegaskan dirinya sebagai simpul sentral (nodal point) dalam ekosistem hukum pidana nasional yang terintegrasi. Kodifikasi ini tidak diposisikan sebagai norma yang berdiri sendiri (stand alone statute), melainkan sebagai living system yang berinteraksi secara dinamis dengan KUHAP, undang-undang sektoral, yurisprudensi, serta prinsip-prinsip konstitusional. Integrasi normatif dengan rezim hukum khusus—seperti perlindungan anak, kekerasan seksual, tindak pidana korupsi, lingkungan hidup, dan kejahatan siber—mencerminkan penerapan asas lex specialis derogat legi generali secara konsisten, sekaligus meneguhkan KUHP Baru sebagai ius commune hukum pidana nasional.
Pada aras penegakan, pendekatan sistemik ini menggeser peran negara dari sekadar punitive authority menjadi regulatory mediator yang menjaga keseimbangan antara kepentingan publik, perlindungan hak individu, dan ketertiban sosial. KUHP Baru, dalam koherensi dengan KUHAP Baru, membangun relasi fungsional antara norma materiil dan hukum acara pidana, sehingga prinsip due process of law tidak berhenti sebagai deklarasi normatif, tetapi bekerja secara operasional dalam setiap tahapan proses peradilan. Mekanisme pemidanaan yang fleksibel, alternatif penyelesaian perkara, serta penguatan posisi korban dan kelompok rentan menunjukkan bahwa sistem hukum pidana kini dirancang untuk menghasilkan keadilan substantif (substantive justice), bukan sekadar kepastian prosedural.
Lebih jauh, dimensi sistemik KUHP Baru juga bersifat reflektif dan prospektif. Ia membuka ruang koreksi konstitusional melalui mekanisme judicial review, menandakan bahwa kodifikasi pidana modern tidak menutup diri terhadap dinamika nilai dan kritik publik. Dalam kerangka ini, hukum pidana tidak lagi dipahami sebagai bangunan normatif yang beku, melainkan sebagai proses berkelanjutan (law in motion), yang senantiasa diuji oleh realitas sosial, perkembangan teknologi, dan tuntutan hak asasi manusia. Dengan demikian, kebaharuan KUHP Baru terletak bukan hanya pada perumusan pasal, tetapi pada desain sistemiknya yang adaptif, responsif, dan berorientasi jangka panjang.
Secara keseluruhan, integrasi level normatif, substantif, dan sistemik menegaskan bahwa KUHP Baru merepresentasikan transformasi hukum pidana yang bersifat paradigmatik. Kodifikasi ini mengartikulasikan pergeseran dari hukum pidana kolonial yang represif menuju sistem nasional yang humanis, proporsional, dan berkeadilan sosial, selaras dengan adagium salus populi suprema lex esto—bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi. Dalam kerangka inilah KUHP Baru dapat dibaca sebagai fondasi strategis bagi pembangunan hukum pidana Indonesia yang modern, konstitusional, dan berkelanjutan.
Transformasi Substansi: Refleksi Konstitusional atas Uji Materiil KUHP dan KUHAP di Mahkamah Konstitusi
Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru telah memicu gelombang constitutional review yang terpantau melalui sistem Tracking Perkara Mahkamah Konstitusi hingga Januari 2026. Sedikitnya dua belas permohonan uji materiil teregistrasi, mencerminkan kegelisahan normatif atas keseimbangan antara ambisi kodifikasi nasional dan jaminan hak konstitusional warga negara. Gugatan tersebut terbagi ke dalam tiga klaster utama: perkara gabungan yang menguji koherensi antara norma materiil dan hukum acara pidana, perkara khusus terhadap pasal-pasal strategis dalam KUHP Baru, serta perkara tambahan yang menyoroti isu kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi digital.
Dalam klaster pertama, permohonan uji materiil terhadap kedua undang-undang secara simultan menempatkan prosedur penyidikan sebagai titik kritis relasi antara law enforcement dan due process of law. Klaster kedua, yang secara khusus menyasar KUHP Baru, memperlihatkan spektrum keberatan yang luas—mulai dari perumusan delik penggelapan dan tindak pidana korupsi, jaminan hak pendampingan hukum, kriminalisasi penghinaan terhadap lembaga negara, pengaturan delik kesusilaan, hingga eksistensi pidana mati. Sementara itu, klaster ketiga mempertegas sensitivitas hukum pidana modern terhadap ruang kebebasan sipil, terutama melalui pengujian pasal penyebaran berita bohong, penghinaan ringan, serta kewenangan penyitaan data elektronik tanpa izin awal pengadilan.
Berlakunya KUHP Baru dan KUHAP Baru memicu gelombang uji materiil yang terpantau melalui sistem Tracking Perkara Mahkamah Konstitusi per Januari 2026. Sejauh ini, terdapat 12 perkara yang menyoroti isu substansial dan prosedural:
- Perkara Gabungan (KUHP & KUHAP Baru): Nomor 1 & 2/PUU-XXIV/2026, permohonan uji materi oleh perseorangan terkait prosedur penyidikan dan pasal-pasal terkait KUHP.
- Perkara Khusus KUHP Baru: Nomor 282/PUU-XXIII/2025 (penggelapan dan tindak pidana korupsi), 5/PUU-XXIV/2026 (hak advokat), 7/PUU-XXIV/2026 (penghinaan presiden), 8/PUU-XXIV/2026 (pasal zina dan kohabitasi), 9/PUU-XXIV/2026 (hukuman mati).
- Perkara Tambahan KUHP & KUHAP Baru: Nomor 10, 11 (pengujian pasal hoaks dan penghinaan ringan), 12/PUU-XXIV/2026 (penyitaan data elektronik tanpa izin pengadilan).
Fenomena tersebut mengafirmasi adagium ubi ius incertum, ibi ius nullum: ketidakpastian rumusan norma berpotensi menegasikan hukum itu sendiri. Persidangan di Mahkamah Konstitusi menjadi arena dialektika antara kebutuhan menjaga ketertiban umum dan perlindungan kebebasan sipil, khususnya dalam pengujian pasal-pasal yang bersifat open textured norms. Ketegangan ini tampak nyata pada perdebatan mengenai delik penghinaan dan diseminasi informasi yang berpotensi menimbulkan chilling effect, serta pada perluasan kewenangan penyidik dalam mengakses dan menyita data elektronik.
Dengan demikian, rangkaian uji materiil ini tidak dapat dipahami semata sebagai resistensi terhadap pembaruan hukum pidana, melainkan sebagai bagian inheren dari proses konsolidasi negara hukum konstitusional. Mahkamah Konstitusi, dalam posisinya sebagai the guardian of the constitution, dihadapkan pada tugas menjaga agar ius constitutum hasil kodifikasi baru tetap selaras dengan prinsip lex certa, lex stricta, dan perlindungan hak asasi manusia. Di titik inilah masa depan KUHP dan KUHAP Baru diuji: apakah ia akan berkembang sebagai instrumen ketertiban yang berkeadilan, atau justru terperangkap dalam formalisme normatif yang menggerus kebebasan sipil secara subtil.
Pemberlakuan lex specialis baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) secara inheren memicu gelombang judicial review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pemantauan melalui sistem Tracking Perkara Mahkamah Konstitusi hingga Januari 2026 mengonfirmasi dinamika tersebut, dengan teregistrasinya sejumlah perkara yang menguji konstitusionalitas norma-norma baru dalam kerangka transisi kodifikasi hukum pidana nasional.
Perkara-perkara yang bergulir di judicial forum ini merepresentasikan spektrum keberatan yang mencakup dimensi prosedural dan substantif sekaligus. Pada ranah hukum acara, pengujian terhadap KUHAP Baru—sebagaimana tercermin dalam perkara Nomor 2/PUU-XXIV/2026—memusatkan perhatian pada norma penyidikan yang dinilai berpotensi menggerus hak konstitusional warga negara, khususnya terkait kewenangan penyitaan data elektronik tanpa izin awal pengadilan. Isu ini mengemuka sebagai titik krusial relasi antara efektivitas penegakan hukum dan prinsip due process of law dalam lanskap digital.
Sementara itu, pengujian terhadap KUHP Baru menyoroti delik-delik materiil yang menyentuh jantung kebebasan sipil dan moralitas publik. Gugatan terhadap pasal penghinaan terhadap Presiden—seperti Pasal 218 KUHP Baru—dipersepsikan berpotensi menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi (freedom of expression) dan kritik politik. Di sisi lain, kriminalisasi perbuatan zina dan kohabitasi memunculkan perdebatan tentang batas legitimasi intervensi negara terhadap ruang privat warga negara. Tidak kalah fundamental, pengujian atas eksistensi pidana mati merefleksikan perdebatan klasik mengenai inhuman punishment dan hak untuk hidup (right to life) sebagai hak asasi yang bersifat non-derogable.
Perkara-perkara yang bergulir di judicial forum ini mencakup isu-isu substansial dan prosedural krusial, antara lain:
- Pengujian a quo KUHAP Baru: Terdapat permohonan yang secara spesifik menyasar aspek prosedural dalam KUHAP Baru, sebagaimana teregistrasi dalam perkara Nomor 2/PUU-XXIV/2026. Fokus pengujian ini meliputi norma yang dianggap berpotensi mengancam hak konstitusional warga negara dalam proses peradilan pidana, seperti isu penyitaan data elektronik tanpa prerogative izin pengadilan yang adekuat.
- Pengujian a quo KUHP Baru: Beberapa permohonan terfokus pada delik-delik materiil dalam KUHP Baru. Isu krusial yang di-challenge antara lain:
- Delik Terhadap Harkat dan Martabat Presiden: Pengujian terhadap pasal yang mengkriminalisasi “penghinaan presiden” (misalnya, Pasal 218 KUHP Baru), yang dipersepsikan mengancam kebebasan berekspresi (freedom of expression) dan berpotensi menjadi instrumen kriminalisasi kritik politik.
- Kriminalisasi Ranah Privat: Permohonan terkait pasal-pasal yang mengatur perbuatan zina dan kohabitasi, menyoal intervensi negara terhadap ruang privat warga negara.
- Ketentuan Pidana Mati: Pengujian terhadap eksistensi hukuman mati, menyangkut isu inhuman punishment dan hak asasi manusia yang paling fundamental, yakni hak untuk hidup (right to life).
Fenomena constitutional complaint ini menegaskan kembali adagium ubi ius incertum, ibi ius nullum: ketidakpastian norma berpotensi meniadakan hukum itu sendiri. Rumusan delik yang bersifat open textured atau berisiko obscuur libel dalam fase transisi kodifikasi dapat menjadi ancaman serius bagi asas legalitas dan kepastian hukum yang berkeadilan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai arena dialektika epistemologis antara kebutuhan menjaga ketertiban umum (public order) dan kewajiban konstitusional untuk melindungi kebebasan sipil (civil liberties). Putusan-putusan yang lahir dari perkara-perkara tersebut akan menjadi penentu arah, watak, dan legitimasi penegakan hukum pidana Indonesia ke depan—apakah bergerak menuju sistem hukum yang proporsional dan humanis, atau justru terjebak dalam formalisme normatif yang berpotensi membatasi ruang kebebasan secara subtil.
Analisis Kritis Rezim Penyitaan Data Elektronik dalam KUHAP Baru
Wacana hukum pidana Indonesia tengah berada dalam fase transformasi fundamental seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru). Salah satu isu yang paling banyak menyita perhatian publik dan komunitas akademik adalah pengaturan mengenai penyitaan data elektronik, khususnya Pasal 235 KUHAP Baru yang mengafirmasi alat bukti elektronik sebagai alat bukti mandiri. Norma ini dipahami sebagai bagian dari modernisasi hukum acara pidana dalam rangka menyesuaikan diri dengan realitas masyarakat digital dan kebutuhan pembuktian berbasis teknologi.
Namun demikian, narasi yang berkembang—seolah-olah KUHAP Baru memberikan diskresi absolut kepada penyidik untuk melakukan penyitaan data elektronik dalam keadaan mendesak tanpa izin pengadilan—memerlukan pembacaan yang lebih cermat dan proporsional. Secara normatif, pengakuan bukti elektronik dimaksudkan untuk memperluas instrumen pencarian materiele waarheid, bukan untuk menegasikan prinsip-prinsip fundamental due process of law. KUHAP Baru tetap menempatkan penyitaan sebagai tindakan yang bersifat intrusif dan karena itu harus tunduk pada batasan hukum, asas kehati-hatian, serta mekanisme pertanggungjawaban yudisial.
Meski demikian, sejumlah contentious issues tetap mengemuka dalam praktik dan diskursus konstitusional. Pertama, ketiadaan batasan operasional yang limitatif atas frasa “keadaan mendesak” (urgent circumstances) menimbulkan kekhawatiran akan munculnya excessive discretion di tangan penyidik. Ketidakjelasan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip lex certa, yang menuntut norma hukum dirumuskan secara jelas dan dapat diprediksi. Kedua, absennya pengawasan yudisial di muka (prior judicial oversight) dalam konteks tertentu memunculkan risiko pelanggaran hak privasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Ketiga, penyitaan data elektronik yang bersifat masif dan permanen di ruang siber berpotensi berbenturan dengan prinsip right to be forgotten, sehingga secara doktrinal seharusnya diposisikan sebagai ultimum remedium dan dilaksanakan berdasarkan prinsip proporsionalitas.
Beberapa gugatan (contentious issues) yang mengemuka mencakup:
- Ketiadaan Batasan Operasional (Lack of Operational Boundaries): Istilah “mendesak” (urgent circumstance) tidak didefinisikan secara limitatif (limitatively defined) dalam norma undang-undang. Hal ini berpotensi membuka ruang bagi diskresi penyidik yang eksesif (excessive discretion), yang bertentangan dengan prinsip lex certa (hukum harus jelas).
- Pelanggaran Due Process of Law: Penggeledahan ruang digital tanpa adanya pengawasan yudisial awal (prior judicial oversight) berpotensi melanggar hak privasi konstitusional warga negara (constitutional rights to privacy). Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai keseimbangan antara efisiensi penegakan hukum dan perlindungan hak individu.
- Benturan dengan Right to be Forgotten: Penyitaan data elektronik sering kali menyentuh informasi yang bersifat sangat pribadi, sensitif, dan permanen dalam ruang siber. Oleh karena itu, tindakan penyitaan seharusnya menjadi ultimum remedium (upaya terakhir) dan tunduk pada prinsip proporsionalitas (proportionality principle).
Perbandingan dengan KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) memperlihatkan pergeseran paradigma yang signifikan. Jika sebelumnya penguatan kewenangan penyidik diimbangi secara ketat oleh mekanisme izin pengadilan sebagai bentuk judicial oversight, KUHAP Baru memperkenalkan model post-factum authorization dalam konteks tertentu. Model ini memang diklaim meningkatkan efisiensi penegakan hukum (effectiveness of law enforcement), tetapi sekaligus menguji daya tahan perlindungan civil liberties dalam negara hukum konstitusional. Dalam kerangka ini, asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali tidak hanya relevan bagi hukum pidana materiil, tetapi juga menuntut kejelasan, pembatasan, dan akuntabilitas dalam hukum acara pidana demi menjamin rechtszekerheid dan legitimasi penegakan hukum di era digital.
Tinjauan Kritis Transformasi Hukum Pidana: Dari Konsepsi Doktriner menuju Adaptabilitas Sistemik
Wacana hukum pidana Indonesia memasuki fase transformatif pasca-efektivitas penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru (UU No. 20 Tahun 2025). Pergeseran ini menandai sebuah metamorphosis iuris, yakni peralihan dari paradigma retributif klasik yang menekankan pembalasan, menuju kerangka holistik yang mengedepankan keadilan substantif (substantive justice), kemanfaatan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum pidana tidak lagi diposisikan semata sebagai instrumen koersif negara, melainkan sebagai mekanisme normatif yang adaptif terhadap kompleksitas sosial, teknologi, dan nilai konstitusional.
Dalam ranah hukum acara pidana, isu pembuktian dan penyitaan data elektronik menjadi titik krusial dalam diskursus kontemporer. Secara normatif, Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP Baru menegaskan alat bukti elektronik sebagai alat bukti mandiri, melengkapi rezim pembuktian konvensional yang sebelumnya diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP Lama. Inovasi ini tidak hanya mengafirmasi perkembangan teknologi informasi, tetapi juga mengintegrasikan praktik pembuktian modern ke dalam sistem hukum acara pidana nasional, yang sebelumnya bergantung pada instrumen sektoral seperti Undang-Undang ITE. Namun demikian, pengakuan ini menuntut kehati-hatian ekstra karena karakter data elektronik yang bersifat intangible, masif, dan berimplikasi langsung terhadap hak privasi. Rekonstruksi sistemik melalui KUHP Baru memberikan implikasi multi-dimensional:
- Fleksibilitas Sanksi bagi Aparat Penegak Hukum: KUHP Baru mengintroduksi double track system (sistem pemidanaan ganda) yang mengombinasikan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan. Pendekatan ini memberikan hakim ruang diskresi yang lebih luas dalam mengindividualisasi pidana, sehingga putusan mencerminkan proporsionalitas dan kontekstualisasi sosial, serta memfasilitasi tujuan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.
- Optimalisasi Perlindungan Korban dan Keadilan Restoratif: Filosofi restorative justice diarusutamakan. Meskipun narasi merujuk pada “Pasal 5, 35-42 KUHP Baru”, secara spesifik, Pasal 5 KUHP Baru memang memayungi penyelesaian perkara di luar jalur formal (diversi/keadilan restoratif) untuk tindak pidana tertentu. Ketentuan lain (misalnya dalam pasal-pasal terkait pemidanaan) memperkuat hak korban atas restitusi (ganti rugi), pemulihan sosial, dan partisipasi dalam proses peradilan, sebagai manifestasi dari adagium audi et alteram partem (mendengarkan pihak lain, termasuk korban).
- Respons terhadap Kriminalitas Modern: Integrasi norma-norma yang adaptif memungkinkan penegakan hukum yang lebih realistis terhadap kejahatan siber (cybercrime), kejahatan lingkungan, dan tindak pidana berbasis relasi kuasa, yang membutuhkan kerangka hukum yang lebih dinamis.
Secara konseptual, transformasi ini bukan sekadar revisi parsial, melainkan sebuah rekonstruksi arsitektur hukum pidana yang berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum (legal certainty), keadilan substantif (substantive justice), dan adaptabilitas sistemik (systemic adaptability).
Diskresi penyidik untuk melakukan penyitaan dalam keadaan mendesak tanpa izin pengadilan di muka harus dibaca secara sistemik, bukan sebagai kewenangan absolut. Secara doktrinal, mekanisme tersebut berkelindan dengan prinsip in flagrante delicto dan pengecualian terbatas dalam hukum acara pidana, sebagaimana tercermin dalam spirit pengaturan penyitaan pada KUHAP Baru. Namun, diskresi tersebut tetap mensyaratkan mekanisme kontrol pasca-penyitaan (post-factum judicial control) guna menjamin legalitas tindakan dan mencegah abuse of power. Tanpa batasan operasional yang jelas dan pengawasan yudisial yang efektif, perluasan kewenangan ini berpotensi bertentangan dengan asas lex certa dan prinsip due process of law sebagai fondasi negara hukum.
Pada tataran substantif, KUHP Baru menghadirkan implikasi filosofis dan pragmatis yang signifikan. Pengenalan double track system—yang mengombinasikan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan—memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi hakim untuk mengindividualisasi pemidanaan. Pendekatan ini memungkinkan penjatuhan sanksi yang proporsional, kontekstual, dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial pelaku, tanpa mengorbankan kepentingan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi bersifat mekanistik, melainkan reflektif terhadap kompleksitas motif, dampak sosial, dan kapasitas bertanggung jawab pelaku.
Lebih jauh, arus utama keadilan restoratif (restorative justice) memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Pasal 5 KUHP Baru membuka ruang penyelesaian perkara tertentu di luar jalur formal, sementara ketentuan pemidanaan menegaskan pentingnya restitusi, pemulihan sosial, dan partisipasi korban sebagai subjek keadilan. Pendekatan ini mencerminkan aktualisasi adagium audi et alteram partem, di mana proses peradilan tidak hanya mendengar negara dan pelaku, tetapi juga mengakui suara dan penderitaan korban sebagai bagian integral dari keadilan substantif.
Dalam konteks kriminalitas modern—seperti kejahatan siber, kejahatan lingkungan, dan tindak pidana berbasis relasi kuasa—integrasi norma dalam KUHP dan KUHAP Baru menunjukkan orientasi adaptif dan futuristik. Hukum pidana nasional dirancang untuk merespons dinamika sosial dan teknologi tanpa kehilangan pijakan pada prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, transformasi ini tidak dapat dipahami sebagai revisi parsial, melainkan sebagai rekonstruksi arsitektur hukum pidana secara sistemik, yang berupaya menyeimbangkan kepastian hukum (legal certainty), keadilan substantif (substantive justice), dan adaptabilitas sistemik (systemic adaptability) dalam satu kerangka normatif yang koheren.
Rekonstruksi Epistemologis KUHP Baru: Sebuah Ekosistem Keadilan Adaptif
Secara konseptual, kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai sebuah paradigma baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kodifikasi ini seyogianya dipahami sebagai sebuah jaringan normatif (normative network) yang terintegrasi, di mana setiap komponennya merefleksikan pergeseran fundamental dalam cara negara mengelola respons terhadap tindak pidana. Elemen-elemen kunci dalam ekosistem hukum ini meliputi:
- Subjek Hukum (Subjectum Juris): Spektrum subjek hukum pidana mengalami perluasan signifikan. Tidak hanya mencakup individu (natuurlijk persoon), baik anak maupun dewasa, KUHP baru secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 45 dan Pasal 46) dan pejabat publik (misalnya, dalam tindak pidana korupsi yang terintegrasi di dalamnya).
- Objek Hukum (Objectum Juris): Fokus perlindungan hukum melampaui kerugian material semata, merangkul nilai-nilai esensial seperti hak asasi manusia, martabat (misalnya, melalui delik penghinaan), lingkungan hidup, ruang digital, hingga kesusilaan, menegaskan prinsip ius constitutum yang responsif terhadap dinamika sosial.
- Perbuatan Pidana (Crimen): KUHP mengadopsi tipologi perbuatan pidana yang lebih komprehensif, meliputi tindakan fisik (actus reus), nonfisik (misalnya, kelalaian), tindakan berbasis relasi kuasa (yang sering terkait dengan kekerasan seksual), dan kejahatan siber (misalnya, Pasal 271-274).
- Sanksi (Sanctio) Multi-modal: Sistem pemidanaan bertransformasi dari retributif murni menuju pendekatan multi-modal (majemuk). Selain pidana penjara dan denda, KUHP memperkenalkan secara eksplisit pidana kerja sosial (Pasal 67), pidana pengawasan, rehabilitasi, restitusi bagi korban, dan larangan tertentu, sesuai amanat Pasal 64.
- Prinsip Filosofis (Principium Philosophicum): Narasi filosofis KUHP ditopang oleh pilar-pilar penting: Ius integrum nusantara (hukum yang terintegrasi dan berakar pada nilai lokal), jus restaurativum (keadilan restoratif) ante jus retributivum (sebelum keadilan retributif/pembalasan), dan adagium klasik salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi).
- Integrasi Normatif (Integratio Normativa): KUHP ini tidak berdiri sebagai menara gading. Ia dirancang sebagai undang-undang payung yang terhubung secara sistemik dengan berbagai undang-undang khusus (lex specialis), yurisprudensi, dan praktik penegakan hukum modern, memastikan koherensi sistem hukum pidana secara keseluruhan.
Peta konseptual (mental map) ini menegaskan bahwa KUHP Baru adalah sebuah ekosistem hukum yang hidup dan dinamis. Setiap elemen normatif, prosedural, dan filosofis saling terkait dalam relasi dialektis untuk membangun arsitektur keadilan yang manusiawi dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Secara reflektif, lex lata (hukum yang berlaku) dalam KUHP Baru menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia bukan sekadar mekanisme penghukuman (punitif), tetapi instrumen pembangunan masyarakat yang adil, manusiawi, dan harmonis. Pembaca dapat membayangkan KUHP Baru sebagai jaringan normatif yang saling terhubung, menyeimbangkan secara cermat antara kepastian hukum (rechtszekerheid), keadilan sosial (sociale rechtvaardigheid), perlindungan korban, dan rehabilitasi pelaku. Kebaharuan ini bersifat normatif, substantif, dan sistemik, menunjukkan bahwa kodifikasi hukum pidana adalah sebuah rekonstruksi menyeluruh, bukan sekadar modernisasi pasal secara parsial.
Dinamika judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal tahun 2026 secara apik menegaskan manifestasi dari living constitution dalam lanskap demokrasi hukum di Indonesia. Fenomena ini mengemuka melalui serangkaian permohonan uji materiil terhadap pasal-pasal krusial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku efektif, yaitu:
- Pasal Penghinaan (terhadap pemerintah/lembaga negara): diatur dalam Pasal 240 dan 241 KUHP Baru. Pasal-pasal ini sering menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap berpotensi mengkriminalisasi kritik dan bertentangan dengan asas kesetaraan di depan hukum (equality before the law).
- Pasal Penyebaran Berita Bohong: diatur dalam Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang sebelumnya mengatur hal ini telah dicabut oleh MK, namun ketentuan serupa kini termuat dalam KUHP Baru dan UU ITE No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE).
- Pasal Penyitaan Data Elektronik: Rujukan ini bersifat kontekstual. Penyitaan diatur dalam Pasal 39 KUHAP, namun alat bukti elektronik dan penyadapannya diatur secara spesifik dalam UU ITE (misalnya Pasal 31 UU ITE) dan undang-undang pidana khusus lainnya, karena KUHAP Baru belum ada.
- Pasal Hukuman Mati: KUHP Baru mengubah wajah pidana mati, menjadikannya sebagai pidana pokok yang bersifat alternatif dan bersyarat, bukan lagi wajib, serta sebagai pilihan terakhir (ultimum remedium)
Gugatan-gugatan tersebut, utamanya menyasar delik-delik terkait penghinaan terhadap pemerintah, penyebaran berita bohong, penyitaan data elektronik, dan eksistensi pidana mati, mengindikasikan bahwa kodifikasi hukum pidana nasional sedang menghadapi ujian konstitusional yang menuntut adanya keseimbangan fundamental antara efektivitas penegakan hukum (pro justitia) dan proteksi hak-hak asasi manusia (human rights protection). Proses check and balances yang dinamis ini esensial untuk memastikan agar instrumen hukum pidana senantiasa responsif terhadap realitas sosial dan perkembangan teknologi mutakhir, sembari menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif (justice for all).
Secara teleologis, KUHP Baru dan regulasi hukum acara pidana terkait merefleksikan visi hukum pidana yang humanis, futuristik, dan deterministik. Adagium klasik jus restaurativum ante jus retributivum secara eksplisit menegaskan prioritas pemulihan sosial dan kepentingan korban, mendahului pendekatan retributif semata. Sementara itu, adagium salus populi suprema lex esto dimaknai secara kontekstual, bahwa kepentingan publik tertinggi adalah mewujudkan kesejahteraan holistik bagi individu, korban, dan masyarakat luas. Sistem hukum pidana modern ini, yang mengintegrasikan filosofi pemidanaan, norma substantif, prosedur yudisial, dan adaptasi teknologi, menjadi fondasi konseptual, normatif, dan operasional yang inheren bagi arsitektur hukum Indonesia di masa mendatang.
Perlindungan Korban, Kearifan Lokal, dan Integrasi Global: Menyatukan Hukum, Budaya, dan Hak Asasi
Transformasi KUHP dan KUHAP Baru menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia: dari sistem pelaku-sentris dan represif warisan kolonial, menuju hukum humanis, proporsional, dan berbasis Pancasila. Reformasi ini menempatkan korban sebagai subjek hukum dengan hak pemulihan jelas melalui mekanisme restorative justice, sambil mengakomodasi kearifan lokal, norma sosial, dan perlindungan kelompok rentan—anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Pendekatan sistemik ini juga mengintegrasikan hukum pidana dengan standar internasional, termasuk konvensi HAM, pidana transnasional, dan cybercrime lintas negara, serta menegaskan tanggung jawab korporasi dalam pidana lingkungan dan ekonomi. Dengan struktur pasal yang jelas, sanksi fleksibel, mediasi, dan edukasi hukum sebagai bagian dari pencegahan, KUHP Baru menjadi instrumen hukum yang adaptif, restoratif, dan efektif—menghasilkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan sosial yang terpadu.
Paradigma Viktimologi dalam Transformasi Hukum Pidana Indonesia
Yurisprudensi dan doktrin hukum pidana modern mengafirmasi bahwa pendekatan retributif murni tidak lagi adekuat dalam merespons kompleksitas kejahatan. Esensi pembaruan hukum pidana nasional, yang terefleksi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), menandai pergeseran substansial dalam mengakui korban (victims) sebagai subjek hukum yang hak-haknya esensial untuk dilindungi.
Korban tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek statistik (entitas pasif) atau saksi prosedural sebagaimana inheren dalam paradigma hukum kolonial (geen straf zonder schuld, tiada pidana tanpa kesalahan, dengan fokus eksklusif pada pelaku). KUHAP Baru, secara eksplisit dalam bab-bab terkait, memberikan locus standi yang lebih kuat bagi korban untuk berpartisipasi aktif, termasuk hak untuk memperoleh informasi proses peradilan, menuntut restitusi, dan terlibat dalam mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Dalam konteks penegakan hukum yang progresif, restorative justice (keadilan restoratif) menjadi conditio sine qua non (syarat mutlak) dalam sistem peradilan pidana terpadu. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial (social healing) dan harmonisasi komunitas, beranjak dari sekadar pembalasan (retribution). KUHP Baru mengintroduksi prinsip ini secara fundamental melalui Pasal 5, mengamanatkan penerapan keadilan restoratif, terutama untuk tindak pidana ringan atau yang diancam pidana di bawah lima tahun, sebagai alternatif sanksi pidana formal.
Secara empiris, implementasi model pemulihan ini telah mengakar kuat dalam sistem peradilan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA mewajibkan diversi (pengalihan proses pidana ke luar pengadilan) pada tahap penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan mengedepankan mediasi, restitusi, dan keterlibatan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Ini merupakan manifestasi konkret dari adagium ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir), di mana kepentingan terbaik anak dan pemulihan korban menjadi prioritas fundamental.
Reformasi hukum pidana nasional menandai sebuah paradigma baru dalam kerangka sistematisasi hukum di Indonesia, mentransformasi pendekatan yang sebelumnya didominasi oleh nuansa kolonial. Inovasi fundamental ini secara eksplisit mengakui dan mengartikulasikan kearifan lokal (living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat) sebagai bagian inheren dari norma hukum positif, sebuah manifestasi dari adagium hukum ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum).
Pengakuan substansial terhadap living law ini tidak termaktub dalam Pasal 1–3, melainkan secara spesifik diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pasal ini membuka ruang bagi delik adat, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional, hak asasi manusia (human rights), dan kepentingan publik. Pengakuan ini bersifat kontekstual dan aplikatif, misalnya, dalam penyelesaian konflik agraria atau sengketa komunal yang dapat menggunakan mekanisme musyawarah adat dan sanksi sosial lokal sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan ini menunjukkan bagaimana hukum nasional berintegrasi secara harmonis dengan norma sosial lokal, membentuk ekosistem hukum yang kontekstual dan berakar pada budaya bangsa.
Selanjutnya, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (human rights protection) menjadi salah satu pilar utama pembaruan, yang terefleksi dalam kodifikasi tindak pidana tertentu, bukan pada rentang pasal 80–88 KUHP Baru yang secara historis (dalam KUHP lama) mengatur tentang daluwarsa penuntutan dan permufakatan jahat. KUHP Baru menekankan perlindungan kelompok rentan, termasuk anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, melalui bab-bab spesifik mengenai tindak pidana kesusilaan dan kejahatan seksual, yang juga diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sanksi yang diatur bersifat proporsional dan komprehensif, mencakup mekanisme rehabilitasi bagi pelaku dan korban. Pembaruan KUHAP memang menguatkan prinsip keseimbangan hak tersangka (due process of law) dan hak korban, termasuk hak akses bantuan hukum, hak pendampingan psikologis, dan partisipasi dalam proses peradilan. Prinsip audi et alteram partem (mendengarkan pihak lain secara seimbang) menjadi krusial dalam menjamin keadilan prosedural.
Harmonisasi Hukum Pidana Indonesia dalam Konteks Global dan Era Digital: Sebuah Telaah Normatif
Dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah mengonstruksi paradigma baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana Indonesia secara gradual mengalami proses adaptasi dan integrasi untuk merespons kompleksitas tindak pidana transnasional (transnational crimes). KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) menjadi salah satu manifestasi konkret dari upaya kodifikasi dan modernisasi hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan universalitas, tanpa mengeliminasi identitas lokal.
Perlu digarisbawahi, substansi mengenai tindak pidana lintas negara seperti cybercrime, perdagangan manusia (human trafficking), dan kejahatan ekonomi internasional tidak secara spesifik terakomodasi dalam Bab tersendiri yang merujuk pada Pasal 263 hingga Pasal 270 KUHP Baru. Pasal-pasal tersebut, dalam nomenklatur hukum pidana positif Indonesia, mengatur delik-delik terkait pemalsuan surat (Pasal 263-266) dan penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran (Pasal 263-264), yang merupakan delik konvensional.
Respons yuridis terhadap tindak pidana lintas negara dan kejahatan siber lebih banyak bersandar pada regulasi sektoral, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007). Integrasi ini merefleksikan prinsip universality dan kebutuhan akan kerja sama internasional (international cooperation) yang solid, selaras dengan ratifikasi perjanjian internasional, seperti Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) dan konvensi fundamental HAM lainnya.
Dalam aspek penegakan hukum, sistem pemidanaan kontemporer mengafirmasi pendekatan berlapis (multilayered criminal sanction system). Kejahatan siber yang bersifat transnasional tidak hanya disanksi melalui pidana penjara atau denda, tetapi juga melalui sanksi tambahan seperti restitusi, pemulihan aset (asset recovery), dan mekanisme rehabilitasi digital. Guna menopang efektivitas penegakan hukum, hukum acara pidana modern mengakui prosedur pembuktian elektronik dan keamanan data. Meskipun KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025) masih menjadi lex generalis, pengakuan bukti elektronik melalui UU ITE memastikan proses hukum berjalan secara deterministik, adil (justitia), dan adaptif terhadap lanskap digital yang terus berevolusi. Pendekatan holistik ini mencerminkan keseimbangan adil antara kepastian hukum (certitudo iuris) dan fleksibilitas diskresioner dalam menghadapi tantangan yudikatif di era disrupsi digital.
Secara sistemik, integrasi parsial antara norma hukum positif dan realitas sosial-yuridis merefleksikan dinamika pembaruan hukum pidana di Indonesia. Determinasi normatif kontemporer terejawantahkan melalui perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang bersifat prediktif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Aspek perlindungan korban, pengakuan hukum adat (kearifan lokal), serta restorasi harmoni komunal, menjadi imperatif dalam mencapai keadilan substantif (justice as social balance).
Pada aras institusional, akuntabilitas dan transparansi proses peradilan pidana diakomodasi melalui revisi prosedural dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, UU No. 20 Tahun 2025) dan penerapannya yang progresif, serta antisipasi terhadap implementasi penuh KUHP Baru. Pendekatan restoratif (restorative justice) menjadi paradigma kunci, memprioritaskan pemulihan kerugian korban (restitusi), rehabilitasi pelaku, dan reintegrasi sosial, sejalan dengan adagium ultimum remedium.
Empirisme penerapan model ini tampak dalam praktik mediasi penal, tuntutan restitusi bagi korban penipuan daring, serta pemidanaan korporasi yang melibatkan perampasan aset dan pengawasan probasi jangka panjang. Paradigma ini mentransformasi peran aparat penegak hukum dari sekadar eksekutor sanksi (mere application of law) menjadi fasilitator keadilan substantif. Peran aktif korban, masyarakat, dan komunitas lokal dalam criminal justice system semakin menguat, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 mengenai tata cara pemberian restitusi dan kompensasi. Penegasan yurisprudensial secara konsisten menunjukkan bahwa pengadilan modern mempertimbangkan pemulihan korban dalam penjatuhan sanksi pidana ekonomi, menegaskan bahwa tujuan pemidanaan melampaui sebatas retributif, menuju fungsi restoratif dan preventif.
Menuju Paradigma Humanis dan Integratif
Secara keseluruhan, substansi yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru, UU No. 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, UU No. 20 Tahun 2025) membentuk suatu arsitektur hukum pidana yang transformatif, berorientasi pada nilai-nilai integratif, adaptif, dan humanis. Sistem hukum ini dirancang secara saksama untuk mengakomodasi kompleksitas dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan tuntutan globalisasi, tanpa mengesampingkan penghormatan terhadap norma budaya serta kearifan lokal yang hidup di masyarakat (sesuai Pasal 2 KUHP Baru).
Pendekatan paradigmatik ini merefleksikan respons kritis terhadap warisan KUHP kolonial (Wetboek van Strafrecht), yang sering dinilai represif, formalistik, dan abai terhadap dimensi kemanusiaan korban maupun konteks sosiologisnya. Dalam kerangka Indonesia Integrated National Law (IIN), hukum pidana bertransisi fungsinya sebagai instrumen civilizationis (peradaban). Ia tidak semata-mata mengedepankan aspek retributif (teori pembalasan), melainkan juga menekankan fungsi preventif, rehabilitatif, dan restoratif, sebagaimana tersirat dalam Pasal 54 KUHAP yang menjamin hak-hak tersangka/terdakwa dan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Perlindungan komprehensif bagi korban, restorasi keadilan sosial, penghormatan terhadap living law (hukum yang hidup dalam masyarakat), dan integrasi prinsip-prinsip universal hukum (jus cogens) merupakan esensi fundamental dari pembaruan hukum pidana nasional. Konsepsi ini berakar kuat pada prinsip keseimbangan hak dan kewajiban (Pasal 3 dan Pasal 4 KUHP Baru tentang asas legalitas dan penerapan hukum yang menguntungkan), mengimplementasikan adagium hukum “**Fiat justitia ruat caelum **” (Tegakkan keadilan walau langit runtuh) dalam praksis penegakan hukum.
Meskipun kajian tersebut menggunakan terminologi non-normatif seperti “Segmen Ketiga” dan “four point determination”, substansi filosofisnya merepresentasikan misi multipihak dalam reformasi hukum pidana: dekolonisasi, rekodifikasi, demokratisasi, dan harmonisasi. Kerangka pikir ini berfungsi sebagai instrumen analisis dan implementasi, memastikan bahwa KUHP dan KUHAP mampu menjawab tantangan empiris dan normatif secara simultan, dengan tujuan akhir mencapai keadilan substansial, bukan sekadar keadilan prosedural belaka.
Modernisasi, Sanksi Alternatif, dan Korporasi: Menenun Hukum Pidana Masa Depan
Kajian selanjutnya menyoroti modernisasi hukum pidana Indonesia melalui KUHP dan KUHAP Baru, menempatkan teknologi dan kejahatan digital sebagai fokus utama, sekaligus memperluas spektrum sanksi dengan alternatif sosial, kerja sosial, dan rehabilitasi. Transformasi ini juga menegaskan tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana lingkungan, ekonomi, dan korupsi ringan, sejalan dengan praktik global dan standar internasional. Integrasi prosedur modern, mediasi, dan akses informasi hukum menegaskan hukum yang adaptif, prediktabel, dan restoratif, sementara harmonisasi dengan UU lain memastikan kepastian dan konsistensi. Segmen ini sekaligus menutup narasi reflektif dengan Super Master Table dan Mental Map KUHP Baru, memperlihatkan alur konseptual dari karakter hukum hingga buah keadilan substantif, perlindungan korban, dan kepatuhan global, menjadikan KUHP Baru instrumen hukum modern yang humanis, efektif, dan selaras Pancasila.
Transformasi Hukum Pidana Indonesia Menuju Era Digital dan Global
Salah satu pilar esensial dalam genealogi pembaruan hukum pidana di Indonesia bermanifestasi melalui adopsi paradigma modernisasi hukum dan prosedur, sebuah respons imperatif terhadap akselerasi era digital, kompleksitas ekonomi transnasional, dan globalisasi. KUHP Nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) secara eksplisit mengategorikan tindak pidana siber, ekonomi, dan tindak pidana lintas negara dalam bab-bab tersendiri, bukan pada pasal-pasal yang keliru dirujuk sebelumnya. Pengaturan ini terintegrasi secara sistematis dalam Buku Kedua KUHP, yang mencakup berbagai bentuk kejahatan kontemporer.
Paralel dengan substansi material, Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 2 Tahun 2025) yang baru disahkan telah mengintroduksi mekanisme pembuktian yang relevan dengan perkembangan teknologi. Instrumen normatif ini secara eksplisit mengakui kekuatan yuridis dari bukti digital, dokumen elektronik, dan transaksi lintas platform, yang sebelumnya bersifat abu-abu dalam ius constitutum (hukum yang berlaku) KUHAP lama. Transformasi ini mengarahkan hukum pidana nasional pada karakter yang lebih deterministik secara prosedural, di mana setiap alat bukti dan standar penuntutan diatur secara sistematis, namun tetap adaptif (futuristic and responsive) terhadap dinamika lex informatica.
Modernisasi ini juga mencakup aspek procedural due process, khususnya dalam administrasi peradilan. Inovasi seperti pemanggilan elektronik (e-summons), persidangan daring (e-litigation), dan penggunaan sistem pengajuan elektronik (electronic filing system) ditujukan untuk mencapai efisiensi (celerity of justice), meminimalkan biaya litigasi, dan memperluas akses keadilan. UU KUHAP baru secara fundamental menekankan bahwa efisiensi prosedural tidak boleh mengorbankan prinsip kehati-hatian (due process of law), transparansi (audi et alteram partem), dan perlindungan hak asasi manusia (hak-hak fundamental). Konvergensi antara efisiensi, keadilan substantif, dan kepastian hukum ini merefleksikan dimensi determinasi normatif dan institusional dalam four point determination Ius Integrum Nusantara.
Tinjauan Akademik atas Transformasi Sistem Pidana dalam KUHP Baru
Sejalan dengan proses modernisasi hukum pidana dan pergeseran paradigma global dari retributif (pembalasan) menuju pendekatan restorative dan rehabilitative justice, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mengintroduksi suatu sistem pemidanaan yang fleksibel, berlapis, dan berorientasi pada tujuan. Pendekatan ini secara eksplisit menyeimbangkan kebutuhan aspek represif (penjeraan) dengan fungsi preventif dan pemulihan, menegaskan prinsip bahwa pidana penjara seyogianya menjadi ultimum remedium (upaya terakhir).
Fleksibilitas ini terwujud melalui spektrum sanksi yang komprehensif, mencakup pidana pokok (denda, penjara, dll.), pidana tambahan (pencabutan hak, perampasan aset, pengumuman putusan hakim), serta pidana/tindakan alternatif (kerja sosial, pengawasan, restitusi, rehabilitasi psikososial). Rujukan normatif kunci terkait penerapan sanksi alternatif ini sebenarnya terkonsentrasi pada Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP Baru yang mengatur tentang pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, serta bab terkait tujuan dan pedoman pemidanaan (Pasal 51-53).
Terkait pelaku anak, pendekatannya diatur dalam undang-undang spesialis (lex specialis), yakni UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan prinsip fundamental diversi (pengalihan penyelesaian perkara) dan penekanan bahwa anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipidana. Pendekatan holistik ini mengafirmasi prinsip justice as social learning: pemidanaan bukan sekadar vindictive justice (pembalasan), melainkan diarahkan pada pemulihan keseimbangan tatanan sosial.
Dimensi reformasi ini semakin relevan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability). Kajian awal menyatakan KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) sama sekali tidak mengaturnya; pernyataan ini perlu diluruskan secara nuansatif. Secara eksplisit, KUHP Lama memang tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana secara umum. Namun, dalam perkembangan praktik hukum di Indonesia, badan hukum telah diakui sebagai subjek tindak pidana melalui berbagai undang-undang khusus (lex specialis) di luar KUHP, seperti UU Tindak Pidana Korupsi atau UU Pencemaran Lingkungan.
KUHP Baru mengisi kekosongan normatif dalam kodifikasi hukum pidana umum dengan secara tegas dan sistematis mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 45 hingga Pasal 50. Pasal-pasal ini memungkinkan korporasi, selain pengurusnya secara individu, untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Sanksi yang dapat dikenakan sangat beragam, meliputi pidana denda (kategori IV hingga VIII), perampasan aset, pencabutan izin usaha, dan kewajiban pemulihan kerugian publik. Integrasi sanksi korporasi ini menekankan aspek keadilan distributif dan penegasan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) dalam bingkai prinsip Ius Integrum Nusantara (hukum yang terpadu di Indonesia).
Praktik global (global best practices) menjadi salah satu pilar fundamental dalam arsitektur pembaruan hukum pidana nasional Indonesia, yang terejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan proyeksi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Adopsi prinsip-prinsip pidana korporasi, misalnya, merupakan sintesis eklektik dari sistem hukum common law (Anglo-Amerika) dan civil law (Eropa Kontinental). Pengaruh ini terlihat eksplisit dalam Pasal 45 ayat (1) KUHP Baru, yang secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana (legal subject of crime), bergeser dari paradigma konvensional yang hanya memfokuskan pada individu. Selain itu, checks and balances terhadap HAM diakomodasi melalui ratifikasi instrumen internasional, seperti Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang disahkan melalui UU No. 7 Tahun 2006 dan Konvensi Hak Anak (CRC). Pendekatan sinkretis ini, dengan mengusung adagium ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum), memastikan relevansi hukum pidana di era globalisasi untuk menangani kejahatan transnasional (transnational crimes), seperti kejahatan siber dan pencucian uang (money laundering), tanpa mengerdilkan akar budaya dan identitas nasional. Instrumen operasional seperti mekanisme kerja sama hukum internasional untuk perampasan aset lintas yurisdiksi (asset recovery) dan pengakuan yurisprudensi asing (foreign jurisprudence recognition) menjadi instrumen penegakan hukum yang sah dan kontekstual.
Menyongsong era society 5.0, integrasi teknologi dan penerapan sanksi alternatif memperkuat dimensi keadilan restoratif (restorative justice) dalam lex specialis tindak pidana tertentu maupun dalam KUHP Baru. Dalam konstelasi kejahatan siber (misalnya penipuan daring), KUHP Baru menyediakan pidana tambahan berupa kewajiban pembayaran restitusi dan kompensasi digital (Pasal 66-70 KUHP Baru) sebagai primum remedium, sementara pidana penjara menjadi ultimum remedium. Di ranah prosedural, KUHAP memproyeksikan penegasan prosedur pengawasan bukti elektronik (electronic evidence surveillance), pemanggilan daring, dan persidangan berbasis teknologi (e-court), sebagaimana disinggung dalam wacana perubahan sistem pembuktian. Pendekatan holistik ini merefleksikan keseimbangan antara determinasi normatif, responsivitas sosial, dan orientasi restoratif dalam kerangka four point determination sistem peradilan pidana terintegrasi di Indonesia.
Sistem hukum pidana kontemporer, utamanya pasca-kodifikasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), semakin relevan dalam merespons spektrum kejahatan modern seperti environmental crimes (kejahatan lingkungan) dan ancaman terhadap kesehatan publik, di mana social loss bersifat luas dan berdimensi jangka panjang. Berbeda dengan narasi terdahulu, kerangka normatif untuk pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum yang mandiri tidak terletak pada Pasal 88–91 KUHP, melainkan tersemat secara umum dalam Pasal 45 dan pasal-pasal terkait di Buku Kesatu KUHP Baru, serta diperkuat oleh regulasi sektoral seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sementara itu, narasi tentang lex specialis dalam hukum acara pidana—yang merujuk pada “KUHAP Baru” (belum disahkan, masih berupa Rancangan KUHAP atau RKUHAP)—mengindikasikan adopsi mekanisme penyidikan berbasis scientific evidence dan partisipasi ahli yang lebih kuat (seperti yang tersirat dalam Pasal 133 KUHAP saat ini). Dengan demikian, pemidanaan bergerak melampaui paradigma retributif murni (just deserts); ia berevolusi menjadi pendekatan trifungsi: preventif, represif, dan korektif, yang berupaya meminimalkan kerusakan sosial-ekologis dan menjamin accountability jangka panjang.
Integrasi sanksi alternatif (seperti pidana kerja sosial dalam Pasal 85 KUHP Baru), corporate criminal liability, dan adaptasi praktik global menunjukkan bahwa kodifikasi hukum pidana Indonesia berupaya menyatukan norma in abstracto, prosedur, dan realitas empiris. Sistem ini memadukan prinsip nullum delictum sine praevia lege poenali dengan lex mitior (asas undang-undang yang lebih ringan), perlindungan hak asasi manusia (human rights), dan mengimplementasikan keadilan restoratif. Dalam kerangka Ius Integrum Nusantara (hukum terpadu khas Indonesia), hukum pidana bukan sekadar instrumen ultima ratio negara untuk menghukum, tetapi menjelma sebagai instrumen civilizationis yang memulihkan keseimbangan sosial (social equilibrium), meregulasi perilaku entitas korporasi, dan menjembatani dimensi lokal-global secara kohesif.
Secara empiris, manifestasi hukum pidana modern di Indonesia kini bertransisi dari sekadar lex talionis (hukum pembalasan) menuju restitutio in integrum (pemulihan keadaan semula). Integrasi ini secara nyata terpotret dalam penanganan perkara korupsi sektor publik, kejahatan siber lintas yurisdiksi, serta delik lingkungan hidup oleh korporasi. Yurisprudensi kontemporer menunjukkan kecenderungan Judex Facti maupun Judex Juris untuk mengonvergensi sanksi pidana, restitusi bagi korban, dan pertanggungjawaban korporasi secara simultan—sebuah langkah yang merefleksikan doktrin Ius Integrum Nusantara yang bersifat adaptif dan futuristik.
Hal ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa kodifikasi dalam KUHP Nasional telah berhasil mengoperasionalisasi filosofi social defense yang responsif dan humanis. Modernisasi hukum, diversi sanksi, serta corporate liability bukan sekadar instrumen teknis legislasi, melainkan manifestasi dari architrave hukum masa depan. Di tengah arus globalisasi, paradigma ini memastikan sistem peradilan pidana kita tetap up-to-date terhadap dinamika digital dan kompleksitas sosio-ekonomi tanpa menanggalkan volksgeist (jiwa bangsa) yang menjadi akar keadilan substantif.
Sebagai penutup diskursus normatif-operasional ini, harmonisasi antara teknologi dan hukum haruslah dipandu oleh asas legalitas yang tidak kaku, melainkan yang bervisi restoratif. Fondasi ini menjadi pijakan krusial untuk melangkah pada pembahasan Segmen Kelima, di mana perlindungan hak asasi manusia, keadilan gender, dan pelestarian ekosistem akan disintesiskan ke dalam sebuah Mental Map hukum pidana Indonesia yang utuh—sebuah perjalanan dari akar normatif menuju buah keadilan yang visioner dan modern.
Perlindungan HAM, Gender, Anak, dan Lingkungan: Integrasi Responsif dalam KUHP dan KUHAP Baru
Dalam diskursus hukum kontemporer, UU No. 1 Tahun 2023 bukan sekadar kodifikasi formal, melainkan sebuah paradigm shift yang memanifestasikan filosofi Ius Integrum Nusantara. Hukum kini bertransformasi dari sekadar instrumen kekuasaan (macht) menjadi pengawal kemanusiaan yang responsif terhadap dinamika peradaban.
Perlindungan Hak Asasi Manusia tidak lagi diletakkan sebagai diskursus perifer, melainkan menjadi doktrin sentral melalui adopsi asas pro homine dalam setiap penegakan hukum. Hal ini terefleksi dalam mekanisme Restorative Justice (Keadilan Restoratif) yang mengedepankan pemulihan korban (victim-oriented) ketimbang sekadar pembalasan (retributive).
Secara normatif, keberpihakan terhadap Gender dan Anak dikristalisasi melalui redefinisi delik kesusilaan dan perlindungan pengasuhan. Misalnya, Pasal 452-454 KUHP Baru mempertegas perlindungan hak pengasuhan keluarga sebagai benteng utama tumbuh kembang anak. Sementara itu, perlindungan Lingkungan Hidup mengalami penguatan signifikan dengan mengintegrasikan sanksi bagi korporasi dan pemulihan ekosistem sebagai bagian dari green criminology yang selaras dengan amanat UU PPLH.
Struktur hukum ini menyerupai arbor iuris (pohon hukum) yang hidup: berakar pada Pancasila sebagai volksgeist, bertopang pada konstruksi normatif yang kokoh, dan beranting pada perlindungan kelompok rentan. Di sini, adagium Fiat Iustitia Pereat Mundus (keadilan harus ditegakkan walau dunia runtuh) telah berevolusi menjadi Fiat Iustitia Ne Pereat Mundus—keadilan ditegakkan agar dunia (dan kemanusiaan) tidak runtuh. Transformasi ini memastikan bahwa kepastian hukum (rechtssicherheit) berjalan beriringan dengan keadilan substantif, menciptakan ekosistem hukum yang tidak hanya certain (pasti) tetapi juga just (adil) dan future-proof.
Analisis komparasi pasal spesifik untuk memperkuat argumentasi pergeseran paradigma dari keadilan retributif ke keadilan yang responsif dan sistemik:
- Isu Lingkungan: Evolusi Pertanggungjawaban Korporasi
KUHP Baru secara progresif menggeser beban pidana lingkungan dari sekadar individu (natuurlijk persoon) ke entitas bisnis sebagai subjek hukum mandiri.
- KUHP Lama (WvS): Tidak mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana secara umum. Delik pencemaran atau perusakan lingkungan hanya menyasar pengurus secara individual (individual liability).
- KUHP Baru (UU No. 1/2023): Melalui Pasal 45 ayat (1), korporasi secara eksplisit diakui sebagai subjek tindak pidana.
- Analisis Akademik: Ini adalah manifestasi dari doktrin strict liability dan vicarious liability. Argumentasi ini memperkuat bahwa hukum pidana modern tidak lagi bersifat antroposentris semata, tetapi bergerak ke arah ecocentrism. Penegakan hukum terhadap korporasi bertujuan untuk pemulihan kerusakan lingkungan secara masif—sebuah implementasi dari asas polluter pays principle.
- Isu Gender: Redefinis Kejahatan Kesusilaan
KUHP Baru memperluas cakupan perlindungan gender dengan menggeser fokus dari moralitas publik ke perlindungan otonomi tubuh dan kehormatan individu.
- KUHP Lama: Pasal 284 tentang perzinaan (overspel) sangat terbatas dan hanya dapat diadukan oleh suami/istri yang terikat perkawinan yang tunduk pada Pasal 27 BW.
- KUHP Baru: Melalui Pasal 411, delik perzinaan diperluas maknanya namun tetap dijaga sebagai delik aduan absolut (absolute klachtdelict) guna memitigasi kriminalisasi berlebih (over-criminalization).
- Analisis Akademik: Dari perspektif gender, KUHP Baru berupaya menyeimbangkan nilai-nilai sosial (living law) dengan hak privasi individu. Penekanan pada Keadilan Restoratif (Pasal 12 UU 1/2023) dalam kasus-kasus tertentu menunjukkan bahwa negara memprioritaskan pemulihan harkat korban di atas sekadar pemidanaan pelaku.
- Tabel Perbandingan Paradigma
| Aspek | KUHP Lama (WvS) | KUHP Baru (UU 1/2023) | Landasan Normatif Baru |
| Subjek Lingkungan | Individu pengurus saja. | Individu & Korporasi. | Pasal 45 & 46 |
| Fokus Gender | Pelanggaran moralitas umum. | Perlindungan otonomi individu. | Pasal 411 – 413 |
| Sanksi Utama | Penjara (Retributif). | Penjara, Pengawasan, Kerja Sosial. | Pasal 64 – 66 |
Penjelasan:
Transformasi ini mencerminkan transisi dari Lex Talionis (hukum pembalasan) menuju Lex Justitia yang holistik. Pengakuan korporasi dalam delik lingkungan dan pembaruan delik gender membuktikan bahwa KUHP Nasional kini memiliki daya adaptasi terhadap tantangan global tanpa meninggalkan akar sosiologis bangsa (volksgeist).
Transformasi paradigma hukum pidana di Indonesia kontemporer menunjukkan komitmen substantif terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) universal, yang terejawantahkan dalam pelbagai instrumen hukum positif, termasuk KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan undang-undang sektoral lainnya.
Perlindungan Anak dan Perempuan
Perlindungan anak dan perempuan menjadi salah satu fokus utama ( pars pro toto) reformasi hukum. Tindak pidana seksual terhadap anak secara spesifik diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016). Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak, misalnya, mengatur sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.
Sementara itu, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 44 UU PKDRT menegaskan tanggung jawab pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
Aspek procedural justice dalam penanganan korban anak dan perempuan diakomodasi melalui mekanisme khusus dalam hukum acara (KUHAP dan peraturan pelaksananya), seperti pendampingan oleh lembaga terkait (LPSK, psikolog), perlindungan identitas, dan prosedur sidang tertutup.
Aspek Gender dan Non-Diskriminasi
Aspek gender dan kesetaraan ( equality before the law) mendapat perhatian substansial melalui prinsip non-diskriminasi yang fundamental. Berbeda dengan narasi awal, KUHP Baru tidak memuat pasal diskriminasi berbasis gender di rentang Pasal 292-293 atau penghinaan identitas gender di Pasal 351 (Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan biasa).
Namun, prinsip non-diskriminasi secara umum dijamin dalam konstitusi (Pasal 28I UUD 1945) dan UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999). UU TPKS secara eksplisit juga mengakui berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Prinsip non-discrimination ini sejalan dengan standar HAM internasional, memastikan kerangka hukum untuk mengatasi kejahatan berbasis identitas dalam konteks sosial modern. Adagium klasik ubi jus ibi remedium—di mana ada hak, di situ ada pemulihan—menjadi relevan, karena korban memperoleh sarana pemulihan hukum yang jelas, sementara pelaku dimintai pertanggungjawaban sesuai proporsi (proportionality principle).
Perlindungan lingkungan hidup, sebagai bagian integral dari HAM generasi ketiga, diatur secara lex specialis melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). KUHP Baru mengelompokkan tindak pidana lingkungan hidup dalam bab tersendiri (Bab XXXI, Pasal 444–451), memberikan landasan kodifikasi yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan. Hal ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan adalah kejahatan serius (crimen laesa natura) yang memerlukan sanksi pidana komprehensif.
Tinjauan Kritis Integrasi Dimensi Ekologis dan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana Nasional
Integrasi dimensi ekologis dan hak asasi manusia (HAM) menandai sebuah evolusi paradigma dalam lanskap hukum pidana nasional, merefleksikan pengakuan bahwa kejahatan modern melampaui kerugian individual (delik privat) dan mencakup kerugian kolektif atau publik.
Perlindungan Lingkungan Hidup dalam KUHP Baru
Perlindungan terhadap lingkungan hidup secara eksplisit diatur dalam Bab XXIX KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Tindak pidana lingkungan hidup tersebar dalam beberapa pasal di Bab XXIX tersebut. Pasal-pasal tersebut mengelaborasi berbagai bentuk malum prohibitum (perbuatan yang dilarang berdasarkan undang-undang) dan malum in se (perbuatan yang pada hakikatnya salah) terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pendekatan hukum pidana ini merupakan ultimum remedium, melengkapi sanksi administratif dan perdata yang telah diatur komprehensif dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). KUHP baru mengafirmasi mekanisme sanksi pidana yang menyasar individu (natural person) maupun badan hukum (legal entity), selaras dengan prinsip societas delinquere non potest (korporasi tidak dapat melakukan kejahatan) yang kini telah ditinggalkan. Prinsip res communis—bahwa lingkungan adalah milik bersama demi keberlanjutan generasi mendatang—menjadi ratio legis (dasar pemikiran hukum) dari penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan korektif. Prosedur spesifik seperti audit lingkungan dan penilaian dampak ekologis (ecological impact assessment) lebih banyak diatur dalam UU PPLH serta hukum acara perdata atau tata usaha negara terkait lingkungan.
Integrasi Aspek Hak Asasi Manusia dalam KUHP Baru
Integrasi aspek HAM tercermin dalam filosofi dan sistematika KUHP baru secara keseluruhan, yang berupaya menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan hukum individu dan publik. Pasal-pasal yang dirujuk (Pasal 11–20) dalam narasi tersebut sebenarnya berkaitan dengan ranah fundamental hukum pidana, seperti tempat tindak pidana, permufakatan jahat, persiapan, dan percobaan tindak pidana, bukan spesifik mengenai hak privasi atau kebebasan berekspresi.
Perlindungan terhadap hak-hak berekspresi dan kehormatan diatur dalam bab tersendiri (misalnya, terkait tindak pidana terhadap harkat dan martabat Presiden/Wakil Presiden, yang kini diatur dengan batasan ketat melalui mekanisme delik aduan). Hal ini merefleksikan dialektika antara freedom of expression dan perlindungan kehormatan institusi negara, sebuah keseimbangan yang esensial dalam negara demokrasi yang berlandaskan rule of law. Dalam praktiknya, putusan pengadilan yang menerapkan restitusi ekologis atau denda korporasi telah banyak eksis berdasarkan UU PPLH, menekankan prinsip mens rea (niat jahat) dan strict liability (tanggung jawab mutlak) dalam konteks kejahatan korporasi.
Arsitektur Hukum Pidana Kontemporer: Responsivitas, Restoratif, dan Integratif
Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mentransformasi lanskap kriminalitas, menjadikan kejahatan siber dan pemanfaatan teknologi sebagai domain pengaturan hukum yang esensial. Narasi awal menyebutkan bahwa Pasal 263–270 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur spesifik penipuan daring, pencurian data pribadi, dan penyebaran konten ilegal. Hal ini tidak sepenuhnya akurat. Faktanya, pasal-pasal tersebut dalam KUHP Baru masih berfokus pada tindak pidana pemalsuan surat (misalnya, [Pasal 391 s.d. Pasal 400 UU 1/2023 yang menggantikan Pasal 263 s.d. Pasal 276 KUHP lama]).
Pengaturan komprehensif terkait aktivitas siber, seperti akses ilegal, manipulasi data, dan penipuan daring, utamanya termaktub dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah, khususnya Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 35 yang mengatur tentang akses ilegal dan perusakan data elektronik. KUHP Baru sendiri memuat beberapa pasal terkait kejahatan komputer, namun tidak secara eksklusif dalam seksi 263-270.
Adapun terkait KUHAP Baru menegaskan prosedur pengumpulan bukti digital dan persidangan daring mencerminkan aspirasi reformasi hukum acara pidana yang berlaku saat ini belum secara eksplisit mengatur alat bukti elektronik secara rinci, yurisprudensi dan UU ITE telah mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah di pengadilan ([Pasal 5 ayat (1) UU ITE]). Semangat “lex futurum”—hukum yang antisipatif terhadap perkembangan zaman, bukan sekadar reaktif—menjadi imperatif dalam memastikan instrumen hukum pidana relevan menghadapi kejahatan yang melampaui batas yurisdiksi fisik (transnasional).
Selanjutnya, narasi mengenai penguatan pendekatan restoratif melalui mekanisme diversi dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) adalah benar adanya. KUHP Baru mengadopsi prinsip keadilan restoratif (restorative justice) secara lebih luas, terutama untuk tindak pidana ringan atau yang melibatkan pelaku anak. Fokusnya bergeser dari retributif (pembalasan) menuju pemulihan relasi sosial, dengan mengedepankan mediasi antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan pemulihan, restitusi, atau kerja sosial.
Pendekatan ini mengimplementasikan kerangka holistik yang memadukan tiga determinasi: determinasi normatif (apa yang diamanatkan oleh norma hukum positif), determinasi sosial (konteks sosiologis dan partikularistik pelaku serta korban), dan determinasi restoratif (upaya mengembalikan keseimbangan/harmoni di masyarakat). Praktik ini menekankan adagium hukum: Fiat justitia et pereat mundus (hendaklah keadilan ditegakkan, sekalipun dunia harus binasa) dimodifikasi dengan pendekatan yang lebih humanis, di mana tujuan akhir peradilan pidana bukan semata-mata inkonsistensi penghukuman (penjara), melainkan tercapainya kemanfaatan dan keseimbangan sosial.
Secara keseluruhan, KUHP dan rancangan KUHAP memang berupaya membangun arsitektur hukum pidana yang kohesif, responsif, dan integratif, di mana berbagai dimensi—HAM, gender, anak, lingkungan, teknologi, dan tanggung jawab korporasi—terakomodasi dalam satu ekosistem hukum yang komprehensif. Paradigma “Ius Integrum Nusantara” merefleksikan visi hukum pidana Indonesia yang utuh dalam norma, adil dalam praksis, dan visioner dalam tujuannya, sekaligus teguh mempertahankan karakter lokal yang humanis.
Transformasi Arsitektur Hukum Pidana Indonesia: Menuju Keadilan Substantif
Evolusi hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bukan sekadar retus teknis atas norma kolonial, melainkan sebuah dekolonialisasi paradigmatik yang merekonstruksi pilar ius poenale (hukum pidana materiil). Mengacu pada adagium lex prospicit, non respicit (hukum melihat ke depan, bukan ke belakang), KUHP Nasional bertransformasi dari instrumen retributif yang kaku menjadi sistem yang adaptif dan humanis.
Secara sistemik, pembaruan ini dapat dianalogikan sebagai struktur organik yang koheren:
- Akar Filosofis (The Living Law): Berbeda dengan sistem WvS yang bersifat legalistic-positivistic, Pasal 2 KUHP Baru mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law), menyeimbangkan asas legalitas formal dengan keadilan materiil.
- Batang Konstruksi (Ultimum Remedium): Penegasan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium tercermin dalam diversifikasi sanksi. Pasal 65 ayat (1) memperkenalkan pidana pengawasan dan kerja sosial sebagai alternatif penjara, mengedepankan prinsip culpue poena par esto (hukuman harus setimpal dengan perbuatan).
- Cabang Perlindungan & Kemanusiaan: Melalui doktrin restorative justice, orientasi hukum bergeser dari sekadar menghukum pelaku menjadi memulihkan korban. Hal ini diperkuat dengan institusi rechterlijk pardon (pemaafan hakim) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2), yang memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan.
- Integrasi Global & Kejahatan Modern: Adaptasi terhadap tindak pidana mayantara dan lingkungan hidup menunjukkan kematangan legal engineering Indonesia dalam menghadapi tantangan transnasional, memastikan hukum tetap relevan di tengah dinamika global.
Selain itu, kodifikasi ini adalah manifestasi dari kemandirian hukum nasional yang berusaha menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan. Implementasi KUHP Nasional menuntut kesiapan mentalitas aparat penegak hukum agar tidak terjebak dalam legal-formalism, melainkan mampu menyelami ruh keadilan substantif demi kemaslahatan masyarakat luas.
Transformasi Filosofis dan Substantif Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
Secara filosofis, keberlakuan KUHP baru menandai sebuah paradigma pergeseran dari pendekatan legalistik-positivistik (berorientasi pada kepatuhan formalistik) yang menjadi ciri khas Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan kolonial, menuju suatu arketipe ( archetype ) hukum pidana modern yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan substantif. Di sini, hukum pidana tidak lagi sekadar berfungsi sebagai instrumentalisasi alat represif (ultimum remedium) untuk menegakkan sanksi an sich, melainkan bertransformasi menjadi instrumen korektif, edukatif, dan restoratif yang menyeimbangkan secara adil kepentingan vital pelaku, korban, dan masyarakat (sociale veiligheid).
Semangat integrasi dan sintesis nilai-nilai luhur Nusantara ini, yang sering diistilahkan dalam diskursus akademis sebagai prinsip Ius Integrum Nusantara, menjadi landasan epistemologis kebaharuan kodifikasi hukum pidana nasional. Hukum dipandang sebagai suatu sistem integral yang menekankan konkurensi (keselarasan) antara keadilan substantif, kepastian normatif (lex certa), dan responsivitas sosial.
Prinsip nulla poena sine lege (asas legalitas formal) tetap dijaga eksistensinya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023; namun, ia diperluas dengan pengakuan terhadap pengecualian asas non-retroaktif melalui lex mitior (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2023), pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau kearifan lokal (living law) dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023, serta justifikasi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan standar hukum internasional. Ini merepresentasikan sebuah lompatan konseptual signifikan dari pendekatan kolonial yang kaku menuju model deterministik-futuristik yang humanis.
Dalam dimensi substansi pemidanaan, KUHP baru mengintroduksi inovasi signifikan melalui adopsi paradigma pemidanaan berlapis (double track system) yang menggabungkan secara holistik antara pidana (hukuman) dan tindakan (rehabilitasi, denda, kerja sosial, dan keadilan restoratif). Hal ini berbeda fundamental dengan KUHP lama yang terpusat pada pelaku dan sanksi penjara. Inovasi ini, yang pengaturannya tersebar dalam Bab III tentang Pidana dan Bab IV tentang Tindakan (Pasal 64 sampai dengan Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023), memungkinkan hukum pidana beradaptasi dengan tantangan sosial, teknologi (misalnya kejahatan siber), dan ekonomi modern, sekaligus menegaskan pertanggungjawaban korporasi (Pasal 45 dan selanjutnya). Pengaturan mengenai keadilan restoratif secara lebih rinci juga dapat ditemukan dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).
Secara mental map konseptual, kebaharuan KUHP Baru dapat dibayangkan sebagai sebuah conceptual tree yang berakar kuat pada filosofi humanisme konstitusional dan nilai Pancasila. Dari akar tersebut, tumbuh cabang-cabang utama yang merepresentasikan lima domain kunci hukum pidana modern: norma pidana materiil, hukum acara pidana, perlindungan hak asasi manusia dan korban, peran serta akuntabilitas aparat penegak hukum, serta harmonisasi dengan hukum dan standar internasional. Cabang-cabang ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung oleh mekanisme keadilan restoratif, prinsip proporsionalitas, dan tanggung jawab institusional, sehingga membentuk sebuah jaringan hukum pidana yang koheren, adaptif, dan berorientasi ke masa depan (future-oriented criminal justice system).
Dalam perspektif reflektif, konfigurasi tersebut menegaskan novelty hukum pidana Indonesia yang bersifat sistemik, bukan sekadar kosmetik normatif. Pembaruan KUHP dan KUHAP tidak lagi dimaknai sebagai penyesuaian pasal demi pasal, melainkan sebagai rekonstruksi menyeluruh terhadap karakter, konstruksi, dan orientasi hukum pidana nasional. Pergeseran ini mencerminkan transisi dari hukum pidana yang represif dan pelaku-sentris menuju sistem yang preventif, restoratif, dan masyarakat-sentris, selaras dengan adagium jus restaurativum ante jus retributivum dan prinsip salus populi suprema lex esto dalam konteks negara hukum demokratis.
Dengan demikian, KUHP Baru hadir sebagai sebuah arsitektur integratif yang memadukan kepastian hukum (rechtszekerheid), keadilan substantif (substantive justice), perlindungan hak asasi manusia, pengakuan terhadap kearifan lokal, serta keterbukaan terhadap dinamika global. Integrasi KUHP dan KUHAP Baru tidak hanya menegakkan hukum dalam arti formal, tetapi juga memfasilitasi pemulihan sosial, reintegrasi pelaku, perlindungan korban, dan stabilitas masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum pidana Indonesia bergerak menuju instrumen modern yang humanis, responsif, dan resilien, mampu menjawab tantangan kontemporer sekaligus menyiapkan fondasi normatif bagi masa depan sistem peradilan pidana nasional.
Tinjauan Kritis Transformasi Hukum Pidana Indonesia
Di ranah hukum acara pidana, korpus normatif Indonesia mengalami reformasi fundamental melalui adopsi mekanisme modern dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Pergeseran paradigma ini secara eksplisit menyeimbangkan posisi subjek hukum—tersangka, terdakwa, dan korban—dalam suatu kerangka kerja yang menjunjung tinggi prinsip due process of law.
Secara prosedural, KUHAP Baru memperkenalkan instrumen-instrumen yudisial kontemporer. Pengaturan ulang institusi praperadilan dan mekanisme upaya hukum luar biasa seperti kasasi serta peninjauan kembali (PK) menjadi lebih terstruktur, sejalan dengan semangat checks and balances peradilan. Guna mengadaptasi zeitgeist era digital, KUHAP Baru mengafirmasi penggunaan sidang daring dan alat bukti digital sebagai instrumen normatif yang esensial, memungkinkan proses peradilan bergerak secara lebih efisien dan adil.
Integral dari kebaharuan ini adalah pengarusutamaan (mainstreaming) pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi anak. Berbeda dengan pandangan bahwa ini sekadar tempelan, kedua konsep ini secara sistemik diintegrasikan dalam prosedur peradilan, terutama termaktub dalam Pasal 5 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pergeseran ini merefleksikan adagium hukum ultimum remedium, di mana hukum pidana tidak lagi didominasi oleh pendekatan retributif an sich, melainkan bertransformasi menjadi sistem partisipatif yang melibatkan multipihak dalam pemulihan harmoni sosial (social rehabilitation).
Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), KUHAP Baru menegaskan perlindungan komprehensif bagi hak-hak fundamental warga negara, yang membedakannya secara substansial dari warisan kolonial HIR/RBg. Hak dasar korban dan saksi diatur secara tegas dalam Pasal 143 dan Pasal 144 KUHAP Baru, di samping jaminan hak anak, perempuan, kebebasan berpendapat, dan larangan penyiksaan. Integrasi prinsip restorative justice memastikan tercapainya keadilan substantif (substantive justice), yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban (victim compensation) dan reintegrasi pelaku. Dari aspek yurisprudensi, Mahkamah Agung (MA) melalui berbagai putusan telah memperkuat kebijakan ini sebagai standar penanganan perkara nasional.
Menyikapi globalisasi dan hukum internasional, KUHAP Baru mengadopsi praktik terbaik (best practices) hukum pidana global. Meskipun terdapat kritik mengenai harmonisasi dengan standar HAM internasional tertentu, undang-undang ini memuat kerangka regulasi untuk kejahatan lintas negara (transnational crimes), cybercrime, pidana internasional, dan perdagangan manusia, selaras dengan konvensi internasional terkait, seperti Protokol Palermo dan Konvensi Hak Anak. Kebaharuan ini menempatkan arsitektur hukum pidana Indonesia dalam spektrum hukum global, sekaligus meneguhkan identitasnya yang mandiri.
Menjaga Arah Pembaruan: Hukum Pidana di Persimpangan Konstitusi dan Keadilan
Pembaruan hukum pidana melalui berlakunya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) menegaskan bahwa Indonesia telah melangkah melampaui sekadar revisi normatif menuju rekonstruksi sistemik. Pergeseran dari hukum represif-pelaku-sentris ke pendekatan preventif-restoratif-masyarakat-sentris mencerminkan upaya sadar untuk menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan martabat manusia dan keseimbangan sosial. Dengan memperluas subjek, objek, serta ragam sanksi, kodifikasi baru ini berusaha menjawab dinamika kejahatan modern, sekaligus meneguhkan adagium salus populi suprema lex esto dalam makna yang lebih inklusif dan kontekstual.
Namun, dinamika uji materiil di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa kebaruan normatif selalu berhadapan dengan tuntutan kepastian dan perlindungan hak konstitusional. Pengujian terhadap pasal-pasal strategis, baik dalam ranah substansi pidana maupun prosedur acara, merefleksikan kekhawatiran akan potensi perluasan kewenangan negara yang berlebihan. Pada titik ini, prinsip nullum crimen sine lege certa dan due process of law menjadi jangkar yang tidak dapat ditawar, agar hukum pidana tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis, bukan tergelincir menjadi instrumen koersif yang kontraproduktif.
Secara reflektif, perdebatan konstitusional tersebut justru memperlihatkan vitalitas sistem hukum. Mekanisme judicial review berfungsi sebagai ruang dialektika yang memastikan bahwa ius constitutum senantiasa diuji terhadap nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia yang bersifat inalienable. Dalam konteks ini, adagium ubi ius incertum, ibi ius nullum menjadi pengingat bahwa kejelasan rumusan norm99a adalah prasyarat mutlak bagi keadilan substantif. Kodifikasi hukum pidana yang modern tidak cukup hanya responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, tetapi juga harus presisi, proporsional, dan akuntabel.
Pada akhirnya, KUHP dan KUHAP Baru harus dibaca sebagai proyek hukum yang masih bergerak—a living legal system. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma, melainkan oleh kemampuan seluruh institusi hukum dan masyarakat untuk menafsirkan dan menerapkannya secara arif. Simpulan ini menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana akan mencapai tujuan idealnya apabila kebaruan normatif, pengawasan konstitusional, dan praktik penegakan hukum berjalan selaras, sehingga hukum benar-benar menjadi sarana keadilan yang beradab, manusiawi, dan berpijak pada cita hukum nasional. []
*) Penulis 1: Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia
**) Penulis 2: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
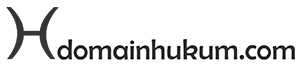



















Komentar