Quo Vadis Jabatan Notaris Pasca KUHP Baru dan KUHAP Baru
Antara Perlindungan Jabatan dan Bayang-Bayang Kriminalisasi
Oleh: Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp,N., M.Kn.*) dan Andi Hakim Lubis**)
 Ketika Prosedur Bertransformasi Menjadi Ancaman, dan Ius Integrum Nusantara sebagai Jalan Rekonstruksi
Ketika Prosedur Bertransformasi Menjadi Ancaman, dan Ius Integrum Nusantara sebagai Jalan Rekonstruksi
Hukum acara pidana, dalam konsepsi idealnya, bekerja secara low profile: hadir sebagai mekanisme penjaga  keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak warga negara. Ia seharusnya beroperasi in silence, memastikan due process of law tanpa menciptakan kegaduhan sosial. Namun, bagi notaris di Indonesia, hukum acara justru tampil dalam wajah yang berisik—melalui laporan pidana yang prematur, pemanggilan penyidik yang repetitif, dan stigma publik yang terbentuk jauh sebelum kebenaran diuji secara judicially ascertainable. Paradoks ini bukan lahir dari pelanggaran hukum yang nyata, melainkan dari praktik prosedural yang gagal membaca konteks jabatan publik secara proporsional. Dalam lanskap demikian, KUHAP baru—yang semestinya menjadi simbol pembaruan—justru berisiko memperdalam ketidakpastian apabila ditafsirkan secara sempit dan positivistik.
keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak warga negara. Ia seharusnya beroperasi in silence, memastikan due process of law tanpa menciptakan kegaduhan sosial. Namun, bagi notaris di Indonesia, hukum acara justru tampil dalam wajah yang berisik—melalui laporan pidana yang prematur, pemanggilan penyidik yang repetitif, dan stigma publik yang terbentuk jauh sebelum kebenaran diuji secara judicially ascertainable. Paradoks ini bukan lahir dari pelanggaran hukum yang nyata, melainkan dari praktik prosedural yang gagal membaca konteks jabatan publik secara proporsional. Dalam lanskap demikian, KUHAP baru—yang semestinya menjadi simbol pembaruan—justru berisiko memperdalam ketidakpastian apabila ditafsirkan secara sempit dan positivistik.
Sebagai public officer, notaris menjalankan kewenangan negara dalam membentuk akta autentik, yang menurut Pasal 1868 KUHPerdata merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna (perfect proof). Namun, di titik inilah muncul ironi sistemik: akta yang dirancang sebagai instrumen kepastian hukum sering kali ditarik ke dalam pusaran sengketa pidana yang sejatinya berakar pada konflik perdata. Masalahnya bukan pada substansi akta, melainkan pada kecenderungan criminalization of civil conduct—sebuah distorsi nalar hukum ketika rezim pidana digunakan untuk menyelesaikan ketidakpuasan perdata. Tanpa mekanisme klarifikasi awal (pre-investigative clarification), notaris yang bertindak in official capacity dan bona fide kerap dijadikan subjek laporan pidana. Dalam konteks ini, absennya pengaturan eksplisit mengenai klarifikasi sejak tahap penyelidikan dalam KUHAP baru berpotensi menginstitusionalisasi formalistic criminalization terhadap pejabat publik.
Situasi tersebut mendorong lahirnya serangkaian pengujian konstitusional terhadap ketentuan KUHAP baru, khususnya Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (5). Uji materi ini merefleksikan ketegangan laten antara procedural justice dan substantive justice. Pertanyaan normatif yang mengemuka bersifat mendasar: apakah status “terlapor” dapat dilekatkan tanpa proses klarifikasi awal? Apakah hukum membenarkan ambiguitas status hukum yang berkepanjangan? Sampai batas mana sengketa perdata dapat dipaksakan mengenakan penal cloak? Tanpa jawaban yang tegas, notaris akan bekerja dalam kondisi structural fear—takut menjalankan kewenangan, takut mengambil keputusan, dan pada akhirnya takut menjalankan fungsi negara itu sendiri.
Akar problematika ini terletak pada dominasi positivisme hukum yang rigid. Selama terdapat laporan, proses penyidikan dianggap sah untuk dimulai, tanpa mempertimbangkan konteks jabatan, fungsi sosial, dan itikad baik. Hukum acara bertransformasi menjadi mesin prosedural yang dingin—procedural automatism—yang gagal membedakan antara ordinary offender dan pejabat publik yang menjalankan mandat negara. Akta notaris diperlakukan seolah hasil kehendak privat, bukan produk jabatan yang secara normatif dilindungi. Dalam kerangka ini, adagium nemo censetur ignorare legem kerap disalahgunakan sebagai legitimasi penjeratan, padahal seharusnya dibaca bersama prinsip authority-based responsibility dan perlindungan terhadap tindakan jabatan yang sah.
Di sinilah Ius Integrum Nusantara (IIN) menawarkan perspektif korektif dan transformatif. IIN menolak reduksi hukum menjadi sekadar teks normatif; hukum harus dipahami sebagai sistem utuh yang mengintegrasikan norma tertulis, nilai sosial, dan keadilan substantif. Dalam konteks kenotariatan, IIN mengajukan normative test: apakah tindakan notaris dilakukan dalam lingkup kewenangan jabatan (intra vires) dan dengan itikad baik (good faith)? Jika jawabannya afirmatif, maka pendekatan pidana harus ditunda, dan klarifikasi administratif-yuridis menjadi primary recourse. Penyidikan pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium, bukan prima facie response.
Dengan lensa ini, KUHAP baru sejatinya masih dapat dibaca secara progresif. Kewajiban klarifikasi terhadap terlapor, penegasan status hukum sejak tahap awal, serta transparansi proses pelaporan bukanlah hambatan penegakan hukum, melainkan instrumen rights-based protection. Tanpa paradigma integratif ala IIN, pasal-pasal KUHAP berisiko dimaknai secara sempit dan instrumental, menjadikan hukum acara sebagai alat kekuasaan (instrument of control), bukan sarana keadilan. Perlindungan terhadap jabatan notaris tidak boleh bergantung pada diskresi individual aparat, melainkan harus dijamin oleh desain sistem hukum itu sendiri.
Berulangnya pola perkara notaris mengindikasikan kegagalan struktural: sengketa perdata dikonversi menjadi laporan pidana, notaris diproses tanpa klarifikasi memadai, dan perkara berlarut hingga akhirnya dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana. Kerusakan reputasi, kelelahan psikologis, dan erosi kepercayaan publik menjadi harga yang harus dibayar. Apabila KUHAP baru gagal memutus mata rantai ini, maka reformasi hukum acara pidana kehilangan legitimasi sosiologisnya.
Negara hukum (Rechtsstaat) tidak hanya disangga oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh notaris yang independen, berani, dan bebas dari rasa takut. Tanpa perlindungan jabatan yang memadai, notaris akan bersikap defensif (defensive practice), menghindari risiko, dan pada akhirnya menurunkan kualitas kepastian hukum. IIN menegaskan bahwa hukum yang baik bukanlah hukum yang paling represif, melainkan yang paling adil dalam konteks masyarakatnya. Melindungi notaris dari kriminalisasi prosedural bukanlah pelemahan hukum pidana, melainkan penguatan fondasi negara hukum itu sendiri.
Gugatan konstitusional terhadap KUHAP baru karenanya harus dipahami sebagai momen reflektif, bukan sekadar koreksi prosedural. Pertanyaannya bukan hanya apakah pasal-pasal tersebut konstitusional, tetapi apakah hukum acara pidana telah setia pada mandat konstitusionalnya: melindungi martabat manusia dan fungsi publik. Dengan pendekatan Ius Integrum Nusantara, hukum Indonesia dituntut hadir secara utuh—menjaga kepastian, mewujudkan keadilan, dan menjunjung kemanusiaan. Kegagalan melindungi notaris bukan sekadar persoalan profesi, melainkan ancaman terhadap kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri.
Judicial Review KUHP dan KUHAP Baru: Sebuah Pembacaan Konstitusional
Pemberlakuan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) menandai fase baru hukum pidana nasional, sekaligus membuka ruang ketegangan antara kepastian hukum formal dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hal ini tercermin dari banyaknya permohonan judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam KUHP Baru, sejumlah pasal menjadi sorotan krusial. Pasal 218 dan Pasal 240, terkait penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara, dipersoalkan karena potensi chilling effect terhadap kebebasan berekspresi. Pasal 100 mengenai masa percobaan pidana mati diuji dari perspektif kepastian hukum. Pasal 411 dan 412 tentang perzinaan dan kohabitasi diuji karena beririsan dengan hak privasi. Sementara Pasal 263 mengenai penyiaran berita bohong dipertanyakan konsistensinya dengan ratio decidendi Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023.
Dalam KUHAP Baru, isu konstitusional terpusat pada prosedur dan perlindungan hak individu. Pertama, rezim alat bukti—khususnya bukti elektronik dan hasil penyadapan—diperhadapkan dengan hak privasi. Kedua, pengaturan penahanan pra-persidangan diuji agar tidak membuka ruang abuse of power. Ketiga, prinsip Dominus Litis diuji untuk memastikan keseimbangan kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana.
Rangkaian judicial review ini menegaskan bahwa reformasi hukum pidana tidak dapat berhenti pada perubahan normatif. Hukum harus dibaca secara integratif sebagaimana ditawarkan oleh Ius Integrum Nusantara: menyatukan teks, nilai sosial, dan keadilan substantif. Dalam konteks notaris, pengujian konstitusional tersebut menjadi indikator penting bahwa hukum acara pidana harus memprioritaskan klarifikasi awal, perlindungan jabatan, dan penghormatan terhadap fungsi publik, guna mencegah kriminalisasi prosedural terhadap pejabat yang menjalankan kewenangan sah.
Dengan perspektif ini, judicial review bukan sekadar koreksi pasal, melainkan refleksi sistemik tentang bagaimana KUHP dan KUHAP baru dapat diselaraskan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan nilai-nilai Pancasila sebagaimana dicita-citakan dalam paradigma Ius Integrum Nusantara.
Rekodifikasi Hukum Pidana dan Konsekuensinya bagi Profesi Notaris
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) menandai berakhirnya dominasi Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan kolonial dan sekaligus membuka babak baru rekodifikasi hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional bukan sekadar penggantian teks normatif, melainkan reposisi paradigma hukum pidana yang berakar pada nilai Pancasila, konstitusionalisme modern, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi dipahami semata sebagai instrument of repression, melainkan sebagai social engineering tool yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (rechtssicherheit, gerechtigkeit, zweckmäßigkeit).
Secara paradigmatik, KUHP Nasional bergerak dari pendekatan retributif klasik menuju model restorative justice, dengan menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam relasi yang lebih proporsional. Di saat yang sama, KUHP Nasional mengakui keberadaan living law sebagai sumber hukum pidana, sepanjang selaras dengan Pancasila dan prinsip HAM. Pengakuan ini mencerminkan adagium ubi societas, ibi ius—bahwa hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dari realitas sosial yang hidup.
Arah Pembaruan dan Struktur Sistemik KUHP Nasional
Pembaruan KUHP Nasional memiliki signifikansi struktural. Pertama, ia mengakhiri dualisme historis antara hukum pidana nasional dan kolonial, serta membangun sistem yang lebih kontekstual dengan perkembangan sosial, teknologi, dan kejahatan modern (modern crimes). Kedua, keberlakuannya ditunda selama tiga tahun sejak pengundangan (2 Januari 2023) hingga efektif berlaku pada 2 Januari 2026, sebagai bentuk legal transition period agar aparatur penegak hukum dan masyarakat memiliki ruang adaptasi.
Secara sistematika, KUHP Nasional disusun dalam dua buku utama:
Buku Kesatu memuat aturan umum (general principles of criminal law), termasuk asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, alasan pembenar dan pemaaf, serta pemidanaan korporasi. Buku Kedua mengatur jenis-jenis tindak pidana, termasuk delik terhadap kepercayaan publik dan jabatan.
Dalam konteks ini, KUHP Nasional membangun sistem hukum pidana yang lebih adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap kejahatan berbasis teknologi serta kejahatan ekonomi, tanpa mengabaikan perlindungan korban dan kepastian hukum bagi warga negara.
Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam KUHP Nasional
Sebagai pejabat umum (public officer) yang menjalankan fungsi negara dalam pembuatan akta autentik, notaris menempati posisi strategis dalam sistem hukum. Oleh karena itu, KUHP Nasional secara eksplisit mengatur bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan kebenaran dan integritas akta autentik.
Pasal 396 ayat (1) huruf a KUHP Nasional menegaskan bahwa pemalsuan surat berupa akta autentik diancam pidana penjara paling lama delapan tahun. Ketentuan ini secara lex specialis ratione personae menyasar dokumen yang dibuat oleh pejabat umum, termasuk notaris. Selanjutnya, Pasal 392 dan Pasal 394 memperluas pertanggungjawaban pidana terhadap setiap perbuatan memasukkan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, baik oleh pejabat pembuat maupun oleh pihak yang berkepentingan. Norma ini menegaskan prinsip actus non facit reum nisi mens sit rea: pemidanaan mensyaratkan adanya kesengajaan atau kesadaran hukum.
KUHP Nasional juga mengatur larangan pembukaan rahasia jabatan tanpa dasar hukum yang sah melalui Pasal 443, yang beririsan langsung dengan kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan akta. Dalam konteks korporasi, Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 memperkenalkan rezim pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk ketika notaris berperan sebagai functional officer atau pihak pengendali (controlling mind). Selain itu, sistem denda diperbarui melalui Pasal 78–79 jo. Pasal 521 dengan klasifikasi denda kategori I hingga VIII, yang lebih fleksibel dan proporsional dibandingkan sistem lama.
KUHP Nasional juga mengatur delik lanjutan yang relevan dengan praktik kenotariatan, seperti penggunaan dokumen palsu (Pasal 486) dan penyalahgunaan dokumen angkutan barang atau konosemen (Pasal 501), yang menunjukkan perluasan rezim perlindungan terhadap kepercayaan publik dalam transaksi hukum.
Relasi KUHP Nasional dan UU Jabatan Notaris
Hubungan antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) bersifat komplementer. KUHP mengatur aspek ius puniendi negara, sementara UUJN mengatur standar profesi, kewajiban jabatan, serta mekanisme perlindungan notaris. Pasal 66 UUJN menegaskan bahwa pemanggilan notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta dalam proses pidana wajib memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang berfungsi sebagai institutional safeguard terhadap kriminalisasi jabatan. Di sisi lain, Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN mengatur kewajiban merahasiakan isi akta (right of refusal / hak ingkar).
Perlindungan jabatan ini tidak bersifat absolut. Prinsip equality before the law tetap berlaku apabila notaris dengan sengaja dan sadar hukum membuat akta palsu atau menyalahgunakan kewenangannya. Dengan kata lain, perlindungan profesi tidak boleh disalahartikan sebagai impunity clause.
KUHAP Baru dan Dinamika Prosedural bagi Notaris
Seiring dengan KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru—yang juga berlaku efektif 2 Januari 2026—memperkenalkan rezim hukum acara pidana yang lebih modern dan berbasis digital. Pengakuan alat bukti elektronik memperluas spektrum pembuktian, termasuk email, data digital, dan rekaman elektronik. Di sisi lain, kewenangan penyitaan digital dan penyitaan dalam keadaan mendesak (Pasal 49–50 dan Pasal 113A KUHAP Baru) berpotensi bersinggungan dengan mekanisme perlindungan notaris sebagaimana diatur Pasal 66 UUJN.
KUHAP Baru juga memperkuat hak saksi, termasuk hak notaris untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan serta tetap menggunakan hak ingkar sepanjang menyangkut rahasia jabatan. Dalam konteks justice collaborator atau saksi mahkota, posisi notaris menjadi semakin sensitif karena keterangan pihak dalam akta dapat digunakan untuk memberatkan, sehingga ketertiban administrasi minuta, sidik jari, dan protokol notaris menjadi krusial sebagai defensive evidence.
Perlindungan Jabatan dan Rasionalisasi Risiko
Meskipun risiko hukum meningkat, perlindungan jabatan notaris tetap diakui secara normatif. Hak ingkar tetap berlaku, persetujuan MKN tetap menjadi lex specialis, dan Pasal 31 KUHP Nasional mengenai alasan pembenar melindungi notaris yang bertindak berdasarkan perintah undang-undang atau kewenangan jabatan. Dalam kerangka ini, prinsip nulla poena sine culpa tetap menjadi pagar etis dan yuridis pemidanaan.
Mulai 2 Januari 2026, keberlakuan KUHP dan KUHAP baru secara simultan menegaskan perluasan sekaligus penajaman tanggung jawab pidana notaris. Risiko hukum meningkat seiring pengakuan bukti digital dan kewenangan penyitaan, namun perlindungan jabatan tetap dijaga melalui UUJN. Notaris hanya dapat dipidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bertindak dengan kesengajaan atau kesadaran hukum dalam membuat akta palsu, membuka rahasia jabatan tanpa dasar hukum, atau terlibat dalam kejahatan korporasi dan tindak pidana lanjutan.
Oleh karena itu, kepatuhan prosedural, dokumentasi akta yang cermat, dan pemahaman komprehensif terhadap rezim KUHP dan KUHAP baru bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategic necessity untuk menjaga marwah profesi notaris dalam era KUHP Nasional 2026.
Antara Perlindungan Jabatan dan Bayang-Bayang Kriminalisasi
Efektif sejak 2 Januari 2026, berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menandai transformasi yang fundamental dalam arsitektur hukum pidana Indonesia. Reformasi ini bukan sekadar pembaruan teks normatif; ia adalah pergeseran paradigma—dari logika retributive justice menuju corrective justice—yang menekankan penegakan hukum yang sistemik, transparan, dan proporsional. Fokusnya tidak hanya pada penghukuman, tetapi pada pencegahan, perbaikan, dan penguatan integritas institusi hukum, sehingga hukum hadir sebagai instrumen yang tidak hanya menilai akibat, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial.
Di tengah arus perubahan ini, jabatan Notaris berada pada persimpangan kritis antara cahaya kepercayaan dan bayang-bayang kriminalisasi. Sebagai pejabat preventif, Notaris bekerja di hulu sistem hukum, menjembatani kehendak para pihak dengan kepastian hukum formal melalui akta autentik. Ia adalah guardian of legal certainty, menjamin bahwa setiap hak, kewajiban, dan niat hukum tercatat dengan sah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jabatan ini adalah oficium nobile, panggilan mulia yang lahir dari kepercayaan masyarakat (officium trust), sekaligus mandat negara (officium publicum) untuk menyajikan alat bukti yang menjadi rujukan dalam peradilan.
Namun, di balik kemuliaan itu, terdapat bayang-bayang risiko yang tidak ringan. Perluasan subjek pertanggungjawaban pidana dan kewenangan penyidik dalam KUHP dan KUHAP Baru menempatkan Notaris pada garis tipis antara kehati-hatian profesional dan tuduhan pidana. Bahkan ketika seluruh prosedur UU Jabatan Notaris dijalankan dengan sempurna, kesalahan materiil yang dilakukan oleh pihak penghadap, atau interpretasi aparat terhadap isi akta, dapat menjerat Notaris dalam konstruksi kriminalisasi struktural. Di sinilah dilema jabatan preventif muncul secara dramatis: antara melindungi integritas profesi dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta menghadapi potensi risiko pidana yang muncul dari luar kendali profesionalnya.
Notaris menjadi simbol ketegangan antara hukum sebagai pelindung dan hukum sebagai ancaman. Setiap tinta yang dituangkan dalam akta bukan hanya merekam kehendak para pihak, tetapi juga menegaskan kepercayaan publik, sekaligus menantang aparat penegak hukum untuk membedakan antara kesalahan administratif dan perbuatan pidana. Jabatan ini adalah medan di mana etika, tanggung jawab, dan hukum berpadu, menuntut kehati-hatian yang melebihi prosedur, serta keberanian yang lahir dari pemahaman mendalam bahwa menjaga Notaris berarti menjaga fondasi kepastian hukum itu sendiri.
Di ujung perjalanan hukum yang baru ini, jabatan Notaris berdiri seperti mercusuar di tengah gelombang perubahan. Tinta akta yang dituangkan bukan sekadar catatan formal, melainkan saksi bisu dari kepercayaan publik—officium trust—yang digenggam dengan tanggung jawab mulia. Dalam setiap goresan pena, tersimpan janji bahwa hak dan kewajiban setiap individu akan diakui, dihormati, dan terlindungi, tanpa bias atau rekayasa.
Namun, cahaya kepercayaan itu selalu beriringan dengan bayang-bayang kemungkinan kriminalisasi. Setiap prosedur yang dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian bisa dipertanyakan, setiap akta autentik berpotensi menjadi bahan uji di pengadilan, seolah jabatan preventif yang mulia ini selalu berada di ambang risiko. Inilah paradoks yang lahir dari modernisasi hukum: semakin besar perlindungan hukum, semakin tajam tuntutan akuntabilitas; semakin kuat kepercayaan masyarakat, semakin nyata bayang-bayang pengawasan negara.
Dalam palung terdalam jabatan ini, terdapat sebuah prinsip sederhana namun mendalam: menjaga Notaris berarti menjaga fondasi kepastian hukum, dan menjaga kepastian hukum berarti menjaga keadilan itu sendiri. Kepercayaan publik bukan sekadar modal simbolis, melainkan inti dari struktur hukum yang beradab, yang menuntut perlindungan terhadap mereka yang menyalurkan kehendak hukum secara sah dan bertanggung jawab. Tanpa perlindungan normatif yang jelas, oficium nobile itu bisa menjadi medan yang menakutkan, di mana takut menulis bisa mengalahkan keberanian untuk menegakkan kepastian hukum.
Seperti kata bijak klasik, “Fides publicae est fundamentum juris”—kepercayaan publik adalah fondasi hukum. Jabatan preventif bukan sekadar posisi administratif; ia adalah pengikat sosial yang menegaskan bahwa hukum bukan hanya instrumen penghukuman, tetapi juga perisai bagi mereka yang melayani kebenaran formal dan integritas masyarakat. Dalam era KUHP dan KUHAP Baru, meneguhkan perlindungan jabatan Notaris berarti meneguhkan hukum itu sendiri, agar tetap menjadi mercusuar keadilan di tengah arus kompleksitas zaman. Jabatan Notaris adalah panggilan mulia (oficium nobile), lahir dari kepercayaan publik (officium trust), sekaligus mandat negara (officium publicum) untuk menyajikan alat bukti di pengadilan, Notarii officium nobile est, ex fiducia publicae (officium trust) orta, simulque mandato civitatis (officium publicum) instrumenta probatoria in iudicio praebere.
Jabatan Preventif dan Prinsip Lex Specialis
Notaris adalah pejabat umum yang tunduk pada kerangka normatif UU Jabatan Notaris (UUJN), di mana akta autentik ditempatkan dalam ranah formele waarheid, bukan materiële waarheid. Prinsip klasik notarius non iudicat menegaskan bahwa Notaris tidak menilai kebenaran materiil fakta di balik dokumen, melainkan memastikan prosedur hukum dijalankan dengan tepat—mulai dari verifikasi identitas pihak penghadap, pemenuhan prosedur administratif, hingga kesesuaian bentuk akta—yang bersama-sama menjadi fondasi integritas profesi dan kepastian hukum formal.
Namun, era KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025), yang berlaku efektif bersamaan pada 2 Januari 2026, memperluas lingkup pertanggungjawaban pidana hingga menyentuh pejabat preventif seperti Notaris. KUHAP Baru menghadirkan rezim hukum acara pidana modern, termasuk pengakuan alat bukti elektronik serta pengaturan penyitaan digital (Pasal 49–50 dan Pasal 113A), yang berpotensi bersinggungan dengan perlindungan jabatan Notaris.
Bagi Notaris, beberapa hak tetap dijaga: hak untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan, serta hak ingkar (right of refusal) ketika menyangkut rahasia jabatan. Namun, posisi Notaris menjadi semakin sensitif dalam konteks justice collaborator, karena keterangan pihak dalam akta bisa memberatkan orang lain. Prinsip nulla poena sine culpa tetap menjadi pagar etis bagi Notaris, sementara Pasal 31 KUHP Nasional menyediakan alasan pembenar bagi tindakan yang dijalankan sesuai kewenangan jabatan.
Jabatan Notaris adalah oficium nobile, lahir dari kepercayaan publik (officium trust) dan mandat negara (officium publicum). Sebagai guardian of legal certainty, Notaris memastikan bahwa akta autentik merekam kehendak para pihak secara sah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, di era KUHP dan KUHAP Baru, jabatan preventif ini menghadapi bayang-bayang kriminalisasi struktural:
- Penyitaan protokol, minuta, atau dokumen digital tanpa persetujuan MKN (Pasal 222 KUHAP Baru).
- Risiko pidana atas dokumen yang ternyata mengandung keterangan palsu atau digunakan untuk tindak pidana (Pasal 392, 394, 486, 501 KUHP).
- Tanggung jawab korporasi yang dapat meluas hingga menjerat Notaris yang memfasilitasi pendirian atau legalisasi dokumen (Pasal 46–48 KUHP).
Paradoks ini menegaskan adagium klasik: “Fides publicae est fundamentum juris”—kepercayaan publik adalah fondasi hukum. Jabatan preventif menuntut kehati-hatian, keberanian, dan kebijaksanaan, sekaligus menjaga integritas dokumen dan kepastian hukum formal.
Notaris tunduk pada UUJN sebagai lex specialis, memastikan akta autentik adalah formele waarheid, bukan materiële waarheid. Prinsip notarius non iudicat menegaskan peran preventif, bukan evaluatif atas fakta di balik dokumen.
Namun, KUHP dan KUHAP Baru sebagai lex generalis memperluas pertanggungjawaban pidana, menempatkan Notaris pada garis tipis antara:
- Menjalankan tugas mulia (oficium nobile),
- Menghadapi risiko pidana retrospektif karena dokumen disalahgunakan pihak lain.
Dalam praktik, paradoks ini tampak jelas: Notaris memverifikasi identitas, memeriksa dokumen, dan menyusun akta sesuai UUJN. Apabila dokumen ternyata palsu atau digunakan untuk kejahatan, akta yang dihasilkan—meskipun dibuat dengan niat baik—dapat dipertanyakan di pengadilan, sesuai adagium “nemo tenetur ad extra facta sua”.
Di sinilah, jabatan preventif Notaris berada di persimpangan kritis antara cahaya kepercayaan publik dan bayang-bayang kriminalisasi, menuntut profesionalisme, kehati-hatian prosedural, dan keberanian etis yang konsisten dengan mandat formal, integritas profesi, dan kepastian hukum.
Akta, Keterangan Palsu, dan Pemalsuan Dokumen
Dalam praktik, Notaris sering menghadapi dilema ketika akta yang dibuatnya dikaitkan dengan tindak pidana. Misalnya, penyidik dapat menyita protokol atau minuta akta korporasi yang kemudian terbukti digunakan untuk tindak pidana, tanpa mengindahkan fakta bahwa Notaris telah mengikuti prosedur UUJN. Hal ini menunjukkan bagaimana jabatan preventif dapat bertransformasi menjadi tanggung jawab retrospektif.
Pasal 392 KUHP Baru mengatur pidana atas pemalsuan surat, sementara Pasal 394 menegaskan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta. Tujuan norma ini (ratio legis) adalah melindungi kepastian hukum, menjaga kepercayaan publik terhadap dokumen resmi, dan mencegah peredaran informasi yang menyesatkan dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian, undang-undang menekankan integritas dokumen sebagai fondasi transaksi hukum dan instrumen penguatan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas publik.
Dalam praktik kenotariatan, Notaris tidak menciptakan isi akta, melainkan mencatat dan mengesahkan pernyataan para pihak sesuai dengan fungsi verlijden notaris. Namun, apabila dokumen ternyata mengandung keterangan palsu, Notaris berpotensi dipandang lalai dalam melakukan verifikasi, meskipun seluruh prosedur yang diatur UUJN telah dijalankan. Situasi ini mencerminkan ketegangan inheren antara fungsi preventif Notaris—sebagai penjaga kepastian hukum—dengan konstruksi pidana yang menempatkan akibat materiil sebagai tolok ukur pertanggungjawaban, sehingga penilaian hukum harus mempertimbangkan proporsionalitas, kehati-hatian profesional, dan batas kewenangan jabatan.
Bayangkan seorang Notaris di ruang kerjanya, pena di tangan, menuliskan akta pengikatan jual beli tanah. Pihak penghadap menyerahkan sertifikat yang tampak sah, dan Notaris, dengan ketelitian dan integritasnya, memverifikasi identitas, memeriksa dokumen, dan menunaikan seluruh prosedur administratif yang diwajibkan UU Jabatan Notaris. Namun, di luar kendalinya, sertifikat itu palsu. Akta yang tercatat dengan tinta kepercayaan itu kini bisa ditafsirkan mengandung keterangan palsu oleh penyidik, membuka risiko dijerat Pasal 394 KUHP Baru. Dalam satu tarikan napas, jabatan preventif yang mulia ini—oficium nobile—yang lahir dari kepercayaan masyarakat (officium trust) dan diperkuat mandat negara (officium publicum) untuk menyajikan alat bukti di pengadilan, berubah menjadi medan ujian, di mana kehati-hatian profesional dan kepercayaan publik diuji oleh bayang-bayang pertanggungjawaban pidana. Notarii officium nobile est, ex fiducia publicae (officium trust) orta, simulque mandato civitatis (officium publicum) instrumenta probatoria in iudicio praebere. Di sinilah paradoks jabatan preventif: pena yang menulis kepastian hukum sekaligus dapat menjeratnya, dan setiap garis yang dicatat bukan sekadar catatan formal, tetapi saksi bisu dari kepercayaan masyarakat—yang menuntut perlindungan, keberanian, dan kebijaksanaan untuk menegakkan keadilan.
Dokumen Niaga dan Konosemen: Ancaman bagi Jabatan Preventif
Pasal 486 dan 501 KUHP Baru mengatur pidana penggunaan dokumen palsu dan penyalahgunaan dokumen angkutan barang (konosemen). Dalam praktik ekspor-impor dan transaksi korporasi, Notaris berperan dalam legalisasi dokumen niaga. Jika dokumen tersebut dipalsukan atau disalahgunakan, Notaris dapat dikaitkan sebagai pihak yang “memfasilitasi” tindak pidana, meskipun tidak mengetahui niat penghadap.
Bayangkan ketika Notaris menandatangani konosemen ekspor, setiap langkah telah dijalankan dengan ketelitian penuh: identitas pihak diperiksa, dokumen diverifikasi, akta disusun sesuai kaidah UU Jabatan Notaris (UUJN). Di balik tinta yang tertulis dengan rapi itu, tersimpan kepercayaan publik—officium trust—dan mandat negara—officium publicum. Namun, jika barang yang dikirim ternyata ilegal atau dokumen yang diserahkan palsu, akta yang dibuat Notaris bisa tiba-tiba berubah wujud menjadi alat bukti pidana, menempatkan jabatan preventif ini pada risiko struktural yang jauh melampaui kendali profesionalnya. Dalam sekejap, medan yang seharusnya aman sebagai panggilan mulia—oficium nobile—menjadi medan ranjau: setiap goresan pena bisa ditafsir sebagai kelalaian, setiap catatan formal bisa dipertanyakan di pengadilan. Tekanan untuk bersikap defensif muncul begitu nyata; pelayanan hukum tertahan, kepastian transaksi terguncang, dan kepercayaan publik diuji.
Padahal, Notaris bukanlah pihak yang menciptakan isi akta, melainkan penjaga kehendak hukum dan integritas dokumen. Posisi Notaris bukanlah pihak dalam pembuatan akta (notarius non est partis in instrumento constituto), sehingga ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di luar perbuatannya sendiri (nemo tenetur ad extra facta sua), baik secara pidana maupun perdata. Jabatan ini berdiri di persimpangan antara cahaya dan bayang-bayang: cahaya kepercayaan dan mandat publik yang mulia, bayang-bayang kemungkinan kriminalisasi yang mengintai. Setiap tinta yang dituangkan adalah janji—janji bahwa hak dan kewajiban akan diakui dan dihormati, bahwa hukum akan tetap menjadi pelindung, bukan ancaman. Menjaga jabatan Notaris berarti menjaga fondasi kepastian hukum itu sendiri; kehilangan ruang aman untuk melaksanakan oficium nobile sama artinya dengan kehilangan mercusuar keadilan di tengah gelombang kompleksitas zaman.
Korporasi sebagai Subjek Pidana dan Dampak pada Notaris
Pengakuan korporasi sebagai subjek pidana dalam Pasal 46–48 KUHP Baru menimbulkan risiko tambahan bagi Notaris. Jika korporasi melakukan tindak pidana, Notaris yang memfasilitasi pendirian, perubahan anggaran dasar, atau legalisasi dokumen dapat ditarik ke ranah pidana sebagai pihak yang “membiarkan” atau “memfasilitasi” tindak pidana.
Bayangkan Notaris yang menandatangani akta pendirian sebuah perseroan terbatas, menjalankan setiap prosedur dengan teliti: identitas para pendiri diverifikasi, dokumen diperiksa, dan akta disusun sesuai kaidah UU Jabatan Notaris (UUJN). Semua dilakukan untuk menegakkan kepastian hukum, menjunjung integritas formal, dan melindungi hak pihak yang terlibat. Namun, ketika korporasi itu ternyata menipu klien, akta yang awalnya bersih dan sah bisa berubah menjadi pusat sorotan penyidik. Notaris, meskipun tidak berperan dalam niat atau tindakan penipuan, berpotensi dipanggil sebagai saksi, atau bahkan tersangka, dalam konstruksi pidana retrospektif. Kasus ini menegaskan paradoks jabatan preventif: lex generalis KUHP dapat meluas menutupi risiko pidana, sehingga perlindungan yang semestinya diberikan lex specialis UUJN seolah tergerus. Posisi Notaris, yang seharusnya berdiri sebagai guardian of legal certainty, menjadi medan tipis antara menjalankan tugas mulia—oficium nobile, lahir dari kepercayaan publik (officium trust) dan mandat negara (officium publicum)—dengan bayang-bayang kriminalisasi yang dapat menghantui setiap langkah profesionalnya.
Alasan Pembenar dalam KUHP Baru: Pasal 31 sebagai Benteng Legalitas Jabatan
Pasal 31 KUHP Baru menegaskan salah satu pilar klasik hukum pidana modern, yakni alasan pembenar (justification ground). Norma ini menyatakan bahwa setiap orang tidak dipidana atas perbuatan yang pada dasarnya dilarang, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan konstruksi demikian, hukum pidana mengakui bahwa tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur delik secara formil layak dipidana, apabila perbuatan tersebut berada dalam koridor kewajiban hukum yang sah.
Secara doktriner, Pasal 31 merupakan pengejawantahan asas lex imperat, non punit—hukum yang memerintah tidak sekaligus menghukum. Negara tidak dapat secara kontradiktif memerintahkan suatu tindakan melalui undang-undang, lalu menghukum pelaksanaannya. Dalam konteks ini, alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), bukan sekadar menghapus kesalahan pribadi.
Bagi Notaris, Pasal 31 memiliki arti strategis. Setiap tindakan yang dilakukan in executione officii—dalam pelaksanaan jabatan—berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau peraturan perundang-undangan lainnya, berada dalam ruang perlindungan pidana. Pembuatan akta sesuai prosedur, pemenuhan kewajiban formil, hingga penggunaan hak ingkar untuk menjaga rahasia jabatan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pasal 31 dengan demikian berfungsi sebagai normative shield, yang mencegah hukum pidana berubah menjadi instrumen kriminalisasi jabatan preventif.
Prinsip Kesalahan sebagai Fondasi Pertanggungjawaban: Pasal 36 KUHP Baru
Pasal 36 KUHP Baru meneguhkan asas fundamental nulla poena sine culpa—tiada pidana tanpa kesalahan. Ayat (1) menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus) atau karena kealpaan (culpa). Ayat (2) selanjutnya mempersempit ruang pemidanaan atas kealpaan dengan menegaskan bahwa tindak pidana karena kealpaan hanya dapat dipidana apabila secara tegas ditentukan oleh undang-undang.
Secara sistematik, ketentuan ini menempatkan kesengajaan sebagai default mental element dalam hukum pidana. Setiap tindak pidana harus diasumsikan dilakukan dengan sengaja, dan unsur kesengajaan tersebut wajib dibuktikan secara aktif pada setiap tahap pemeriksaan perkara—dari penyelidikan hingga persidangan. Bentuk kesengajaan dalam peraturan perundang-undangan biasanya dirumuskan melalui frasa “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, atau “padahal diketahuinya”, yang semuanya menunjuk pada kesadaran batin pelaku terhadap akibat perbuatannya.
Dalam konteks jabatan Notaris, Pasal 36 berfungsi sebagai filter kriminalisasi. Pemalsuan akta, penyertaan keterangan palsu, atau manipulasi kehendak para pihak yang dilakukan dengan kesengajaan jelas membuka ruang pertanggungjawaban pidana. Namun, kesalahan administratif, kekeliruan prosedural, atau kelalaian yang tidak secara tegas dipidana oleh undang-undang tidak serta-merta dapat ditarik ke ranah pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak boleh direduksi menjadi liability without fault, terlebih terhadap pejabat preventif yang bekerja dalam batas kewenangan formal.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Pasal 45–50 KUHP Baru
KUHP Baru memperluas cakupan subjek hukum pidana dengan secara eksplisit mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 45). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang memandang kejahatan korporasi sebagai organizational wrongdoing, bukan sekadar kesalahan individual.
Pasal 46 dan Pasal 47 menguraikan siapa yang dapat dianggap melakukan tindak pidana atas nama korporasi, yakni pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, maupun pihak di luar struktur formal yang memiliki kendali nyata (controlling mind atau beneficial owner). Konstruksi ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak lagi bergantung pada struktur formal semata, tetapi pada realitas pengendalian dan pengambilan keputusan.
Pasal 48 kemudian menetapkan syarat pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain adanya keterkaitan dengan lingkup usaha, keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, penerimaan sebagai kebijakan korporasi, kegagalan melakukan pencegahan, atau pembiaran terjadinya tindak pidana. Norma ini mencerminkan prinsip corporate fault, bahwa kesalahan korporasi dapat bersumber dari budaya organisasi, kebijakan internal, atau kelalaian sistemik.
Pasal 49 memperluas subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara kumulatif, baik terhadap korporasi maupun individu di dalamnya. Sementara itu, Pasal 50 memberikan konsekuensi penting: alasan pembenar dan pemaaf yang dapat diajukan oleh individu juga dapat diajukan oleh korporasi, sepanjang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan. Prinsip ini menegaskan bahwa bahkan dalam rezim pidana korporasi, hukum tetap menjunjung asas keadilan dan proporsionalitas.
Dalam praktik kenotariatan, ketentuan ini relevan ketika Notaris terlibat dalam struktur atau kegiatan korporasi, baik sebagai pengurus fungsional maupun pihak yang menjalankan peran administratif tertentu. Namun, kembali pada Pasal 31 dan Pasal 36, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terdapat kesengajaan atau kealpaan yang secara tegas dipidana, dan tidak dapat dikenakan terhadap tindakan yang dilakukan semata-mata untuk melaksanakan perintah undang-undang.
Rangkaian Pasal 31, Pasal 36, dan Pasal 45–50 KUHP Baru membentuk satu bangunan sistemik: hukum pidana yang berorientasi pada kesalahan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap tindakan jabatan yang sah. Bagi Notaris, norma-norma ini bukan sekadar ketentuan teknis, melainkan constitutional guarantee agar jabatan preventif tidak tereduksi menjadi objek kriminalisasi prosedural.
Sebagaimana adagium klasik fiat justitia ne pereat officium—tegakkan keadilan agar jabatan tidak binasa—KUHP Baru menuntut pembacaan yang utuh dan berhati-hati. Perlindungan terhadap Notaris bukanlah pelemahan hukum pidana, melainkan syarat mutlak bagi tegaknya kepastian hukum dan kepercayaan publik dalam negara hukum yang beradab.
Pidana Denda dalam KUHP Nasional: Rasionalisasi, Kategorisasi, dan Fleksibilitas Nilai
Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP Nasional menandai perubahan mendasar dalam politik pemidanaan (penal policy) Indonesia, khususnya terkait pidana denda sebagai instrumen sanksi yang bersifat ekonomis (pecuniary punishment). Dalam paradigma baru ini, pidana denda tidak lagi dipahami sebagai pelengkap pidana penjara, melainkan sebagai sarana pemidanaan yang mandiri, proporsional, dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi.
Pasal 78 ayat (1) mendefinisikan pidana denda sebagai kewajiban pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan. Formulasi ini menegaskan karakter in personam dari pidana denda: sanksi diarahkan langsung kepada subjek hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban individual. Ayat (2) kemudian menetapkan batas minimum umum sebesar Rp50.000,00 apabila undang-undang tidak menentukan minimum khusus. Ketentuan ini mencerminkan asas lex certa, sekaligus memberikan rambu batas agar pemidanaan tidak jatuh ke dalam bentuk simbolik yang kehilangan daya korektif.
Lebih jauh, penjelasan Pasal 78 menautkan satuan minimum denda dengan upah minimum harian, yang secara implisit menunjukkan orientasi keadilan distributif (distributive justice). Dengan demikian, pidana denda tidak dilepaskan dari konteks kemampuan ekonomi masyarakat, sejalan dengan adagium poena debet esse proportionata delicto—pidana harus sebanding dengan perbuatan dan kondisi pelaku.
Sistem Kategorisasi Denda: Dari Kepastian Normatif ke Elastisitas Kebijakan
Pasal 79 KUHP Nasional memperkenalkan sistem kategorisasi pidana denda (Kategori I–VIII), suatu pendekatan yang bersifat structured discretion. Alih-alih mencantumkan angka denda secara rigid dalam setiap delik, pembentuk undang-undang memilih model kategoris untuk menjamin konsistensi dan fleksibilitas sekaligus. Setiap kategori merepresentasikan tingkat keseriusan tindak pidana dan dampak sosial-ekonominya, dengan rentang maksimum mulai dari Rp1.000.000,00 hingga Rp50.000.000.000,00.
Secara konseptual, sistem ini menjawab dua kebutuhan fundamental hukum pidana modern. Pertama, kebutuhan akan kepastian hukum (legal certainty), karena hakim memiliki acuan normatif yang jelas mengenai batas maksimum pidana denda. Kedua, kebutuhan akan adaptabilitas (economic adaptability), sebagaimana ditegaskan Pasal 79 ayat (2), yang memungkinkan penyesuaian nilai denda melalui Peraturan Pemerintah apabila terjadi perubahan nilai uang. Dengan demikian, hukum pidana tidak tertinggal oleh inflasi atau fluktuasi moneter—sebuah antisipasi yang mencerminkan prinsip ius sequitur tempus.
Penjelasan Pasal 79 mengungkap rasionalitas matematis di balik kategori denda, yang disusun berdasarkan kelipatan tertentu dari minimum umum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemidanaan denda dirancang secara sistemik, bukan kasuistik, sehingga mampu menjaga koherensi antarjenis tindak pidana sekaligus memudahkan pembaruan kebijakan pidana di masa depan.
Implikasi Teoretis dan Praktis
Dengan konstruksi Pasal 78–79, pidana denda dalam KUHP Nasional berfungsi sebagai instrumen korektif yang rasional dan berkeadilan. Ia tidak hanya menghukum, tetapi juga mendorong kepatuhan hukum melalui mekanisme ekonomi yang terukur. Dalam konteks tindak pidana jabatan, korporasi, maupun pelanggaran administratif yang dipidana, sistem denda kategoris memungkinkan penjatuhan sanksi yang efektif tanpa harus selalu mengandalkan pidana penjara.
Pada titik ini, adagium ultimum remedium menemukan relevansinya: pidana penjara tidak lagi menjadi pilihan utama, sementara pidana denda tampil sebagai sarana pemidanaan yang lebih proporsional dan responsif. KUHP Nasional dengan demikian memperlihatkan orientasi baru—bahwa efektivitas hukum pidana tidak diukur dari beratnya sanksi, melainkan dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (certainty, justice, and utility).
Bab XIII KUHP Nasional: Pemalsuan Surat sebagai Delik terhadap Kepercayaan Publik
Bab XIII KUHP Nasional menempatkan tindak pidana pemalsuan surat sebagai kejahatan serius terhadap public trust dan legal certainty. Norma-norma dalam Pasal 391 sampai dengan Pasal 394 dirancang untuk melindungi integritas dokumen tertulis sebagai instrumen utama dalam lalu lintas hukum perdata, administrasi, dan pidana. Dalam perspektif teoritik, pemalsuan surat bukan semata delik terhadap harta kekayaan, melainkan delik terhadap sistem pembuktian itu sendiri (offences against evidentiary order). Di sinilah adagium fides publica est anima iuris menemukan relevansinya: kepercayaan publik adalah jiwa dari hukum.
Pasal 391: Pemalsuan Surat Umum dan Perlindungan Kepastian Formal
Pasal 391 mengatur bentuk dasar (basic offence) pemalsuan surat, dengan fokus pada surat yang mampu melahirkan akibat hukum—baik berupa hak, perikatan, pembebasan utang, maupun fungsi pembuktian. Unsur esensial pasal ini terletak pada tiga pilar: perbuatan memalsu atau membuat tidak benar (actus reus), maksud untuk menggunakan seolah-olah benar (mens rea), dan potensi kerugian (potential harm).
Penjelasan pasal ini memperluas makna “surat” sebagai segala representasi pikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan, termasuk salinan, fotokopi, dan faksimile. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang terhadap realitas pembuktian modern, di mana nilai hukum suatu dokumen tidak selalu ditentukan oleh keasliannya secara fisik, tetapi oleh fungsinya dalam menimbulkan kepercayaan. Dengan demikian, delik ini berorientasi pada formele waarheid, bukan pada kebenaran materiil dari peristiwa yang mendasarinya.
Ancaman pidana penjara hingga enam tahun atau denda kategori IV menunjukkan bahwa pemalsuan surat umum diposisikan sebagai kejahatan yang merusak tatanan kepastian hukum, namun masih berada pada spektrum umum sebelum memasuki rezim perlindungan dokumen yang memiliki nilai kepercayaan lebih tinggi.
Pasal 392: Pemalsuan Surat Tertentu dan Eskalasi Perlindungan Hukum
Pasal 392 merupakan bentuk qualified offence yang menaikkan derajat pemalsuan surat terhadap dokumen-dokumen yang memiliki nilai strategis bagi negara, pasar, dan kepentingan publik. Akta autentik, surat berharga negara, saham, sertifikat utang, surat kredit, hingga surat keterangan hak atas tanah ditempatkan dalam kategori dokumen yang dilindungi secara intensif.
Peningkatan ancaman pidana hingga delapan tahun penjara mencerminkan ratio legis yang jelas: semakin tinggi derajat kepercayaan publik yang dilekatkan pada suatu dokumen, semakin berat konsekuensi pidana atas pemalsuannya. Dalam konteks ini berlaku adagium ubi maior fides, ibi maior poena—di mana kepercayaan publik lebih besar, di sana sanksi harus lebih tegas.
Khusus terhadap akta autentik, pasal ini memiliki implikasi langsung terhadap profesi pejabat umum, termasuk Notaris. Akta autentik adalah perfect proof (probatio plena), sehingga setiap pemalsuan terhadapnya bukan hanya merugikan pihak tertentu, tetapi mengguncang legitimasi sistem pembuktian formal negara.
Pasal 393: Delik Persiapan dan Pencegahan Dini
Berbeda dari Pasal 391 dan 392 yang bersifat represif terhadap akibat, Pasal 393 memperkenalkan pendekatan preventif dengan mengkriminalisasi penyimpanan alat atau bahan yang diketahui digunakan untuk pemalsuan surat tertentu. Delik ini mencerminkan kebijakan kriminal modern yang tidak menunggu terjadinya kerugian aktual, tetapi bertindak pada tahap preparatory acts.
Ancaman pidana yang lebih ringan—penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II—menunjukkan proporsionalitas sanksi sesuai tingkat bahaya perbuatan. Perampasan atau pemusnahan alat pemalsuan juga menegaskan prinsip salus publica suprema lex, bahwa perlindungan kepentingan umum membenarkan intervensi negara bahkan sebelum kejahatan sempurna terjadi.
Pasal 394: Keterangan Palsu dalam Akta Autentik dan Paradoks Jabatan Preventif
Pasal 394 secara khusus mengatur perbuatan meminta dimasukkannya keterangan palsu ke dalam akta autentik. Norma ini menegaskan pemisahan peran antara pembuat akta dan pemberi keterangan. Subjek utama delik bukan pejabat pembuat akta, melainkan pihak yang secara sadar memanipulasi kebenaran formal melalui instrumen autentik.
Dalam konteks teori kenotariatan, pasal ini sejalan dengan prinsip notarius non iudicat: Notaris tidak menilai kebenaran materiil pernyataan para pihak, melainkan menjamin bahwa pernyataan tersebut dituangkan secara sah dan prosedural. Oleh karena itu, kriminalisasi diarahkan kepada pihak yang menyalahgunakan formele waarheid akta untuk tujuan melawan hukum.
Ancaman pidana hingga tujuh tahun penjara atau denda kategori VI menunjukkan bahwa keterangan palsu dalam akta autentik dipandang hampir setara dengan pemalsuan surat tertentu, karena akibatnya sama-sama merusak kepercayaan terhadap dokumen negara.
Secara keseluruhan, Bab XIII KUHP Nasional membangun sistem perlindungan berlapis terhadap dokumen tertulis sebagai tulang punggung kepastian hukum. Dari surat umum hingga akta autentik, dari perbuatan utama hingga tahap persiapan, pengaturan ini menunjukkan konsistensi antara legal policy dan legal philosophy. Pemalsuan surat tidak lagi dipahami sebagai kejahatan teknis semata, melainkan sebagai pelanggaran terhadap etika kepercayaan publik.
Dalam lanskap hukum modern, dokumen bukan sekadar kertas bertinta, melainkan simbol legitimasi negara. Ketika dokumen dipalsukan, yang runtuh bukan hanya hak individual, tetapi juga fondasi rule of law itu sendiri. Oleh karena itu, Bab XIII KUHP Nasional hadir sebagai penjaga senyap atas satu prinsip mendasar: veritas formalis est columna iustitiae—kebenaran formal adalah pilar keadilan.
Bab XVIII KUHP Nasional: Tindak Pidana Pembukaan Rahasia sebagai Pelanggaran terhadap Kepercayaan Institusional
Bab XVIII KUHP Nasional menempatkan pembukaan rahasia (breach of confidentiality) sebagai delik yang menyerang fondasi kepercayaan institusional dalam hubungan jabatan, profesi, dan dunia usaha. Rahasia dalam konteks ini bukan sekadar informasi tertutup, melainkan legal interest yang melekat pada relasi kepercayaan (fiduciary relationship) antara individu dan institusi. Oleh karena itu, norma Pasal 443 sampai dengan Pasal 445 dirancang untuk melindungi bukan hanya kepentingan privat, tetapi juga tertib sosial dan legitimasi profesi.
Adagium klasik fides servanda est—kepercayaan harus dijaga—menjadi benang merah dari keseluruhan pengaturan ini. Tanpa jaminan kerahasiaan, relasi profesional akan kehilangan makna etik dan yuridisnya.
Pasal 443: Rahasia Jabatan dan Profesi sebagai Manifestasi Kepercayaan Negara
Pasal 443 ayat (1) mengkriminalisasi perbuatan membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan, profesi, atau tugas dari instansi pemerintah. Kewajiban ini bersifat melekat (inherent duty), tidak terbatas pada masa jabatan, melainkan juga mencakup rahasia yang diperoleh di masa lalu. Dengan demikian, negara menegaskan bahwa kewajiban menjaga rahasia bersifat berkelanjutan (continuing obligation).
Penjelasan pasal ini memperluas makna “rahasia” sebagai segala sesuatu yang secara hukum atau kebiasaan hanya boleh diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Contoh kewajiban dokter terhadap pasien atau arsiparis terhadap berkas rahasia menegaskan bahwa delik ini melampaui sektor pemerintahan semata dan mencakup profesi dengan duty of confidentiality yang kuat.
Ayat (2) menempatkan pembukaan rahasia orang lain sebagai delik aduan (klacht delict). Formulasi ini menunjukkan kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam menyeimbangkan public interest dan private autonomy. Negara tidak serta-merta memaksakan penuntutan pidana, melainkan menghormati kehendak korban sebagai pemilik kepentingan hukum. Di sini berlaku adagium volenti non fit iniuria—tanpa keberatan dari pihak yang dirugikan, negara menahan diri.
Pasal 444: Rahasia Perusahaan dan Perlindungan Persaingan Usaha yang Sehat
Pasal 444 memperluas rezim perlindungan rahasia ke dalam ranah korporasi, dengan mengkriminalisasi pembocoran hal khusus mengenai perusahaan oleh orang yang bekerja atau pernah bekerja di dalamnya. Norma ini secara eksplisit diarahkan untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat (unfair competition), sebagaimana ditegaskan dalam penjelasannya.
Dalam perspektif hukum pidana ekonomi, rahasia perusahaan—termasuk trade secrets dan informasi strategis—merupakan aset tak berwujud (intangible assets) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pembukaannya secara melawan hukum bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mendistorsi mekanisme pasar. Oleh karena itu, ancaman pidana diperberat menjadi penjara paling lama dua tahun, meskipun tetap dikualifikasikan sebagai delik aduan oleh pengurus perusahaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa negara bertindak sebagai penjaga fair play, bukan sebagai aktor yang mengambil alih konflik internal korporasi tanpa permintaan.
Pasal 445: Pidana Tambahan dan Dimensi Etik Jabatan
Pasal 445 membuka kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf a, b, c, dan/atau f KUHP Nasional. Pidana tambahan ini menempatkan delik pembukaan rahasia dalam dimensi etik-profesional, bukan sekadar pelanggaran hukum pidana biasa.
Pencabutan hak—seperti hak memegang jabatan tertentu atau menjalankan profesi—merupakan bentuk moral sanction yang menegaskan bahwa pelanggaran rahasia mencerminkan ketidaklayakan etik (unfitness) untuk tetap memegang posisi kepercayaan. Di sinilah adagium honos officium sequitur berlaku: kehormatan jabatan mengikuti integritas pemegangnya.
Bab XVIII KUHP Nasional menegaskan bahwa rahasia bukanlah privilese personal semata, melainkan institusi hukum yang menjaga martabat profesi, legitimasi jabatan, dan stabilitas dunia usaha. Dengan mengkualifikasikan sebagian besar delik pembukaan rahasia sebagai delik aduan, pembentuk undang-undang menunjukkan pendekatan moderat yang menghindari over-criminalization, sekaligus tetap menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif.
Dalam lanskap hukum modern, keterbukaan informasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan kerahasiaan yang sah. Tanpa batas yang jelas, transparansi dapat berubah menjadi pelanggaran; sebaliknya, tanpa sanksi, kerahasiaan kehilangan makna normatifnya. Oleh karena itu, Bab XVIII KUHP Nasional berdiri sebagai penegasan prinsip fundamental: secretum est fundamentum fiduciae—rahasia adalah fondasi kepercayaan.
Bab XXVI KUHP Nasional: Penggelapan sebagai Penyalahgunaan Penguasaan yang Sah
Bab XXVI KUHP Nasional menempatkan penggelapan (embezzlement) sebagai tindak pidana terhadap harta benda yang berakar pada penyalahgunaan kepercayaan (abuse of trust). Berbeda dari pencurian (theft), penggelapan tidak diawali oleh pengambilan secara melawan hukum, melainkan oleh penguasaan yang semula sah, yang kemudian bertransformasi menjadi perbuatan melawan hukum pada saat timbulnya kehendak untuk memiliki (animus rem sibi habendi).
Pasal 486 secara tegas merumuskan bahwa objek penggelapan adalah barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana. Frasa ini merupakan unsur pembeda utama (distinctive element) antara penggelapan dan pencurian. Dalam konstruksi ini, hukum pidana tidak mengkriminalisasi fakta penguasaan, melainkan pergeseran niat batin yang kemudian diwujudkan dalam tindakan memiliki secara melawan hukum.
Penjelasan Pasal 486 menegaskan dimensi temporal dari kesalahan (mens rea). Apabila niat memiliki telah ada sejak awal penguasaan, maka perbuatannya jatuh ke dalam rezim pencurian. Sebaliknya, pada penggelapan, niat jahat tersebut lahir setelah hubungan hukum yang sah berlangsung. Oleh karena itu, penggelapan seringkali muncul dalam konteks hubungan perdata—misalnya penitipan, jaminan utang, atau penguasaan karena pekerjaan—yang kemudian diselewengkan.
Dalam perspektif normatif, pengaturan ini mencerminkan adagium fiducia rupta, ius violatum—ketika kepercayaan dilanggar, hukum pun dilukai. Ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda kategori IV menunjukkan bahwa negara memandang serius pelanggaran terhadap kepercayaan sebagai fondasi relasi sosial dan ekonomi.
Bab XXVII KUHP Nasional: Perbuatan Curang sebagai Manipulasi Kehendak Korban
Jika penggelapan bertumpu pada penyalahgunaan penguasaan, maka penipuan (fraud) dalam Bab XXVII bertumpu pada penyesatan kehendak (vitiated consent). Pasal 492 merumuskan penipuan sebagai tindak pidana di mana pelaku tidak secara langsung merugikan korban melalui perbuatannya sendiri, melainkan melalui perbuatan korban yang digerakkan oleh tipu daya.
Ciri khas penipuan terletak pada penggunaan sarana tertentu yang bersifat limitatif (numerus clausus), yakni nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong. Sarana ini berfungsi sebagai instrumen manipulasi psikologis yang menimbulkan kepercayaan semu (false belief), sehingga korban secara sukarela menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.
Penjelasan Pasal 492 menegaskan bahwa penipuan merupakan delik materiil, yang baru dianggap selesai ketika akibat yang dikehendaki pelaku benar-benar terjadi. Dengan demikian, hubungan kausal (causal nexus) antara tipu daya dan tindakan korban menjadi elemen esensial. Tanpa adanya hubungan sebab akibat tersebut, perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai penipuan.
Pasal 493 kemudian mengkhususkan penipuan dalam konteks hubungan jual beli, dengan menitikberatkan pada penyimpangan prestasi oleh penjual. Norma ini menegaskan bahwa penipuan tidak selalu berbentuk kebohongan verbal, tetapi juga dapat berwujud penyerahan prestasi yang menyimpang (fraudulent performance).
Selanjutnya, Pasal 494 memperkenalkan rezim penipuan ringan, yang didasarkan pada nilai objek atau keuntungan yang relatif kecil. Pendekatan ini mencerminkan asas ultimum remedium, di mana hukum pidana digunakan secara proporsional dan tidak berlebihan, dengan mengalihkan respons negara pada pidana denda semata.
Penggelapan dan Penipuan dalam Peta Delik Harta Benda
Secara dogmatis, penggelapan (Pasal 486) dan penipuan (Pasal 492–494) menempati dua kutub berbeda dalam spektrum tindak pidana terhadap harta benda. Penggelapan melanggar kepercayaan atas penguasaan, sedangkan penipuan melanggar kepercayaan atas informasi dan kehendak. Keduanya bertemu pada satu titik temu normatif: perlindungan integritas hubungan sosial dan ekonomi.
Perbedaan waktu lahirnya niat jahat, cara terjadinya kerugian, serta peran korban dalam terwujudnya akibat pidana menjadi parameter utama dalam membedakan kedua delik tersebut. Oleh karena itu, adagium dolus malus non praesumitur—niat jahat tidak boleh diasumsikan—menjadi prinsip penting dalam penerapan pasal-pasal ini secara cermat dan adil.
Dengan konstruksi demikian, KUHP Nasional menunjukkan pendekatan yang lebih sistematis dan berlapis dalam melindungi harta benda, tidak hanya sebagai objek ekonomi, tetapi sebagai refleksi dari kepercayaan, itikad baik (good faith), dan kepastian hukum dalam masyarakat.
Pasal 501 KUHP Nasional: Konosemen sebagai Titik Temu Hukum Pidana, Dagang, dan Kepercayaan
Pasal 501 KUHP Nasional merepresentasikan kriminalisasi yang bersifat sektoral-spesifik (sector-specific criminalization), yang lahir dari kebutuhan melindungi kepastian hukum dalam lalu lintas perdagangan dan pengangkutan barang. Konosemen (bill of lading) dalam norma ini tidak sekadar dipandang sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai surat berharga (negotiable instrument) yang mengandung nilai ekonomis dan hak kebendaan.
Penjelasan Pasal 501 menegaskan perbedaan fundamental antara konosemen asli dan salinan konosemen. Konosemen asli (lembar pertama) memiliki karakter title document, yakni surat yang mewakili barang (document of title), sehingga penguasaannya berarti penguasaan atas barang itu sendiri. Sebaliknya, salinan atau lembaran lainnya bersifat informatif semata dan tidak memiliki daya legitimasi kebendaan.
Kriminalisasi dalam Pasal 501 diarahkan pada perbuatan membebani salinan konosemen dengan perjanjian timbal balik kepada beberapa penerima barang. Perbuatan ini mengandung penyesatan struktural (institutional deception), karena pelaku secara sadar memperlakukan dokumen yang tidak bernilai sebagai seolah-olah bernilai kebendaan. Dalam konteks ini, hukum pidana melindungi bukan hanya kepentingan individual penerima barang, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan.
Adagium nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet—seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi apa yang dimilikinya—menjadi dasar filosofis pasal ini. Pemegang salinan konosemen pada hakikatnya tidak memiliki hak kebendaan apa pun, sehingga setiap pengalihan atau pembebanan yang dilakukannya bersifat semu dan menyesatkan.
Ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda kategori IV menunjukkan bahwa Pasal 501 ditempatkan di antara delik penipuan (Pasal 492) dan delik penggunaan dokumen palsu (Pasal 486), namun dengan objek khusus berupa konosemen. Dengan demikian, Pasal 501 memperkaya tipologi tindak pidana harta benda dalam KUHP Nasional dengan nuansa hukum dagang dan logistik modern.
Pasal 521 KUHP Nasional: Perlindungan Integritas Benda sebagai Kepentingan Hukum
Berbeda dengan Pasal 501 yang berfokus pada dokumen dan representasi hukum atas barang, Pasal 521 KUHP Nasional menitikberatkan pada perlindungan fisik dan fungsional barang sebagai objek kepemilikan. Norma ini mengatur tindak pidana perusakan dan penghancuran barang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik (property right) dan ketertiban sosial.
Penjelasan Pasal 521 membedakan secara tegas antara merusak dan menghancurkan. Merusak dipahami sebagai perbuatan yang menurunkan fungsi barang untuk sementara (temporary impairment), sedangkan menghancurkan berarti meniadakan fungsi barang secara permanen (permanent destruction). Distingsi ini penting secara dogmatis karena berkaitan dengan tingkat keseriusan serangan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.
Pasal 521 ayat (1) mengkriminalisasi perbuatan merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang milik orang lain secara melawan hukum. Formulasi kumulatif ini mencerminkan pendekatan result-oriented, di mana fokus utama terletak pada akibat terhadap barang, bukan semata pada modus perbuatannya.
Ayat (2) memperkenalkan klasifikasi berdasarkan nilai kerugian, dengan ambang batas Rp500.000,00 sebagai indikator proporsionalitas pemidanaan. Pendekatan ini sejalan dengan asas de minimis non curat lex—hukum tidak mengurusi hal yang terlalu kecil—serta menegaskan orientasi KUHP Nasional pada keadilan substantif dan efisiensi pemidanaan.
Dalam konteks sistem pemidanaan baru, Pasal 521 juga harus dibaca bersama Pasal 78–79 KUHP Nasional tentang kategori denda. Dengan demikian, pidana denda tidak lagi bersifat simbolik, melainkan menjadi instrumen korektif yang adaptif terhadap nilai kerugian dan kondisi ekonomi.
Pasal 501 dan Pasal 521 menunjukkan dua wajah perlindungan hukum pidana terhadap harta benda: yang satu melindungi kepercayaan dalam lalu lintas dokumen dan perdagangan, yang lain melindungi integritas fisik dan fungsi barang. Keduanya menegaskan bahwa KUHP Nasional tidak lagi memandang harta benda secara sempit, melainkan sebagai simpul relasi hukum, ekonomi, dan sosial.
Dengan konstruksi demikian, adagium ubi societas, ibi ius menemukan aktualisasinya: di mana terdapat kompleksitas hubungan sosial dan ekonomi modern, di situ hukum pidana hadir untuk menjaga kepercayaan, kepastian, dan keadilan.
Analisis Risiko Terpadu: Jabatan Preventif di Persimpangan
Dengan mengintegrasikan Pasal 222 KUHAP Baru serta Pasal 392, 394, 486, 501, dan 46–48 KUHP Baru, risiko yang mengancam Notaris muncul secara multilapis, membentuk medan kompleks yang menuntut kehati-hatian sekaligus keberanian profesional.
Kesatu, pada dimensi administratif versus pidana, kesalahan prosedural sekecil apa pun dapat bertransformasi menjadi delik pidana, meskipun tanpa dolus—menegaskan adagium klasik nemo tenetur ad extra facta sua, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di luar perbuatannya sendiri.
Kedua, pada dimensi preventif versus retrospektif, fungsi preventif Notaris yang seharusnya menjadi benteng pencegahan sengketa kini dikonversi menjadi evaluasi retrospektif; akta yang semula berfungsi sebagai instrumentum probatorium bisa menjadi objek pengawasan pidana, menciptakan chilling effect yang menekan keberanian dan integritas jabatan.
Ketiga, pada dimensi korporasi versus individu, tanggung jawab korporasi (responsabilitas societatis) kerap menarik Notaris ke ranah pidana, meskipun perannya terbatas pada fasilitasi formal, sehingga pejabat preventif ini berada di persimpangan antara officium nobile dan bayang-bayang kriminalisasi.
Keempat, pada dimensi integritas akta, penyitaan protokol dan akses digital (archiva digitalia) menimbulkan risiko hilangnya nilai bukti formal (valorem probatorium), sekaligus mengancam kepastian hukum (certitudo iuris) yang menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap jabatan mulia ini.
Kerangka four point determination menempatkan empat titik krusial sebagai jangkar keberlanjutan fungsi Notaris: risiko pidana yang mengintai dari luar kendali profesional, integritas akta yang menjadi saksi bisu kehendak hukum, kewajiban prosedural yang harus dijalankan dengan ketelitian dan kehati-hatian, serta perlindungan jabatan preventif yang menjaga agar pejabat ini tidak terseret ke dalam konstruksi pidana retrospektif. Keempat titik ini bukan sekadar konsep normatif; ia adalah peta bagi Notaris untuk menavigasi medan tipis antara pelayanan publik, tanggung jawab profesional, dan bayang-bayang kriminalisasi. Jika salah satu titik tergelincir—misalnya prosedur administratif dilewati atau integritas akta diragukan—maka seluruh keseimbangan jabatan preventif bisa goyah. Sebaliknya, ketika keempat titik ini dijaga dengan disiplin, jabatan Notaris tetap berdiri sebagai mercusuar kepastian hukum, mengokohkan oficium nobile yang lahir dari kepercayaan publik (officium trust) sekaligus mandat negara (officium publicum), di mana setiap akta bukan sekadar dokumen formal, tetapi juga simbol keadilan, tanggung jawab, dan kepercayaan yang memandu perjalanan hukum masyarakat.
Bayangkan Notaris yang tengah menandatangani akta pendirian sebuah korporasi. Setiap huruf yang tertulis di kertas itu adalah hasil verifikasi identitas, pemeriksaan dokumen, dan kepatuhan terhadap prosedur UU Jabatan Notaris. Namun kemudian korporasi itu menipu kliennya, dan akta yang telah dibuat dengan niat tulus menjadi alat bukti dalam konstruksi pidana retrospektif. Dari perspektif hukum, ini bukan sekadar masalah administratif; ini adalah medan di mana jabatan preventif diuji oleh lex generalis KUHP, yang kadang mengaburkan perlindungan lex specialis UUJN. Tekanan muncul bukan karena kelalaian Notaris, tetapi karena realitas bahwa risiko pidana bisa melingkari, bahkan ketika prosedur telah dipatuhi.
Di sinilah kerangka four point determination hadir sebagai peta penuntun. Risiko pidana, integritas akta, kewajiban prosedural, dan perlindungan jabatan preventif menjadi empat titik jangkar yang saling terkait—empat penopang yang menjaga agar Notaris tidak hanyut dalam pusaran retrospektif yang menghukum meski kesalahan bukan di tangannya. Risiko pidana menuntut kehati-hatian, integritas akta menuntut kesetiaan pada kebenaran formal, kewajiban prosedural menuntut disiplin tanpa kompromi, dan perlindungan jabatan preventif menegaskan bahwa Notaris bukan pihak yang menciptakan isi akta (notarius non est partis in instrumento constituto), sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di luar perbuatannya sendiri (nemo tenetur ad extra facta sua). Keempat titik ini bukan sekadar teori; ia adalah benteng yang menjaga oficium nobile, panggilan mulia yang lahir dari kepercayaan publik (officium trust) dan mandat negara (officium publicum), agar setiap akta tetap menjadi saksi sah dari kehendak hukum masyarakat.
Ilustrasi kasus itu menggugah kita untuk melihat paradoks jabatan preventif: cahaya kepercayaan publik yang begitu terang, namun bayang-bayang kriminalisasi selalu mengintai. Notaris harus menulis dengan ketelitian, menegakkan kepastian hukum dengan keberanian, dan menjaga integritas jabatan di tengah pusaran risiko struktural yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Inilah inti dari refleksi hukum kontemporer: bahwa menjaga Notaris berarti menjaga fondasi kepastian hukum, dan menjaga fondasi kepastian hukum berarti menegakkan keadilan yang sejati. Dalam setiap akta, tersimpan janji bahwa hukum bukan sekadar alat penghukuman, tetapi juga perisai yang meneguhkan kepercayaan publik—sebuah pesan abadi bahwa fides publicae est fundamentum juris, kepercayaan publik adalah fondasi hukum, dan officium nobile harus tetap terlindungi agar mercusuar kepastian hukum terus bersinar bagi seluruh masyarakat.
Analisis Normatif dan Komparatif
Secara normatif, Notaris berada di bawah payung lex specialis UU Jabatan Notaris (UUJN), berfungsi sebagai guardian of legal certainty dan menjalankan notariële geheimhouding sebagai fondasi kerahasiaan jabatan (secreta notarii). Dalam kerangka ini, setiap akta yang dibuat bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumentum fidei publica—perwujudan kehendak hukum para pihak yang harus dilindungi dengan integritas penuh. Namun, lex generalis KUHP dan KUHAP Baru membuka ruang interpretasi yang lebih luas bagi aparat penegak hukum, sehingga perlindungan jabatan preventif sering bertemu ketegangan dengan tujuan penegakan hukum pidana. Ketegangan ini semakin terasa ketika tindakan preventif yang sah secara prosedural—memverifikasi identitas, meneliti dokumen, dan menyusun akta sesuai kaidah UUJN—dapat ditafsirkan secara retrospektif sebagai kelalaian atau bahkan tindak pidana (culpa in contrahendo).
Dari perspektif komparatif, pengalaman sistem Prancis (notaire) dan Jerman (Notarrecht) menawarkan contoh perlindungan jabatan preventif yang eksplisit dan sistemik. Di kedua yurisdiksi tersebut, penyitaan dokumen hanya dapat dilakukan dalam kondisi terbatas dan dengan izin pengadilan (permissio iudicialis), sementara pertanggungjawaban pidana menuntut pembuktian kesengajaan (Vorsatz) atau kelalaian berat (grobe Fahrlässigkeit). Pendekatan ini menegaskan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan pejabat preventif—menghargai integritas akta dan kepercayaan publik (fides publicae) tanpa mengorbankan hak-hak profesional Notaris. Bandingkan dengan KUHP dan KUHAP Baru di Indonesia, yang meski membawa modernisasi normatif, masih menghadirkan tantangan dalam menjaga agar pejabat preventif tetap aman dari risiko kriminalisasi struktural, sekaligus memastikan hukum hadir sebagai instrumen keadilan dan kepastian bagi masyarakat (iustitia et securitas publica).
Menjaga Jabatan Preventif dalam Arsitektur Hukum Futuristik
Transformasi KUHP dan KUHAP Baru menegaskan bahwa Notaris berdiri di persimpangan risiko struktural yang kompleks: administratif versus pidana (administrativa vs. criminalis), preventif versus retrospektif (praeventiva vs. retrospectiva), individu versus korporasi (persona vs. societas), dan integritas akta (integritas instrumenti). Tanpa pengaturan normatif yang tegas, jabatan preventif ini berpotensi berubah menjadi sasaran kriminalisasi (criminatio structuralis), melemahkan kepastian hukum formal (certitudo iuris) dan mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi yang bergantung pada kepastian dokumen hukum.
Dalam konteks itu, penyelarasan normatif, penguatan lex specialis UUJN, dan perlindungan prosedural melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menjadi penopang agar Notaris tetap berfungsi sebagai guardian of legal certainty. Hukum pidana harus kembali pada peranannya sebagai ultimum remedium, bukan instrumen yang menakut-nakuti pejabat preventif (officium nobile). Quo vadis jabatan Notaris kini bergantung pada kemampuan pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum untuk menempatkan keadilan substantif (iustitia substantiva) di atas ketakutan struktural, menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan profesi yang esensial bagi kelangsungan kepastian hukum nasional.
Evolusi Historis dan Transformasi Jabatan Preventif
Transformasi KUHP dan KUHAP Baru—sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP—menempatkan Notaris pada persimpangan risiko struktural yang multilapis: administratif versus pidana (administrativa vs. criminalis, Pasal 392, 394, 486, 501 KUHP Baru), preventif versus retrospektif (praeventiva vs. retrospectiva, Pasal 222 KUHAP Baru), individu versus korporasi (persona vs. societas, Pasal 46–48 KUHP Baru), dan integritas akta (integritas instrumenti, UUJN Pasal 16, Pasal 66). Kesalahan prosedural yang sejatinya bersifat administratif dapat bertransformasi menjadi delik pidana walaupun tanpa dolus (culpa levis), sementara fungsi preventif Notaris—yang seharusnya mencegah sengketa melalui akta autentik (notariële akte)—terkadang dikonversi menjadi penilaian retrospektif oleh aparat penegak hukum, menciptakan chilling effect yang nyata bagi praktik kenotariatan.
Tanpa penyelarasan normatif yang tegas, jabatan preventif ini berisiko menjadi sasaran kriminalisasi struktural (criminatio structuralis), mengikis kepastian hukum formal (certitudo iuris) dan menurunkan kepercayaan publik (fides publicae), sementara aktivitas ekonomi yang bergantung pada dokumen hukum melambat. Penyelarasan melalui lex specialis UUJN, perlindungan prosedural Majelis Kehormatan Notaris (MKN), serta penerapan adagium klasik notarius non est partis in instrumento constituto dan nemo tenetur ad extra facta sua menjadi kunci agar Notaris tetap berperan sebagai guardian of legal certainty, menjaga integritas akta sekaligus melindungi diri dari tuntutan pidana yang tidak semestinya.
Dalam perspektif komparatif, sistem Prancis (notaire) dan Jerman (Notarrecht) menegaskan prinsip bahwa penyitaan dokumen dan pertanggungjawaban pidana terbatas pada kesengajaan (dolus) atau kelalaian berat (grobe Fahrlässigkeit), menunjukkan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum (efficacia iuris) dan perlindungan jabatan preventif (officium nobile). KUHP dan KUHAP Baru di Indonesia masih menghadapi tantangan untuk menegaskan batas ini, agar hukum pidana tetap menjadi ultimum remedium, bukan instrumen yang menakut-nakuti pejabat preventif yang melayani kepercayaan publik (officium trust) sekaligus mandat negara (officium publicum).
Quo vadis jabatan Notaris bergantung pada kemampuan pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum untuk menempatkan iustitia substantiva di atas ketakutan struktural, menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan profesi yang esensial bagi kepastian hukum nasional. Menjaga Notaris berarti menjaga mercusuar kepastian hukum di tengah arus kompleksitas zaman, di mana setiap tinta yang dituangkan dalam akta adalah saksi bisu dari kepercayaan publik dan integritas institusi—sebuah pengingat bahwa fides publicae est fundamentum juris.
Jabatan Preventif sebagai Pilar Kepastian Hukum
Notaris bukan sekadar pencatat akta; ia adalah penjaga fondasi integritas ekosistem hukum formal (officium nobile). Jabatan preventifnya menegaskan bahwa setiap akta autentik adalah cerminan kepatuhan prosedural dan kebenaran formal (formele waarheid), yang membedakannya dari penilaian materiil (materiële waarheid). Akta tersebut bukan hanya dokumen administratif, melainkan alat bukti tertulis (instrumentum probatorium) yang diakui di persidangan dan menjadi pilar kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.
Namun, bayang-bayang kriminalisasi struktural mengintai. Tafsir agresif terhadap keterangan pihak penghadap atau penyitaan arsip digital (digitalia instrumenta) dapat mengubah jabatan preventif yang mulia ini menjadi sumber risiko pidana yang berada di luar kendali profesionalnya. Tekanan ini memaksa Notaris mengadopsi praktik defensif—menunda akta, membatasi layanan, atau berhati-hati secara berlebihan—yang pada gilirannya memperlambat akses masyarakat terhadap keadilan, melemahkan kepercayaan publik (fides publicae), dan meredam fungsi ekonomi yang bergantung pada kepastian hukum. Oleh karena itu, perlindungan normatif yang tegas—melalui lex specialis UUJN, mekanisme Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan prinsip klasik notarius non est partis in instrumento constituto serta nemo tenetur ad extra facta sua—menjadi instrumen vital untuk menegaskan bahwa hukum pidana tetap harus berperan sebagai ultimum remedium, bukan sebagai bayang-bayang yang menakut-nakuti pejabat preventif.
Di dunia nyata, setiap goresan pena Notaris adalah perwujudan kepercayaan publik (fides publicae) dan mandat negara (officium publicum). Bayangkan Notaris yang melegalkan konosemen ekspor: identitas pihak diverifikasi, dokumen diperiksa, akta disusun sesuai prosedur UUJN. Namun, jika barang yang dikirim ilegal atau dokumen ternyata palsu, akta itu, yang lahir dari upaya preventif, tiba-tiba menjadi alat bukti pidana. Atau ketika Notaris mengesahkan akta pendirian korporasi, dan perusahaan itu menipu kliennya: meskipun prosedur dijalankan dengan sempurna, penyidik dapat menafsirkan akta secara retrospektif, menempatkan Notaris di persimpangan tipis antara integritas dan kriminalisasi.
Inilah paradoks jabatan preventif—oficium nobile—yang lahir dari kepercayaan publik (officium trust) dan mandat negara (officium publicum), yang harus menavigasi medan hukum di mana setiap kesalahan administratif pihak lain bisa menimpa dirinya secara pidana. Posisi Notaris sesungguhnya bukanlah pihak dalam pembuatan akta (notarius non est partis in instrumento constituto), sehingga secara prinsip ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di luar perbuatannya sendiri (nemo tenetur ad extra facta sua). Namun, modernisasi KUHP dan KUHAP Baru, dengan tafsir yang agresif dan penyitaan arsip digital, menimbulkan bayang-bayang risiko yang nyata dan menakutkan.
Kerangka four point determination menjadi mercusuar dalam gelap ini. Empat titik krusial—risiko pidana, integritas akta, kewajiban prosedural, dan perlindungan jabatan preventif—mengikat seluruh fungsi Notaris dalam sebuah ekosistem hukum yang rapuh namun vital. Dimensi administratif versus pidana menunjukkan bahwa kelalaian formal dapat dikonversi menjadi delik pidana (culpa lata). Dimensi preventif versus retrospektif menegaskan bahwa jabatan hulu bisa diseret ke penilaian ex post, menimbulkan chilling effect. Dimensi individu versus korporasi menyoroti bahwa pertanggungjawaban perusahaan dapat menarik Notaris ke ranah pidana meski hanya terbatas pada fasilitasi formal (facultas instrumentalis). Dan dimensi integritas akta menegaskan bahwa penyitaan protokol atau akses arsip digital dapat merusak kepastian hukum (certitudo iuris) yang dijaga Notaris.
Di palung terdalam jabatan ini, terdapat ketegangan emosional yang tak bisa diabaikan: setiap akta yang dituangkan adalah saksi bisu dari kepercayaan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi pedang yang mengancam profesionalitasnya. Setiap prosedur preventif, meski dilaksanakan dengan cermat, berisiko diinterpretasikan sebagai kelalaian. Inilah dilema struktural yang hanya bisa diatasi dengan perlindungan normatif yang kuat: lex specialis UUJN, mekanisme Majelis Kehormatan Notaris, serta prinsip klasik bahwa Notaris tidak menilai niat batin (non iudicat sed certifica), sehingga hukum pidana tetap berfungsi sebagai ultimum remedium, bukan instrumen ancaman.
Akhirnya, menjaga Notaris berarti menjaga fondasi kepastian hukum. Menjaga kepercayaan publik adalah merawat fides publicae yang menjadi inti legitimasi hukum. Jabatan preventif yang mulia ini adalah mercusuar keadilan di tengah gelombang kompleksitas modern: officium nobile, lahir dari kepercayaan publik (officium trust), sekaligus mandat negara (officium publicum) untuk menyajikan alat bukti (instrumenta probatoria in iudicio praebere). Di sinilah hukum menunjukkan wajah terbaiknya—bukan sebagai alat penindas, tetapi sebagai perisai bagi mereka yang menegakkan kepastian, integritas, dan keadilan formal, sehingga masyarakat dan profesi hukum dapat saling mempercayai, berkembang, dan bertahan di tengah arus perubahan yang tak terelakkan.
Analisis Normatif dan Komparatif
Secara normatif, jabatan Notaris diatur sebagai lex specialis melalui UU Jabatan Notaris (UUJN), sementara KUHP dan KUHAP merupakan lex generalis. Keseimbangan antara kedua tatanan hukum ini menjadi kunci agar Notaris tidak secara otomatis terseret ke ranah pidana ketika menjalankan prosedur formal (proceduralis actus). Secara komparatif, sistem kenotariatan di Prancis (notaire) dan Jerman (Notarrecht) menegaskan perlindungan eksplisit bagi pejabat preventif: penyitaan dokumen hanya dapat dilakukan di bawah pengawasan dewan notaris atau ketika terbukti ada niat jahat (dolus) maupun kelalaian berat (grobe Fahrlässigkeit). Pendekatan ini menjaga integritas arsip, kerahasiaan jabatan (notariële geheimhouding), serta kepastian hukum formal (certitudo iuris), menegaskan adagium klasik bahwa ubi ius incertum, ibi nullum ius—di mana hukum tidak jelas, di situ tiada kepastian hukum—sehingga posisi Notaris tetap terlindungi sebagai officium nobile, lahir dari kepercayaan publik (officium trust) dan mandat negara (officium publicum).
Fakta Hukum dalam Praktik
Beberapa ilustrasi praktik nyata menyingkap kompleksitas jabatan preventif Notaris, yang berada di persimpangan antara kepercayaan publik dan bayang-bayang kriminalisasi. Misalnya, ketika Notaris membuat akta pengikatan jual beli tanah berdasarkan sertifikat palsu, seluruh prosedur formal telah dijalankan—identitas diverifikasi, dokumen diperiksa, dan akta disusun sesuai UU Jabatan Notaris—namun penyidik tetap dapat menilai akta mengandung keterangan palsu. Demikian pula, ketika melegalkan konosemen ekspor, barang atau dokumen yang bermasalah berpotensi menjadikan akta sebagai alat bukti pidana, menempatkan Notaris pada risiko struktural yang tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya. Bahkan legalitas akta pendirian korporasi dapat membawa Notaris ke ranah pidana jika korporasi melakukan tindak pidana, meskipun Notaris hanya bertindak sebagai fasilitator formal (notarius non est partis in instrumento constituto). Kasus-kasus ini menegaskan multilapisnya risiko pidana—dimensi administratif versus pidana, preventif versus retrospektif, individu versus korporasi, serta integritas akta (formele waarheid)—sebagaimana tercermin dalam Pasal 222 KUHAP Baru, Pasal 392, 394, 486, 501 KUHP Baru, dan Pasal 46–48 KUHP Baru. Kondisi ini menuntut lex specialis UUJN dan mekanisme perlindungan normatif agar jabatan preventif tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai guardian of legal certainty, menjaga kepercayaan publik (officium trust) dan mandat negara (officium publicum), sekaligus memastikan bahwa hukum pidana tetap berperan sebagai ultimum remedium, bukan alat menakut-nakuti mereka yang menyalurkan kehendak hukum secara sah (nemo tenetur ad extra facta sua).
Ius Constituendum dan Reformasi Legislasi
Transformasi jabatan preventif Notaris menuntut langkah-langkah strategis (ius constituendum) yang tidak sekadar normatif, tetapi juga reflektif terhadap fungsi sosial dan struktural jabatan ini, yaitu:
Pertama, perlindungan lex specialis harus ditegaskan: KUHP secara eksplisit mengakui Notaris sebagai pejabat preventif, sehingga pidana hanya berlaku bila terdapat keterlibatan aktif dan dolus. Hal ini menegaskan hierarki normatif antara UU Jabatan Notaris dan KUHP/KUHAP, menjaga agar jabatan preventif tidak otomatis terseret risiko retrospektif.
Kedua, penguatan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menjadi filter normatif yang vital: penyitaan protokol, minuta, atau arsip digital harus melalui MKN, kecuali dalam kondisi darurat. Mekanisme ini bukan hanya menjaga integritas arsip negara, tetapi juga menghormati kerahasiaan jabatan preventif (notariële geheimhouding) dan posisi Notaris sebagai guardian of legal certainty.
Ketiga, batasan pertanggungjawaban korporasi menegaskan bahwa Notaris bertindak sebagai fasilitator formal, bukan pengendali tindak pidana perusahaan. Penafsiran proporsional Pasal 46–48 KUHP Baru memastikan jabatan preventif tidak berubah menjadi sumber risiko pidana, sekaligus mencegah praktik defensif yang dapat memperlambat pelayanan hukum dan menurunkan kepastian transaksi.
Keempat, literasi dan edukasi aparat penegak hukum menjadi kunci agar prinsip integritas akta, fungsi preventif Notaris, dan asas in dubio pro reo dipahami secara menyeluruh. Dengan demikian, tafsir agresif terhadap akta autentik berkurang, dan pidana tetap berfungsi sebagai ultimum remedium.
Kelima, pendekatan bertahap yang memprioritaskan mekanisme administratif, etik, dan mediasi sebelum ranah pidana diterapkan, selaras dengan kerangka hukum futuristik, deterministik, dan responsif. Strategi ini menegaskan bahwa hukum pidana bukan alat pertama, tetapi instrumen terakhir yang menjaga keseimbangan keadilan dan kepastian hukum.
Integrasi kelima langkah ini membentuk ekosistem preventif Notaris yang utuh: jabatan preventif bukan sekadar pencatat akta, tetapi penghubung antara kepentingan publik, individu, dan korporasi. Perlindungan lex specialis, mekanisme MKN, batasan pertanggungjawaban korporasi, edukasi aparat penegak hukum, dan pendekatan bertahap menjaga integritas jabatan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik (officium trust), sehingga oficium nobile Notaris tetap bersinar sebagai mercusuar keadilan di tengah kompleksitas modernisasi hukum pidana.
Quo Vadis Jabatan Notaris
Sejak diberlakukannya KUHP dan KUHAP Baru, jabatan Notaris berdiri di persimpangan kritis, di mana cahaya kepercayaan publik (officium trust) bertemu bayang-bayang risiko kriminalisasi struktural. Transformasi hukum pidana menuju corrective justice menekankan pencegahan, perbaikan, dan integritas institusi, namun dalam praktiknya, Notaris dapat terseret tafsir agresif yang mengubah fungsi preventif menjadi sumber pertanggungjawaban pidana retrospektif. Sebagai guardian of legal certainty dan pelindung arsip negara, Notaris tidak sekadar mencatat, tetapi menyalurkan kehendak hukum para pihak ke dalam akta autentik yang menjadi fondasi hak dan kewajiban, sekaligus instrumen utama dalam peradilan.
Pertanyaan quo vadis jabatan Notaris bukan sekadar retoris. Ia adalah tantangan mendasar: menyeimbangkan perlindungan jabatan preventif (oficium nobile) dengan efektivitas hukum pidana yang tegas namun proporsional. Reformasi legislasi yang responsif, mekanisme pengawasan melalui Majelis Kehormatan Notaris, serta literasi aparat penegak hukum yang memadai menjadi kunci agar Notaris tetap dapat menavigasi medan tipis antara melayani kepastian hukum dan menghindari bayang-bayang kriminalisasi. Dengan perlindungan normatif yang jelas, jabatan preventif ini tetap bersinar sebagai mercusuar keadilan, sementara hukum pidana bertindak sebagai ultimum remedium, bukan alat yang menakut-nakuti. Dalam ekosistem hukum yang futuristik, deterministik, dan responsif, Notaris tetap menjadi penjaga integritas formal, pelindung akta autentik, dan simbol kepercayaan publik yang tak tergantikan.
Transformasi Posisi Notaris dalam Arsitektur Hukum Pidana Modern
Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP Baru) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, efektif sejak 2 Januari 2026, menandai transformasi mendasar dalam lanskap hukum nasional. Perubahan ini tidak hanya meredefinisi substansi delik dan prosedur pembuktian, tetapi secara langsung memengaruhi profesi notaris—pejabat preventif yang secara historis menjadi penjaga kepastian hukum perdata dan pilar integritas formal. Dalam perspektif ius integrum nusantara, notaris menjadi simpul integratif antara kepastian hukum, kepercayaan publik, dan ketertiban sosial, bertindak sebagai penjamin legalitas perbuatan hukum, pelindung arsip negara, dan fasilitator hak serta kewajiban hukum.
Namun, paradigma hukum pidana yang semakin deterministik, dengan perluasan jenis alat bukti, konstruksi delik yang lebih terbuka, dan kewenangan penyidikan yang luas, menempatkan jabatan preventif ini pada risiko struktural yang nyata. Melalui kerangka four point determination, terlihat bagaimana tujuan perlindungan hukum pidana yang sah justru dapat berubah menjadi sumber risiko: integritas akta, kepatuhan prosedural, tanggung jawab terhadap pihak korporasi, dan perlindungan jabatan preventif menjadi titik-titik krusial yang harus dijaga. Fungsi preventif notaris, yang seharusnya melindungi kepastian hukum, kini berpotensi dikonversi menjadi ranah retrospektif, di mana setiap akta atau dokumen bisa menjadi objek penyidikan dan setiap prosedur, walau sudah dijalankan dengan cermat, dapat ditafsirkan sebagai kelalaian atau kesalahan pidana. Jabatan preventif yang mulia (oficium nobile), lahir dari kepercayaan publik (officium trust) dan mandat negara (officium publicum), berada di persimpangan antara pelayanan hukum, integritas formal, dan bayang-bayang kriminalisasi struktural, menuntut kehati-hatian dan keberanian yang melampaui sekadar prosedur.
Penyitaan, Pembuktian, dan Degradasi Akta dalam Rezim KUHAP Baru
Pasal 222 KUHAP Baru, dengan perluasannya terhadap pengakuan alat bukti—surat, barang bukti, hingga data elektronik—menempatkan protokol, minuta akta, dan arsip digital notaris di persimpangan yang rapuh antara kewenangan penyidik dan kewajiban kerahasiaan jabatan. Notaris, yang secara historis berfungsi sebagai guardian of legal certainty, kini bisa menjadi subjek retrospektif dari tindak pidana yang lahir bukan dari kesalahannya sendiri, melainkan dari tindakan pihak penghadap atau tafsir agresif aparat penegak hukum. Penyitaan protokol berpotensi membuka data klien yang tidak terkait dengan perkara, menantang prinsip notariële geheimhouding dan perlindungan data, sementara akta autentik yang semula memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig en bindend bewijskracht) berisiko tereduksi menjadi sekadar bukti surat biasa.
Dalam praktiknya, ilustrasi nyata memperlihatkan kompleksitas ini: sertifikat palsu dalam akta jual beli tanah, konosemen ekspor yang bermasalah, hingga pendirian PT fiktif yang melakukan tindak pidana, semua bisa menarik notaris ke ranah pidana meski seluruh prosedur UUJN telah dijalankan dengan cermat. Jabatan preventif yang mulia—oficium nobile, lahir dari kepercayaan publik (officium trust) dan mandat negara (officium publicum)—menjadi medan tipis antara melindungi kepastian hukum dan menghadapi bayang-bayang kriminalisasi struktural. Tekanan ini mendorong praktik defensif, memperlambat pelayanan, dan menurunkan kepercayaan publik, sekaligus mengguncang integritas ekosistem hukum formal yang selama ini menopang hak dan kewajiban masyarakat.
Kerangka four point determination menegaskan empat titik kritis: risiko pidana yang meluas, integritas akta yang rentan, kewajiban prosedural yang ketat, dan perlindungan jabatan preventif yang harus dijaga. Tanpa keseimbangan normatif antara lex specialis UUJN dan lex generalis KUHP/KUHAP, fungsi preventif Notaris berpotensi hilang, kepastian hukum tergerus, dan hukum pidana berubah menjadi ancaman, bukan pelindung. Inilah paradoks jabatan preventif: semakin besar kepercayaan publik yang digenggamnya, semakin nyata bayang-bayang risiko yang mengintai setiap goresan pena. Dalam lanskap hukum baru ini, menjaga Notaris berarti menjaga fondasi kepastian hukum—fides publicae est fundamentum juris—dan memastikan hukum tetap menjadi ultimum remedium, bukan instrumen yang menakut-nakuti mereka yang menyalurkan kehendak hukum dengan jujur dan sah.
Delik Pemalsuan, Penipuan, dan Bayang-Bayang Kriminalisasi Sistemik
Risiko pidana yang menimpa notaris semakin kompleks ketika Pasal 222 KUHAP Baru dibaca bersamaan dengan delik pemalsuan dan penipuan dalam KUHP Baru, khususnya Pasal 392, Pasal 394, dan Pasal 486. Pasal 392 menegaskan pidana bagi pemalsuan surat secara umum, Pasal 394 mengkriminalisasi permintaan pemuatan keterangan palsu dalam akta autentik, sementara Pasal 486 memperluas pertanggungjawaban terhadap penggunaan surat palsu dan keterlibatan pihak lain. Secara normatif, subjek delik adalah pihak yang melakukan atau meminta pemalsuan; namun, praktik penegakan hukum terkadang menarik notaris ke dalam pusaran, seolah-olah ia mengetahui, membantu, atau turut serta (deelneming) dalam tindak pidana, meskipun seluruh prosedur UU Jabatan Notaris telah dijalankan dengan cermat.
Di titik ini, perbedaan antara kebenaran formal (formele waarheid) dan kebenaran materiil (materiële waarheid) menjadi ranah rawan yang menguji keberanian jabatan preventif. Notaris hanyalah pencatat pernyataan penghadap, penjaga integritas akta, bukan pengendali isi perbuatan pihak lain. Namun, konstruksi delik KUHP Baru menuntut kebenaran materiil secara retrospektif, menempatkan setiap akta di bawah sorotan yang dapat mereduksi nilai formalnya. Akumulasi norma-norma ini melahirkan bayang-bayang kriminalisasi sistemik: risiko pidana tidak langsung, degradasi nilai akta autentik, benturan antara kewajiban kerahasiaan dan kewenangan penyidikan, serta efek chilling yang mendorong praktik defensif dan overcautious.
Dalam konteks ini, adagium klasik summum ius, summa iniuria menjadi sangat relevan: hukum yang diterapkan agresif tanpa diferensiasi justru menimbulkan ketidakadilan struktural. Perspektif ius integrum nusantara menuntut respons normatif yang seimbang, di mana penegakan hukum berjalan beriringan dengan perlindungan jabatan notaris. Tanpa harmonisasi tegas antara KUHP, KUHAP, dan UUJN, risiko pidana pasca-reformasi berpotensi menggeser notaris dari pilar kepastian hukum menjadi subjek yang bekerja di bawah bayang-bayang kriminalisasi. Hukum pidana harus tetap ditempatkan sebagai ultimum remedium, agar modernisasi hukum tidak meruntuhkan fondasi kepercayaan publik yang menjadi inti negara hukum.
Rekonstruksi Sistem Pembuktian Pidana dalam Kerangka Ius Integrum Nusantara
Sejak diberlakukannya KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP Baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, jabatan Notaris menghadapi persimpangan kritis antara fungsi preventif dan risiko kriminalisasi struktural. Praktik nyata mengilustrasikan dilema ini secara gamblang: seorang Notaris yang melegalkan konosemen ekspor bisa terseret pidana jika barang atau dokumen terkait bermasalah; akta pendirian korporasi, meskipun Notaris hanya bertindak sebagai fasilitator formal, berpotensi menimbulkan risiko pidana; dan akta jual beli tanah berdasarkan sertifikat palsu menempatkan Notaris dalam bayang-bayang penyidikan meski prosedur UUJN telah ditaati secara ketat. Kasus-kasus ini menegaskan adagium hukum klasik: notarius non est partis in instrumento constituto—Notaris bukanlah pihak dalam substansi perbuatan hukum—serta prinsip nemo tenetur ad extra facta sua, yang menekankan bahwa pejabat preventif tidak dapat dibebani tanggung jawab materiil atas isi akta.
Dalam kerangka four-point determination, risiko ini dapat dianalisis melalui empat dimensi krusial:
- Dimensi administratif versus pidana: Kesalahan prosedural, meski tanpa unsur dolus, berpotensi dikonstruksi sebagai delik pidana (Pasal 392, 394, 486 KUHP Baru), sehingga fungsi preventif Notaris dapat terdistorsi menjadi risiko retrospektif.
- Dimensi preventif versus retrospektif: Fungsi preventif yang seharusnya proactive dikonversi menjadi evaluasi retrospektif, menciptakan efek chilling—di mana summum ius (hukum tertinggi) dapat berujung pada summa iniuria (ketidakadilan tertinggi).
- Dimensi korporasi versus individu: Pertanggungjawaban korporasi (Pasal 46–48 KUHP Baru) menarik Notaris ke ranah pidana, meskipun perannya hanya sebagai fasilitator formal (ministerial actor), memperluas jangkauan risiko hukum.
- Integritas akta: Penyitaan protokol, minuta, dan data digital (Pasal 222 KUHAP Baru) menurunkan nilai akta sebagai bukti formal (volledig en bindend bewijskracht) dan berpotensi mengganggu kepastian hukum publik (legal certainty).
Tanpa perlindungan lex specialis yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)—sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf f (kerahasiaan jabatan atau notariële geheimhouding), Pasal 1 angka 7, 16 ayat (1) huruf a dan m, Pasal 39, 38 ayat (1–4), 40, 44, 48, 84, serta Pasal 66-A yang mengatur perlindungan arsip berupa protokol Notaris—jabatan Notaris berisiko menjadi medan kriminalisasi struktural. Konsekuensinya sangat serius: fungsi preventif melemah, pelayanan hukum melambat, kepastian transaksi terganggu, dan kepercayaan publik (fides publicae)—fondasi dari legitimasi sistem hukum—tergerus.
Dalam konteks ini, UUJN berfungsi bukan hanya sebagai norma formalistik, tetapi sebagai instrumen yang menegaskan prinsip ultimum remedium: hukum pidana tidak boleh menjadi ancaman menakutkan (deterrent effect) yang menghambat pejabat preventif, melainkan hanya digunakan ketika unsur kesalahan nyata (culpa gravis atau dolus) dapat dibuktikan, sehingga integritas jabatan Notaris tetap terjaga dan kepastian hukum publik tetap terjamin.
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014, perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004, prosedur verifikasi dan penyusunan akta merupakan inti dari due diligence notarial, yang membedakan akta otentik dari akta di bawah tangan (acta sub sigillo). Prosedur ini tidak hanya bersifat formal, tetapi memiliki dimensi substantif untuk melindungi kepentingan hukum para pihak.
- Prosedur Verifikasi Pra-Penyusunan (Preliminary Verification)
Sebelum akta diresmikan, Notaris diwajibkan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap identitas, kehendak, dan kewenangan para pihak (parties involved):
- Identitas Penghadap: Notaris memverifikasi keaslian dokumen identitas (KTP, Paspor) dan memastikan competentia iuris para penghadap.
- Kehendak Para Pihak (Voluntas Contrahentium): Notaris berkewajiban mendengar secara langsung kehendak para pihak yang akan dituangkan ke dalam akta, menjaga asas consensus facit actum.
- Legalitas Dokumen Pendukung: Dokumen dasar transaksi, seperti sertifikat tanah atau surat kuasa, harus diperiksa keabsahannya.
- Kewenangan Bertindak: Notaris memastikan bahwa penghadap memiliki hak atau kuasa untuk melakukan perbuatan hukum (potestas agendi).
Kewajiban ini berpijak pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mewajibkan Notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta Pasal 39 mengenai syarat kecakapan dan pengenalan penghadap.
- Penyusunan Akta (Structura Acta Notarialia)
Pasal 38 UUJN menetapkan tiga komponen esensial sebuah akta otentik:
- Kepala Akta (Initium Actae)
- Judul dan nomor akta.
- Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan.
- Nama lengkap dan kedudukan Notaris.
- Badan Akta (Corpus Actae)
- Identitas lengkap penghadap dan saksi.
- Keterangan kedudukan bertindak penghadap.
- Isi akta sebagai refleksi kehendak para pihak (voluntas actum).
- Akhir Akta (Clausula Finalis)
- Pernyataan pembacaan akta di hadapan penghadap dan saksi.
- Penandatanganan oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- Dokumentasi perubahan atau renvooi, apabila ada, dengan paraf pengesahan.
Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 48 UUJN menegaskan prosedur pembacaan, penandatanganan, dan perubahan akta agar kekuatan hukum (validitas) akta tetap terjaga.
- Akibat Hukum dan Sanksi Ketidakpatuhan
Kegagalan Notaris mematuhi prosedur yang diatur UUJN dapat menimbulkan konsekuensi serius:
- Akibat terhadap Akta
- Degradasi Kekuatan Pembuktian: Pasal 84 UUJN menyatakan bahwa akta yang tidak memenuhi syarat otentisitas hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan.
- Batal Demi Hukum (Nullitas Absolute): Jika akta terbukti mengandung keterangan palsu atau fraus legis, pengadilan dapat membatalkannya.
- Sanksi bagi Notaris
- Administratif: Teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap (Pasal 85 UUJN).
- Perdata: Ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jika terjadi tortious liability.
- Pidana: Ancaman penjara sesuai Pasal 264 atau 266 KUHP atas pemalsuan atau perbuatan curang dalam akta.
- Kode Etik Profesi: Skorsing atau pemecatan dari Ikatan Notaris Indonesia (professional sanction).
- Refleksi Akademik dan Perkembangan Terkini
Hingga awal 2026, putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024, menegaskan bahwa jabatan Notaris harus tetap profesional, bahkan dengan perpanjangan usia pensiun hingga 70 tahun. Hal ini menegaskan prinsip ultimum remedium: hukum pidana tidak boleh menjadi ancaman deterrent yang menghambat fungsi preventif Notaris, melainkan hanya digunakan sebagai penegak keadilan bila prinsip kehati-hatian (diligentia notarialis) dilanggar secara nyata.
Dengan kata lain, UUJN bukan semata aturan formalistik, tetapi instrumen menjaga public trust dan kepastian hukum (legal certainty), menegaskan adagium klasik: nemo censetur ignorare legem—tidak seorang pun dianggap tidak mengetahui hukum, terutama bagi pejabat yang diberi mandat preventif untuk melindungi kepentingan publik.
Secara komparatif, pengalaman sistem Prancis (notaire) dan Jerman (Notarrecht) menunjukkan keseimbangan yang patut dicontoh: penyitaan dokumen hanya berlaku dalam kondisi terbatas, melalui pengawasan dewan notaris atau pengadilan, dan tanggung jawab pidana diterapkan hanya bila terbukti dolus atau kelalaian berat (grobe Fahrlässigkeit). Pendekatan ini selaras dengan prinsip kebenaran formal (formele waarheid), membedakan antara catatan resmi Notaris dengan kebenaran materiil (materiële waarheid) yang sering dituntut penegak hukum secara retrospektif.
Di titik klimaks ini, jabatan Notaris berdiri sebagai mercusuar kepercayaan publik, oficium nobile lahir dari mandat negara (officium publicum) dan kepercayaan masyarakat (officium trust), sekaligus pelindung kepastian hukum perdata. Notaris adalah penjaga arsip dan fasilitator perbuatan hukum yang sah, bukan korban tafsir hukum agresif. Quo vadis jabatan Notaris bergantung pada kemampuan legislator dan aparat penegak hukum menegakkan keadilan substantif, menjaga integritas jabatan, dan memastikan bahwa modernisasi hukum tidak mengorbankan fondasi kepastian hukum yang menjadi inti negara hukum: Fides publicae est fundamentum juris.
Dengan demikian, perlindungan normatif melalui UUJN, literasi aparat penegak hukum, dan penerapan prinsip in dubio pro reo harus dijadikan pilar, agar jabatan preventif Notaris tetap berfungsi optimal dalam ekosistem hukum yang futuristik, deterministik, dan responsif, menjaga kepercayaan publik, integritas akta, dan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.
Pergeseran Status Akta Autentik dan Protokol Notaris dalam Rezim Pidana
Dalam hukum perdata, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig en bindend bewijskracht), menegaskan statusnya sebagai bukti formal yang sah dan mengikat. Namun, Pasal 222 KUHAP Baru menempatkan akta sebagai alat bukti surat dalam proses pidana, tanpa diferensiasi tegas antara akta autentik, akta di bawah tangan, dan dokumen biasa. Reduksi ini menimbulkan degradasi fungsional ketika akta—yang seharusnya menjadi simbol kepastian hukum (certitudo legis)—masuk ke ranah pidana.
Implikasi praktisnya menjadi nyata ketika minuta atau salinan akta disita tanpa persetujuan atau keterlibatan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), sebagaimana dijamin Pasal 66-A UUJN. Hakim pidana berpotensi menilai akta autentik hanya sebagai bukti surat biasa, sehingga integritas akta terdegradasi. Minuta akta, sebagai bagian dari protokol notaris, bukan sekadar dokumen internal, tetapi arsip negara (archiva publica) dan instrumen pelayanan publik yang menjaga kontinuitas layanan (continuity of public service). Penyitaan fisik maupun akses digital yang tidak proporsional dapat melumpuhkan fungsi kantor notaris, merugikan pihak yang tidak terkait perkara, dan menimbulkan ketegangan struktural antara hukum acara pidana dan hukum administrasi kenegaraan.
Dalam konteks ini, adagium summum ius, summa iniuria menjadi relevan: penerapan hukum yang agresif tanpa memperhatikan karakter jabatan preventif Notaris justru menimbulkan ketidakadilan struktural. Perlindungan normatif lex specialis UUJN menjadi krusial untuk menegaskan bahwa Notaris, meskipun akta yang dibuatnya dapat menjadi alat bukti pidana, tetap beroperasi dalam kerangka kepercayaan publik (fides publicae), integritas formal, dan tanggung jawab administratif, bukan sebagai korban tafsir hukum agresif.
Dalam kerangka four point determination, risiko multilapis ini dapat diuraikan sebagai berikut:
- Dimensi administratif versus pidana: Kesalahan prosedural kecil atau kelalaian dalam verifikasi dokumen dapat dikonstruksi sebagai delik pidana, meski tidak ada dolus, bertentangan dengan prinsip nemo tenetur ad extra facta sua.
- Dimensi preventif versus retrospektif: Jabatan preventif Notaris, yang seharusnya menjamin kepastian hukum formal (formele waarheid), berubah menjadi ranah retrospektif di mana akta dan keterangan penghadap dinilai secara materiil (materiële waarheid).
- Dimensi korporasi versus individu: Pertanggungjawaban korporasi (Pasal 46–48 KUHP Baru) dapat menarik Notaris ke ranah pidana meskipun ia hanya berperan sebagai fasilitator formal (facilitator officii).
- Integritas akta: Penyitaan protokol, minuta, dan arsip digital, terutama tanpa persetujuan MKN (Pasal 66-A UUJN), menimbulkan degradasi akta autentik dari volledig en bindend bewijskracht menjadi alat bukti surat biasa (simpel schriftelijk bewijs), sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1868 jo. 1870 dan diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung, misal Putusan MA No. 1234 K/Pdt/2018, yang menegaskan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna jika prosedur formil dijalankan.
Pasal 222 KUHAP Baru menambah ketegangan normatif: protokol dan data digital Notaris dapat disita sebagai alat bukti, berpotensi melanggar kewajiban kerahasiaan jabatan (notariële geheimhouding) dan prinsip confidentiality, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Penerapan hukum yang agresif tanpa diferensiasi justru menegaskan adagium summum ius, summa iniuria.
Secara komparatif, sistem Prancis (notaire) dan Jerman (Notarrecht) menunjukkan keseimbangan: penyitaan dokumen hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas dan dengan izin dewan notaris atau pengadilan, serta pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bila terbukti dolus atau kelalaian berat (grobe Fahrlässigkeit). Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum pidana harus menjadi ultimum remedium, bukan alat menakut-nakuti pejabat preventif.
Dengan integrasi norma UUJN, KUHP/KUHAP Baru, dan prinsip hukum perdata, jabatan Notaris harus dipandang sebagai guardian of legal certainty, pelindung arsip negara, dan fasilitator hak serta kewajiban hukum yang sah. Jabatan preventif ini bukan pihak yang menciptakan isi akta (notarius non est partis in instrumento constituto), sehingga secara prinsip tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di luar perbuatannya sendiri (nemo tenetur ad extra facta sua). Tanpa perlindungan normatif yang tegas—lex specialis UUJN, mekanisme MKN, batasan pertanggungjawaban korporasi, dan edukasi aparat penegak hukum—Notaris menghadapi bayang-bayang kriminalisasi struktural yang dapat mereduksi kepercayaan publik (fides publicae), merusak kepastian transaksi, dan melemahkan integritas hukum formal.
Dengan demikian kajian ini melihat jabatan Notaris muncul sebagai mercusuar keadilan: setiap tinta yang dituangkan dalam akta bukan sekadar catatan formal, tetapi saksi bisu dari kepercayaan publik dan mandat negara (officium trust et officium publicum). Keberanian Notaris untuk menegakkan kepastian hukum, meski di bawah tekanan risiko pidana, adalah inti dari integritas sistem hukum. Quo vadis jabatan preventif ini bergantung pada kemampuan pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum untuk menyeimbangkan penegakan hukum dan perlindungan profesi, menegaskan bahwa hukum pidana tetap menjadi ultimum remedium, sementara Notaris tetap menjadi pilar kepastian hukum di tengah arus kompleksitas zaman.
Bukti Elektronik, Hak Ingkar, dan Risiko Struktural bagi Profesi Notaris
Pengakuan bukti elektronik (digital evidence) sebagai alat bukti sah merupakan keniscayaan dalam hukum pidana modern. Namun, dalam konteks profesi notaris, pengakuan ini membawa implikasi serius. Data digital notaris—mulai dari soft copy minuta, basis data klien, korespondensi elektronik, hingga arsip cloud—dapat dengan mudah dijadikan objek pembuktian pidana. Tanpa pembatasan akses yang tegas dan mekanisme protektif yang memadai, penyidik berpotensi mengakses informasi klien lain yang sama sekali tidak terkait perkara, bertentangan dengan Pasal 16 UU Jabatan Notaris (UUJN), prinsip confidentiality, dan asas data minimization.
Kondisi ini secara faktual menggerus hak ingkar notaris (ius recusandi). Perlindungan professional privilege dapat dilewati (circumvention of professional privilege) melalui penyitaan atau penelusuran data elektronik, meskipun notaris tidak pernah dimintai keterangan secara langsung. Akibatnya, notaris berada dalam posisi struktural yang timpang: protokol dan akta rentan ditarik ke ranah pidana, sementara perlindungan normatif UUJN bekerja secara defensif dan reaktif. Tidak jarang, kesalahan prosedural kecil atau kelalaian dalam verifikasi dibebankan kepada notaris, bukan pada aparat penegak hukum, bertentangan dengan asas nemo tenetur ad extra facta sua.
Dalam konteks inilah Pasal 222 KUHAP Baru harus dibaca secara kritis. Meskipun tampak netral secara tekstual, norma ini memiliki latent destructive effect apabila diterapkan tanpa harmonisasi dengan UUJN, pembatasan penyitaan, dan penguatan peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana diatur dalam Pasal 66-A UUJN. Persoalannya bukan terletak pada pengakuan alat bukti modern, melainkan pada ketiadaan perlakuan diferensial terhadap profesi dengan fungsi preventif dan berbasis kepercayaan publik (officium nobile).
Risiko struktural tersebut semakin nyata sejak berlakunya KUHP dan KUHAP Baru—UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 20 Tahun 2025. Praktik menunjukkan bahwa notaris yang telah menjalankan seluruh prosedur UUJN tetap dapat terseret ke dalam proses pidana, baik dalam kasus akta jual beli tanah berbasis sertifikat palsu, legalisasi konosemen ekspor atas barang bermasalah, maupun pengesahan akta pendirian korporasi yang kemudian melakukan tindak pidana. Dalam situasi demikian, akta dan protokol notaris ditempatkan dalam konstruksi delik Pasal 392, 394, 486, dan 501 KUHP Baru, dibaca bersama Pasal 222 KUHAP Baru, meskipun notaris hanya bertindak sebagai fasilitator formal.
Melalui kerangka four point determination, tekanan multilapis terhadap jabatan notaris dapat dipetakan secara sistematis, yaitu:
Pertama, pada dimensi administratif versus pidana, kesalahan prosedural tanpa dolus berpotensi dikonstruksi sebagai delik pidana.
Kedua, pada dimensi preventif versus retrospektif, fungsi notaris sebagai penjaga kepastian hukum formal (formele waarheid) dikonversi menjadi penilaian retrospektif berbasis kebenaran materiil (materiële waarheid).
Ketiga, pada dimensi korporasi versus individu, rezim pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 46–48 KUHP Baru berpotensi menarik notaris ke ranah pidana meskipun perannya terbatas pada facilitator officii.
Keempat, pada dimensi integritas akta, penyitaan protokol, minuta, dan arsip digital—terutama tanpa persetujuan MKN—menurunkan akta autentik dari kekuatan pembuktian sempurna (volledig en bindend bewijskracht) menjadi sekadar alat bukti surat biasa (simpel schriftelijk bewijs), sebagaimana bertentangan dengan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Putusan MA No. 1234 K/Pdt/2018.
Akumulasi risiko tersebut menimbulkan dampak lanjutan yang bersifat psikologis dan institusional: praktik defensif, penundaan pelayanan, pembatasan akses hukum masyarakat, serta degradasi kepercayaan publik (fides publicae). Di titik ini, adagium summum ius, summa iniuria menemukan relevansinya—penerapan hukum yang terlalu keras dan seragam, tanpa memperhatikan karakter jabatan preventif, justru melahirkan ketidakadilan struktural.
Secara normatif, lex specialis UUJN—terutama Pasal 4 ayat (2), Pasal 15–16, dan Pasal 66-A—menegaskan bahwa Notaris bukanlah pihak dalam penciptaan isi akta (notarius non est partis in instrumento constituto) dan dengan demikian tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di luar perbuatannya sendiri (nemo tenetur ad extra facta sua). Prinsip ini menuntut konsolidasi kelembagaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), pembatasan interpretasi pertanggungjawaban korporasi, serta peningkatan literasi aparat penegak hukum, agar hukum pidana tetap berfungsi sebagai ultimum remedium dan tidak menjadi instrumen chilling effect bagi pejabat preventif.
Pendekatan komparatif, misalnya di Prancis (notaire) dan Jerman (Notarrecht), menunjukkan bahwa keseimbangan antara perlindungan jabatan dan penegakan hukum bukanlah utopia. Penyitaan dokumen dibatasi secara ketat, melibatkan dewan notaris atau izin pengadilan, dan pertanggungjawaban pidana hanya dimungkinkan apabila terbukti dolus atau grobe Fahrlässigkeit. Model ini sekaligus menjaga integritas arsip, kerahasiaan jabatan (notariële geheimhouding), dan efektivitas penegakan hukum secara simultan, sehingga fungsi preventif tetap terjaga tanpa mengorbankan kepastian hukum.
Dalam konteks tersebut, jabatan Notaris tampil sebagai mercusuar kepastian hukum: setiap akta bukan sekadar dokumen formal, melainkan manifestasi kepercayaan publik (fides publicae) dan mandat negara (officium trust et officium publicum). Melindungi Notaris dari kriminalisasi struktural bukanlah bentuk impunitas, melainkan prasyarat bagi negara hukum yang sehat. Quo vadis jabatan preventif ini akan ditentukan oleh kemampuan pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum untuk menempatkan keadilan substantif di atas ketakutan struktural—menegaskan kembali adagium klasik: hukum pidana adalah ultimum remedium, sementara Notaris tetap menjadi pilar kepastian hukum di tengah kompleksitas zaman yang semakin digital dan interkonektif.
Pasal 394 KUHP Baru dan Notaris sebagai Officium Nobile: Menjaga Batas antara Perlindungan Akta dan Kriminalisasi Jabatan Preventif
Pasal 394 KUHP Baru pada hakikatnya dirancang untuk melindungi integritas akta autentik sebagai manifestasi kepercayaan publik (fides publicae), bukan untuk menggeser beban pertanggungjawaban pidana kepada pejabat umum pembuat akta. Norma ini secara eksplisit menyasar setiap orang yang meminta dimasukkannya keterangan palsu ke dalam akta autentik, dengan penekanan pada unsur kesengajaan (dolus) dan tujuan penggunaan seolah-olah benar. Dengan demikian, subjek delik Pasal 394 secara dogmatis adalah pihak penghadap atau pihak yang menginisiasi manipulasi kebenaran, bukan Notaris yang menjalankan fungsi pencatatan kehendak hukum secara formal dan prosedural.
Dalam konstruksi hukum kenotariatan, Notaris bukanlah pencipta isi materiil akta, melainkan pejabat umum yang mewilayahkan kehendak para pihak ke dalam bentuk autentik (verlijden van akten). Posisi ini ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 15 ayat (1), yang menempatkan Notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan atribusi negara untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, asas klasik notarius non est partis in instrumento constituto menjadi relevan: notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya. Konsekuensinya, pertanggungjawaban pidana tidak dapat diperluas melampaui batas perbuatannya sendiri, sejalan dengan adagium nemo tenetur ad extra facta sua dan prinsip nulla poena sine culpa.
Sebagai officium nobile, jabatan Notaris tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi mengandung dimensi etis dan institusional sebagai penjaga kepastian hukum formal (guardian of legal certainty). Kewajiban Notaris adalah memastikan kebenaran formal (formele waarheid), bukan menyelidiki atau membuktikan kebenaran materiil (materiële waarheid) dari setiap pernyataan penghadap. Distingsi ini merupakan fondasi sistem pembuktian perdata dan ditegaskan dalam Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, yang memberikan akta autentik kekuatan pembuktian sempurna (volledig en bindend bewijskracht) sepanjang syarat formil terpenuhi. Menarik Notaris ke dalam delik Pasal 394 hanya karena kemudian hari terbukti adanya keterangan palsu dari penghadap berarti mencampuradukkan dua rezim kebenaran yang secara konseptual berbeda.
Lebih jauh, UUJN secara sadar membangun rezim perlindungan jabatan preventif melalui kewajiban kerahasiaan (notariële geheimhouding) dan hak ingkar, sebagaimana tercermin dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, serta mekanisme Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 66-A UUJN. Perlindungan ini bukanlah privilese personal, melainkan instrumen institusional untuk menjaga kepercayaan publik terhadap akta autentik sebagai arsip negara (archiva publica). Dalam konteks ini, penerapan Pasal 394 KUHP Baru harus dibaca in harmony dengan UUJN sebagai lex specialis, sesuai asas lex specialis derogat legi generali.
Apabila Pasal 394 ditafsirkan secara agresif hingga menyeret Notaris yang telah menjalankan prosedur UUJN secara patuh, maka hukum pidana berisiko melampaui rasionalitasnya sendiri. Di titik inilah adagium summum ius, summa iniuria menemukan relevansinya: hukum yang ditegakkan secara ekstrem justru melahirkan ketidakadilan struktural. Kriminalisasi jabatan preventif tidak hanya merugikan Notaris sebagai individu, tetapi juga merusak ekosistem kepastian hukum, memperlemah fungsi akta autentik, dan pada akhirnya menggerus kepercayaan publik terhadap negara hukum.
Dengan demikian, Pasal 394 KUHP Baru harus dipahami sebagai norma pelindung akta, bukan norma penjerat pejabat pembuat akta. Notaris sebagai officium nobile—lahir dari kepercayaan masyarakat (officium trust) dan mandat negara (officium publicum)—harus tetap ditempatkan sebagai penjaga kebenaran formal, bukan subjek kecurigaan pidana retrospektif. Hukum pidana hanya layak bekerja ketika terdapat bukti keterlibatan aktif, kesengajaan, atau kolusi (dolus malus), bukan semata karena akta autentik digunakan oleh pihak lain untuk tujuan melawan hukum. Di sinilah hukum pidana menemukan kembali posisinya yang proporsional sebagai ultimum remedium, dan jabatan Notaris tetap berdiri sebagai pilar kepastian hukum dalam bangunan negara hukum Indonesia.
Unsur Delik, Mens Rea, dan Batas Kebenaran dalam Akta Autentik
Secara dogmatis, Pasal 394 KUHP Baru memusatkan perhatian pada perbuatan aktif meminta atau menyuruh dimasukkannya keterangan palsu ke dalam akta autentik. Objek delik bukanlah akta sebagai instrumen hukum, melainkan keterangan yang dimuat di dalamnya mengenai hal yang menurut hukum harus dinyatakan benar. Dengan demikian, norma ini diarahkan untuk melindungi kebenaran formal yang dilekatkan negara pada akta autentik sebagai produk pejabat umum (public faith doctrine), bukan untuk menilai ulang substansi materiil di luar jangkauan kewenangan pejabat pembuat akta.
Unsur subjektif (mens rea) Pasal 394 dirumuskan secara tegas melalui frasa “dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakannya seolah-olah benar”. Di sinilah garis pemisah antara kesalahan administratif (culpa levis) dan perbuatan pidana yang layak dipidana (dolus malus) ditarik. Norma ini menuntut adanya kehendak sadar dan tujuan manipulatif, sejalan dengan asas fundamental nulla poena sine culpa. Sementara itu, unsur akibat dirumuskan melalui frasa “dapat menimbulkan kerugian”, yang menunjukkan bahwa kerugian aktual bukan syarat mutlak; cukup adanya potensi kerugian yang rasional dan dapat diperkirakan (voorzienbaarheid van schade).
Dalam konteks ini, distingsi antara kebenaran formal (formele waarheid) dan kebenaran materiil (materiële waarheid) menjadi krusial. Akta autentik—sebagaimana ditegaskan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata—menjamin kebenaran formal atas apa yang dinyatakan para pihak di hadapan pejabat umum, bukan kebenaran materiil atas fakta di luar pengetahuan dan kewenangan pejabat tersebut. Tanpa sensitivitas terhadap batas epistemik ini, penerapan Pasal 394 berisiko meluas secara tidak proporsional, mencampuradukkan fungsi pencatatan kehendak dengan kewajiban pembuktian fakta, dan pada akhirnya mengaburkan asas qui dicit non probat dalam rezim kenotariatan.
Implikasi Sistemik terhadap Jabatan Notaris dan Risiko Kriminalisasi Tidak Langsung
Secara tekstual, Pasal 394 tidak menempatkan Notaris sebagai subjek delik. Namun, dalam praktik penegakan hukum, posisi Notaris sebagai pejabat preventif (preventive public officer) menempatkannya pada risiko struktural yang nyata. Notaris menjalankan kewenangan atribusi negara untuk mencatat dan memformalkan kehendak para penghadap, bukan untuk menyelidiki kebenaran materiil setiap pernyataan, sebagaimana ditegaskan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) UUJN.
Risiko muncul ketika keterangan penghadap kemudian terbukti palsu dan menimbulkan kerugian. Dalam konstruksi pidana tertentu, Notaris berpotensi ditarik ke dalam logika deelneming (penyertaan) dengan asumsi mengetahui, membiarkan, atau membantu pemuatan keterangan palsu. Bahaya laten terletak pada penilaian unsur dolus secara retrospektif, tanpa membedakan antara niat jahat dan pelaksanaan kewajiban jabatan secara patuh prosedur (in bona fide officii). Praktik semacam ini bertentangan dengan asas nemo tenetur ad extra facta sua dan in dubio pro reo.
Kompleksitas tersebut diperparah oleh interaksi Pasal 394 dengan rezim pembuktian KUHAP Baru, khususnya Pasal 222, yang memperluas pengakuan alat bukti, termasuk dokumen dan bukti elektronik. Akta dan protokol Notaris yang terkait dugaan keterangan palsu dapat disita, bahkan berpotensi dinilai ulang sebagai alat bukti surat biasa. Konsekuensinya, kekuatan pembuktian akta autentik—yang secara doktrinal bersifat volledig en bindend bewijskracht—dapat terdegradasi, tidak hanya merugikan Notaris secara personal, tetapi juga mengganggu kepastian hukum pihak ketiga yang bergantung pada akta tersebut.
Dalam perspektif ius integrum nusantara, kondisi ini mencerminkan ketegangan laten antara hukum pidana sebagai instrumen represif (ius puniendi) dan jabatan Notaris sebagai penjaga stabilitas hukum perdata dan kepercayaan publik (fides publicae). Tanpa diferensiasi normatif yang tegas, Pasal 394 berpotensi menimbulkan chilling effect: Notaris bekerja di bawah bayang-bayang kriminalisasi, bersikap overcautious, memperlambat pelayanan, dan secara tidak langsung membatasi akses masyarakat terhadap kepastian hukum.
Keseimbangan antara Perlindungan Hukum Pidana dan Jabatan Preventif Notaris
Keberlakuan Pasal 394 menuntut pembacaan sistemik, kontekstual, dan berkeadilan. Perlindungan terhadap integritas akta autentik tidak boleh dicapai dengan mengorbankan perlindungan struktural jabatan Notaris sebagai officium nobile. Harmonisasi antara KUHP Baru dan UUJN—khususnya Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 66-A UUJN—menjadi kunci untuk mencegah ketidakpastian hukum yang bersifat sistemik, sejalan dengan asas lex specialis derogat legi generali.
Dalam kerangka hukum pidana modern yang responsif dan berorientasi masa depan, Pasal 394 harus ditempatkan sebagai instrumen perlindungan kepercayaan publik terhadap akta, bukan sebagai pintu masuk kriminalisasi jabatan preventif. Hukum pidana harus tetap berfungsi sebagai ultimum remedium, bukan primum refugium. Dengan demikian, fungsi Notaris sebagai penjaga kebenaran formal, pelindung arsip negara, dan penyangga kepastian hukum perdata dapat terus dijalankan tanpa rasa takut yang melumpuhkan. Di situlah keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan struktural menemukan maknanya dalam negara hukum yang beradab.
Rasionalisasi Pasal 501 KUHP Baru dan Perlindungan Integritas Konosemen
Pasal 501 KUHP Baru menegaskan bahwa penyalahgunaan bill of lading atau konosemen—dokumen yang berfungsi ganda sebagai bukti penguasaan barang dan instrumen transaksi niaga—merupakan tindak pidana dengan ancaman penjara maksimal tiga tahun atau denda kategori IV. Norma ini tidak sekadar melindungi kepentingan individu penerima barang, tetapi juga menjaga integritas sistem perdagangan dan kepercayaan publik (trust node) yang menjadi simpul mekanisme distribusi dan pembiayaan barang lintas wilayah. Dalam perspektif ius integrum nusantara, Pasal 501 mencerminkan keseimbangan antara determinisme akibat hukum—misalnya kerugian akibat hak tumpang tindih—dan responsivitas hukum pidana terhadap kompleksitas praktik komersial modern.
Dibandingkan dengan KUHP lama (Pasal 383 bis), pergeseran signifikan terlihat pada peningkatan ancaman pidana serta pengenaan denda, menegaskan karakter kejahatan ekonomi yang berdampak sistemik. Konosemen bukan lagi sekadar dokumen administratif; ia menjadi objek hukum yang memerlukan perlindungan formal dan prediktabilitas hukum, sekaligus menimbulkan risiko kumulatif bagi pejabat yang terlibat dalam pembuatan atau legalisasi dokumen yang bersangkutan, termasuk notaris.
Implikasi Sistemik bagi Jabatan Notaris dan Risiko Kriminalisasi Tidak Langsung
Walaupun Pasal 501 tidak menyebut notaris secara eksplisit, praktik kenotariatan tidak dapat dilepaskan dari norma ini. Notaris kerap diminta mengesahkan akta perjanjian jual beli, kuasa ekspor-impor, atau legalisasi dokumen yang merujuk pada konosemen. Dalam kapasitasnya sebagai penjaga formele waarheid, notaris bekerja pada ranah kebenaran formal, bukan substansial, sehingga tanggung jawab pidana tidak semestinya dibebankan atas kesalahan pihak lain.
Namun, risiko muncul ketika konosemen atau dokumen niaga yang menjadi dasar akta disalahgunakan. Dalam praktik penegakan hukum, notaris bisa ditarik ke konstruksi deelneming atau medeplichtigheid bila dianggap mengetahui atau memfasilitasi hak ganda. Kombinasi Pasal 501 dengan Pasal 392 (pemalsuan surat), Pasal 394 (keterangan palsu dalam akta autentik), dan Pasal 486 (penyesatan dokumen) berpotensi menciptakan risiko pidana berlapis, di mana satu transaksi niaga dapat menyeret notaris ke tuduhan pemalsuan, keterangan palsu, dan penyalahgunaan dokumen secara kumulatif.
Akumulasi risiko ini menimbulkan chilling effect: notaris terdorong bersikap hiper-defensif, menunda, atau menolak pembuatan akta terkait dokumen niaga berisiko tinggi, sehingga efisiensi transaksi terganggu dan kepastian hukum (legal certainty) mengalami erosi. Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan antara fungsi preventif notaris dan pendekatan represif hukum pidana, yang seharusnya tetap bersifat ultimum remedium.
Penguatan Asas dan Doktrin dalam Penafsiran Pasal 501 terhadap Jabatan Notaris
- Asas Geen Straf Zonder Schuld dan Pembatasan Pertanggungjawaban Pidana Notaris: Pemidanaan mensyaratkan kesalahan subjektif (dolus) atau pengetahuan aktual (actual knowledge) atas perbuatan pidana. Notaris yang bertindak dalam ranah formal tidak dapat dibebani dugaan kesalahan materiil pihak lain, sehingga pembuktian kesalahan subjektif menjadi prasyarat mutlak untuk pemidanaan.
- Doktrin Functioneel Daderschap dan Kewenangan Jabatan: Pertanggungjawaban pidana atas jabatan fungsional hanya berlaku jika terdapat kendali nyata (beschikkingsmacht) dan penerimaan sadar (aanvaarding) terhadap perbuatan pidana. Notaris tidak memiliki penguasaan atas penggunaan konosemen setelah akta dibuat; kewenangannya terbatas pada perumusan akta berdasarkan pernyataan para pihak (Pasal 15 UUJN). Oleh karena itu, penerapan doktrin ini terhadap notaris kehilangan dasar yuridis.
- Distingsi antara Beroepsfout dan Strafbaar Feit: Kesalahan profesi (beroepsfout), selama tidak disertai niat jahat atau kesadaran akan akibat pidana, berada dalam ranah etik dan administratif. UUJN telah menyediakan mekanisme sanksi profesi, sehingga kriminalisasi atas kesalahan administratif akan menciptakan preseden berbahaya bagi independensi notaris.
- Konsekuensi Yudisial dan Rekomendasi Penafsiran Sistemik: Penafsiran Pasal 501 harus restriktif dan sistemik, menekankan bukti keterlibatan aktif, kerja sama sadar, dan penguasaan fungsional. Hakim dan penegak hukum sebaiknya menolak konstruksi penyertaan atau pembantuan jika unsur ini tidak terpenuhi, menjaga keseimbangan antara perlindungan sistem perdagangan dan integritas profesi hukum.
Rekonfigurasi Posisi Notaris dalam Arsitektur Hukum Pidana Modern
Berlakunya KUHP Baru dan KUHAP Baru sejak 2 Januari 2026 menandai pergeseran paradigma hukum pidana dari retributive justice menuju model sistemik dan deterministik. Notaris, sebagai officium nobile, kini berada dalam orbit risiko pidana yang meluas akibat intensifikasi norma delik dan kewenangan penyidikan. Perluasan penyitaan (Pasal 222 KUHAP Baru) terhadap protokol, minuta, dan arsip digital meningkatkan efektivitas pembuktian, tetapi menimbulkan friksi dengan prinsip kerahasiaan (confidentiality) dan integritas akta autentik (perfect bewijs).
Ketika risiko sistemik dipersamakan dengan kesalahan personal, hukum pidana kehilangan watak korektif dan berpotensi menjadi instrumen over-criminalization. Notaris berisiko terseret dalam pusaran tuduhan berlapis, dari penyalahgunaan konosemen, pemalsuan, penyesatan dokumen, hingga keterangan palsu, yang pada akhirnya menimbulkan chilling effect terhadap praktik kenotariatan dan mengganggu legal certainty. Dengan demikian, posisi notaris sebagai pilar kepastian hukum harus dilindungi melalui penafsiran yudisial yang proporsional, penguatan asas hukum pidana, dan diferensiasi yang jelas antara fungsi preventif pejabat publik dan kesalahan pihak ketiga.
Penutup
Harmonisasi, Perlindungan, dan Kepastian Hukum Notaris
Transisi menuju ius constituendum adalah keniscayaan. Harmonisasi KUHP Baru, KUHAP Baru, dan UU Jabatan Notaris menegaskan prinsip lex specialis derogat legi generali: pertanggungjawaban pidana notaris hanya dapat dibenarkan jika terbukti opzet, bewuste samenwerking, atau keterlibatan aktif yang melampaui kewenangan jabatan sebagaimana diatur Pasal 15 dan 16 UUJN. Kesalahan prosedural (beroepsfout) yang bersifat administratif tidak otomatis menjadi strafbaar feit. Dalam kerangka kebijakan, penguatan peran Majelis Kehormatan Notaris sebagai filter awal, pembatasan penyitaan protokol dan arsip digital secara proporsional, serta standarisasi verifikasi dokumen niaga adalah langkah korektif yang menjaga keseimbangan fungsi preventif dan efektivitas hukum pidana, memastikan hukum tetap sebagai ultimum remedium, bukan primum remedium, bagi pejabat preventif.
Di persimpangan reformasi ini, jabatan notaris menghadapi pertanyaan eksistensial: quo vadis? Reformasi pidana yang mengabaikan karakter jabatan berisiko menjadikan notaris korban kriminalisasi struktural. Melindungi notaris bukan bentuk impunitas, melainkan upaya menjaga keseimbangan arsitektur negara hukum. Tanpa perlindungan ini, adagium summum ius, summa iniuria menemukan relevansinya: hukum yang paling keras justru melahirkan ketidakadilan paling mendalam.
Notaris berdiri sebagai penjaga jembatan antara kepastian hukum (legal certainty) dan risiko pidana, antara formalitas prosedural (formele waarheid) dan konsekuensi nyata bagi masyarakat. Fungsi preventif yang sejak awal dibangun untuk mencegah sengketa kini diuji oleh kompleksitas hukum modern, di mana setiap akta dan dokumen bisa menjadi titik tumpu tanggung jawab substantif. Integritas, kehati-hatian profesional, dan kesetiaan pada prinsip notarius non iudicat menjadi fondasi kepercayaan publik—pilar yang memastikan hukum hadir sebagai pelindung, bukan ancaman.
Dalam perspektif ini, kepastian hukum harus tetap menjadi mercusuar, bukan bayangan menakutkan bagi warga negara. Pertanyaan quo vadis jabatan notaris bukan lagi retorika akademik, tetapi panggilan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menegakkan keseimbangan: antara perlindungan profesi preventif dan efektivitas hukum pidana. Keberlangsungan jabatan notaris mencerminkan kematangan hukum nasional—ubi societas, ibi ius—di mana ada masyarakat, di situ hukum harus hadir sebagai pelindung, bukan ancaman.
Referensi
ICJR. (2025). Digital evidence in Indonesian criminal law. Jakarta: ICJR Press.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P).
*) Penulis 1: Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia
**) Penulis 2: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
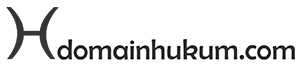



















Komentar