Analisis Yuridis-Konstitusional atas Kebijakan Moratorium Pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan Tahun 2019 Hingga Saat Ini (SE MENRISTEKDIKTI NOMOR 3/M/SE/VIII/2019) : Tinjauan Terhadap Prinsip Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945
Dr KRA MJ Widijatmoko Wreksonegoro SH SpN
Notaris PPAT Jakarta Timur
Eksistensi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Transformasi Pendidikan Kenotariatan di Indonesia.
Eksistensi notaris dalam tatanan hukum Indonesia merupakan manifestasi dari kebutuhan akan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh negara untuk membuat akta autentik, notaris menjalankan sebagian dari fungsi publik negara, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui dokumen legal yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Peran krusial ini menuntut kualifikasi intelektual dan moral yang sangat tinggi, yang secara historis telah berevolusi dari sistem pendidikan spesialis menjadi pendidikan akademik strata dua dalam bentuk Program Magister Kenotariatan.
Pendidikan Magister Kenotariatan di Indonesia diatur secara ketat karena lulusannya dipersiapkan untuk memegang jabatan yang strategis dalam sistem ekonomi dan hukum nasional, termasuk dalam mendukung program strategis seperti Reforma Agraria dan pendaftaran tanah sistematis. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), menetapkan bahwa syarat untuk menjadi notaris adalah lulusan strata dua kenotariatan. Hal ini menempatkan Program Studi Magister Kenotariatan sebagai pintu gerbang tunggal bagi warga negara yang ingin mengabdikan diri dalam profesi ini.
Namun, dinamika penyelenggaraan pendidikan tinggi kenotariatan mengalami perubahan fundamental sejak diterbitkannya kebijakan moratorium oleh Pemerintah. Melalui Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3/M/SE/VIII/2019, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara proses usulan pembukaan program studi baru tersebut. Kebijakan ini memicu diskursus hukum yang mendalam mengenai sejauh mana diskresi pemerintah dapat membatasi hak konstitusional warga negara dan institusi pendidikan dalam menyelenggarakan serta mengakses pendidikan tinggi, terutama ketika instrumen pembatasnya hanyalah sebuah surat edaran yang secara hierarki berada di luar kategori peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum.
Konstruksi Kebijakan Moratorium dan Dinamika Layanan Kelembagaan
Kebijakan moratorium pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan didasarkan pada argumen pemerintah mengenai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mutu pendidikan dan pemerataan kualitas lulusan. Pemerintah memandang bahwa ledakan jumlah program studi baru yang tidak terkendali dapat menurunkan standar kualitas profesi dan menciptakan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah lulusan.
| Komponen Kebijakan | Detail Operasional Berdasarkan
SE No. 3/M/SE/VIII/2019 |
| Dasar Hukum Utama | Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
| Objek Kebijakan | Penghentian usulan baru Program Studi Magister Kenotariatan |
| Wilayah Pengecualian | Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) serta kondisi khusus |
| Mekanisme Pelaksanaan | Penghentian proses pada Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA) |
| Tujuan Strategis | Peningkatan standar akreditasi dan relevansi dunia kerja |
Kebijakan ini tidak hanya berhenti pada tahun 2019, tetapi terus berlanjut hingga periode 2024-2025. Melalui pengumuman teknis pada sistem SIAGA dan berbagai surat dinas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, ditekankan bahwa pembukaan program studi baru diprioritaskan untuk bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), sementara bidang sosial humaniora, termasuk kenotariatan, tetap berada dalam daftar moratorium. Pola ini menunjukkan adanya preferensi pragmatis pemerintah dalam mengarahkan sumber daya pendidikan tinggi yang mungkin mengabaikan hak konstitusional otonomi perguruan tinggi.
Argumen sosiologis yang digunakan pemerintah mencakup ketidakmerataan fasilitas, tenaga pengajar, dan kurikulum di berbagai perguruan tinggi yang membuka prodi baru. Namun, dari perspektif hukum administrasi negara, kebijakan yang bersifat restriktif atau membatasi hak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan ekonomi atau manajerial semata. Muncul persoalan serius ketika instrumen yang digunakan untuk membatasi hak tersebut tidak memiliki derajat legalitas yang setara dengan dampak yang ditimbulkannya terhadap hak asasi manusia.
Kedudukan Yuridis Surat Edaran Sebagai Instrumen Pembatas Hak
Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan merupakan pilar utama dalam menjamin kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan secara limitatif. Surat Edaran (SE) secara formal tidak termasuk dalam daftar tersebut. Secara teoretis, Surat Edaran diklasifikasikan sebagai beleidsregel atau peraturan kebijakan yang merupakan produk dari kewenangan bebas (discretion/freies ermessen) pejabat administrasi negara.
Hakikat Surat Edaran adalah sebagai naskah dinas yang bersifat pemberitahuan, penjelasan, atau petunjuk teknis internal dalam suatu instansi. Karakteristik utama dari peraturan kebijakan adalah tidak adanya wewenang legislasi formal bagi pejabat yang menerbitkannya untuk membentuk norma yang mengikat publik secara luas. Oleh karena itu, Surat Edaran tidak diperkenankan memuat norma baru yang bersifat mengatur (regeling) apalagi yang bersifat membatasi hak asasi warga negara.
| Perbedaan Karakteristik | Peraturan Perundang-undangan (Regeling) | Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) |
| Dasar Kewenangan | Atribusi atau delegasi undang-undang | Diskresi (Freies Ermessen) |
| Sifat Mengikat | Umum dan keluar (Public binding) | Internal organisasi (Internal binding) |
| Hierarki Hukum | Diakui dalam UU No. 12 Tahun 2011 | Tidak termasuk hierarki formal |
| Fungsi Utama | Menciptakan norma hukum baru | Petunjuk operasional norma yang ada |
| Sanksi Hukum | Dapat memuat sanksi pidana/administratif | Tidak boleh memuat sanksi hukum |
Pembatasan hak melalui Surat Edaran merupakan pelanggaran terhadap asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, di mana peraturan yang lebih rendah dilarang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Mengingat hak atas pendidikan dijamin dalam konstitusi dan undang-undang, maka penghentian akses terhadap pembukaan program studi melalui instrumen administratif rendahan seperti SE secara otomatis kehilangan keabsahan materilnya. Praktik ini sering kali dianggap sebagai bentuk pelampauan wewenang karena menteri bertindak seolah-olah memiliki kekuasaan legislatif untuk menutup hak subjek hukum secara permanen tanpa proses perancangan undang-undang yang demokratis.
Pelanggaran Terhadap Hak Atas Pendidikan dalam Konstitusi.
Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Jaminan ini tidak membedakan antara tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 58/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Lebih lanjut, pendidikan tinggi merupakan sarana bagi warga negara untuk meningkatkan kualitas diri dan kompetensi profesional guna mencapai penghidupan yang layak.
Kebijakan moratorium pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan menghambat aksesibilitas dan ketersediaan pendidikan bagi warga negara. Ketika pemerintah menghentikan proses usulan baru, warga negara di wilayah-wilayah yang belum memiliki program studi tersebut terpaksa menempuh biaya pendidikan yang lebih mahal atau melakukan mobilisasi geografis yang memberatkan untuk dapat mengakses prodi kenotariatan di institusi yang sudah ada. Hal ini secara tidak langsung menciptakan ketimpangan akses pendidikan yang bertentangan dengan semangat pemerataan kualitas yang sering didengungkan pemerintah sendiri.
Selain itu, instrumen internasional seperti International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga mengamanatkan bahwa pendidikan tinggi harus terbuka bagi semua orang secara adil berdasarkan kemampuan. Penutupan pintu pembukaan program studi baru bagi universitas yang sebenarnya telah mampu dan memenuhi standar kualitas merupakan bentuk pengingkaran terhadap kewajiban progresif negara dalam memperluas cakupan layanan pendidikan. Moratorium yang tidak memiliki batasan waktu yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi institusi pendidikan yang ingin berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.
Analisis Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 : Batasan Pembatasan Hak
UUD 1945 memang mengenal konsep pembatasan hak, namun pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pasal 28J ayat (2) menetapkan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang“. Frasa “ditetapkan dengan undang-undang” merupakan kunci konstitusionalitas yang seringkali diabaikan dalam kebijakan administratif.
Makna dari pasal tersebut adalah segala bentuk restriksi terhadap hak asasi manusia hanya boleh dilakukan melalui instrumen hukum yang merupakan hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif (Undang-Undang). Penggunaan Surat Edaran untuk melakukan moratorium pembukaan program studi jelas-jelas menyimpangi mandat konstitusional ini karena SE merupakan produk sepihak dari eksekutif.
| Kriteria Pembatasan Hak | Kesesuaian Kebijakan Moratorium |
| Legalitas (Dasar Hukum) | Gagal (Hanya menggunakan Surat Edaran, bukan UU) |
| Legitimasi Tujuan | Parsial (Kualitas pendidikan adalah tujuan sah, namun cara pencapaiannya cacat) |
| Proporsionalitas | Gagal (Menutup total akses alih-alih memperketat akreditasi) |
| Kebutuhan Demokratis | Gagal (Tidak melalui proses pembahasan publik/parlemen) |
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah membatalkan norma hukum yang memberikan kewenangan pembatasan hak tanpa parameter yang jelas dalam undang-undang. Jika undang-undang saja dapat dibatalkan apabila tidak memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil, maka Surat Edaran yang memuat materi pembatasan hak seharusnya dianggap tidak memiliki daya ikat hukum sejak awal. Ketidaksesuaian prosedur ini merupakan bukti nyata bahwa moratorium tersebut bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi.
Dampak Terhadap Hak Atas Pekerjaan dan Pengembangan Diri.
Profesi notaris merupakan salah satu jalan bagi warga negara untuk mengaktualisasikan diri dan mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Karena syarat untuk menduduki jabatan notaris adalah pendidikan magister kenotariatan, maka pembatasan terhadap pembukaan prodi tersebut secara otomatis berdampak pada pembatasan peluang warga negara untuk memasuki profesi tersebut.
Pemerintah berargumen tentang “kejenuhan lulusan”, namun dalam perspektif konstitusi, negara tidak boleh menghambat warga negara untuk menempuh jalur pendidikan tertentu hanya karena prediksi pasar tenaga kerja yang belum tentu akurat. Hak untuk memilih pekerjaan dan mengembangkan diri melalui pendidikan adalah hak individu yang harus dihormati. Diskriminasi terselubung terjadi ketika pemerintah mempermudah pembukaan prodi STEM namun mempersulit prodi hukum, yang seolah-olah menganggap bidang ilmu hukum kurang bernilai secara strategis dibandingkan ilmu teknik.
Lebih jauh, moratorium ini berdampak pada otonomi perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi memiliki hak untuk mengembangkan visi akademik dan berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Dengan adanya moratorium, negara telah melakukan intervensi yang berlebihan terhadap kebebasan akademik dan otonomi institusional perguruan tinggi yang sebenarnya dilindungi oleh prinsip-prinsip pendidikan tinggi yang demokratis.
Preseden Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022.
Kajian mengenai validitas pembatasan hak dalam jabatan notaris dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022. Dalam putusan tersebut, MA membatalkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 yang mewajibkan calon notaris mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN). Alasan utama pembatalan ini adalah karena persyaratan tersebut tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
| Analisis Perbandingan | Pembatasan Syarat PPKJN (Dibatalkan MA) | Moratorium Prodi MKN (Status KuO) |
| Instrumen Hukum | Peraturan Menteri (Permenkumham) | Surat Edaran (Kemenristekdikti) |
| Materi Muatan | Menambah syarat baru jabatan | Menutup akses institusional pendidikan |
| Pelanggaran Utama | Bertentangan dengan UUJN | Bertentangan dengan UUD 1945 & UU Dikti |
| Dampak Hukum | Tidak mengikat secara hukum | Menghambat hak konstitusional warga |
Putusan MA tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa lembaga eksekutif tidak boleh menambah syarat atau melakukan pembatasan yang tidak memiliki dasar hukum dalam undang-undang. Jika sebuah Peraturan Menteri yang hierarkinya lebih tinggi dari Surat Edaran saja dapat dibatalkan karena menambah syarat tanpa dasar undang-undang, maka Surat Edaran moratorium yang secara fundamental menghentikan hak penyelenggaraan pendidikan memiliki derajat pelanggaran hukum yang jauh lebih berat. Prinsip kepastian hukum menuntut agar negara tidak mengubah aturan main secara sepihak dan administratif melalui instrumen yang lemah kedudukan hukumnya.
Implikasi Ketidakpastian Hukum dalam Layanan Administrasi Pendidikan.
Moratorium yang berkepanjangan menciptakan kekosongan regulasi dan ketidakpastian bagi penyelenggara pendidikan. Banyak fakultas hukum di Indonesia yang telah memiliki sumber daya dosen bergelar doktor hukum dan sarana prasarana memadai, namun tetap ditolak usulannya hanya berdasarkan Surat Edaran tahun 2019 yang belum dicabut. Hal ini mengakibatkan terjadinya stagnasi pengembangan keilmuan kenotariatan di daerah-daerah berkembang.
Dalam praktik administrasi negara, penggunaan Surat Edaran sebagai instrumen “moratorium abadi” merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Surat Edaran seharusnya digunakan untuk situasi yang mendesak dan bersifat sementara, namun dalam konteks kenotariatan, ia telah menjadi instrumen permanen untuk mengendalikan pasar pendidikan. Tanpa adanya evaluasi yang transparan dan parameter yang jelas mengenai kapan moratorium akan berakhir, kementerian telah bertindak di luar koridor tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance).
Selain itu, sistem perizinan terintegrasi seperti SIAGA yang secara otomatis menolak usulan prodi kenotariatan menunjukkan adanya automasi diskriminasi dalam birokrasi pendidikan. Hal ini menghalangi hak institusi pendidikan untuk mendapatkan penilaian yang objektif atas kesiapan mereka, karena sistem langsung menutup pintu berdasarkan label “moratorium” tanpa mempertimbangkan kualitas individu perguruan tinggi pengusul.
Korelasi Pendidikan Kenotariatan dengan Kepastian Hukum Agraria.
Pentingnya pembukaan program studi magister kenotariatan di berbagai daerah berkaitan erat dengan kebutuhan pejabat umum yang handal dalam mendukung pendaftaran tanah. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Implementasi dari pasal ini memerlukan infrastruktur hukum, termasuk notaris/PPAT yang tersebar merata untuk menjamin kepastian hak atas tanah masyarakat.
Ketika pendidikan kenotariatan dibatasi secara kaku melalui moratorium, terjadi disparitas distribusi notaris. Daerah-daerah terpencil mungkin tidak mendapatkan akses terhadap pejabat umum yang berkualitas karena pendidikan kenotariatan hanya terkonsentrasi di kota-kota besar yang telah memiliki prodi lama. Hal ini menghambat efektivitas program-program pemerintah dalam redistribusi aset dan sertifikasi tanah. Dengan demikian, moratorium prodi kenotariatan bukan hanya masalah administratif pendidikan, melainkan juga masalah aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat luas.
Rekomendasi Penataan Ulang Kebijakan Berbasis Konstitusionalisme.
Berdasarkan analisis hukum yang komprehensif ini, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengembalikan kebijakan pendidikan kenotariatan ke koridor konstitusi :
- Pencabutan Surat Edaran Moratorium : Pemerintah harus segera mencabut SE No. 3/M/SE/VIII/2019 karena secara substansial melanggar prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan hak konstitusional warga negara.
- Standardisasi Berbasis Undang-Undang : Segala bentuk pembatasan atau pengendalian jumlah program studi harus dituangkan dalam instrumen hukum yang sah (minimal Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang didasarkan pada delegasi UU Pendidikan Tinggi) dengan parameter yang objektif, bukan sekadar Surat Edaran.
- Penerapan Akreditasi Ketat Sebagai Filter : Daripada menutup pintu pembukaan prodi baru secara total, pemerintah seharusnya memperketat standar akreditasi minimum. Perguruan tinggi yang mampu memenuhi kualifikasi dosen, sarana, dan kurikulum yang sangat tinggi harus tetap diberikan hak untuk membuka program studi tersebut demi menjamin persaingan kualitas.
- Sinkronisasi dengan Kebutuhan Daerah : Penentuan kuota atau pemberian izin prodi harus didasarkan pada studi kebutuhan riil pejabat umum di masing-masing provinsi, sehingga moratorium tidak bersifat general melainkan selektif berdasarkan peta kebutuhan layanan hukum nasional.
Penegakan hukum konstitusi dalam kebijakan pendidikan merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya negara hukum yang adil. Pengabaian terhadap hak atas pendidikan dan pelampauan wewenang melalui instrumen administratif rendahan hanya akan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan sistem hukum secara keseluruhan. Reformasi kebijakan ini menjadi urgen untuk memastikan bahwa akses terhadap profesi terhormat seperti notaris tetap terbuka bagi seluruh warga negara yang kompeten, tanpa dihambat oleh regulasi yang cacat secara hukum.
Kesimpulan Akhir : Menuju Tatanan Pendidikan Tinggi yang Konstitusional.
Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan moratorium pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Edaran merupakan tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945. Pelanggaran tersebut mencakup pengabaian terhadap hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 31), hak untuk mengembangkan diri dan bekerja (Pasal 27 dan 28C), serta pelanggaran terhadap prosedur pembatasan hak yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2).
Secara administratif, penggunaan Surat Edaran sebagai instrumen pembatas hak merupakan bentuk malpraktik hukum karena menyalahi hakikat SE sebagai beleidsregel yang tidak memiliki daya ikat umum. Preseden dari Mahkamah Agung dalam kasus-kasus serupa telah menunjukkan bahwa pembatasan hak tanpa dasar undang-undang yang kuat adalah cacat hukum. Oleh karena itu, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, pemerintah harus segera menata ulang kebijakan ini dengan menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dan otonomi pendidikan tinggi di Indonesia. []
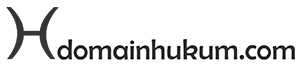



















Komentar