Peran, Tugas, Fungsi, Kewenangan, daan Manfaat Bank Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia.
Oleh :
Dr. KRA. MJ. Widijatmoko SH Sp.N
Abstrak
Sistem pengawasan hakim di Indonesia melibatkan dualisme kewenangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). MA melakukan pengawasan teknis yudisial dan disipliner, sementara KY fokus pada etika dan perilaku. Makalah ini menganalisis argumentasi bahwa pembagian kewenangan ini, alih-alih memperkuat, justru berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan hakim, menciptakan celah impunitas, dan mengikis kepercayaan publik.
Fokus analisis akan mencakup dasar hukum pembagian kewenangan, implikasi yuridis dan praktis dari dualisme ini, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan sistem.
Kata Kunci : Pengawasan Hakim, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Integritas Peradilan, Dualisme Kewenangan, Kode Etik Hakim.
I. Pendahuluan.
Integritas peradilan adalah pilar utama tegaknya supremasi hukum dan keadilan. Hakim, sebagai representasi dari institusi peradilan, memegang peranan krusial dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan terhadap hakim mutlak diperlukan untuk memastikan mereka menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan berintegritas.
Di Indonesia, sistem pengawasan hakim melibatkan dua lembaga utama, yaitu Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif tertinggi dan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat konstitusi.
Pembagian kewenangan antara kedua lembaga ini telah menjadi diskursus panjang, dengan argumentasi bahwa dualisme ini justru berpotensi melemahkan pengawasan, bukan menguatkan.
Penulis akan mengkaji lebih dalam dasar hukum, implikasi, dan alternatif penyelesaian terhadap isu tersebut.
II. Dasar Hukum Dualisme Pengawasan Hakim.
Pembagian kewenangan pengawasan hakim memiliki dasar hukum pada :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) :
a. Pasal 24A ayat (1) menyatakan bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ini secara implisit memberikan kewenangan pengawasan internal bagi MA.
b. Pasal 24B ayat (1) menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) :
a. UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 (perubahan kedua).
MA memiliki fungsi pengawasan, baik pengawasan internal (struktural) terhadap penyelenggaraan peradilan maupun pengawasan atas perilaku hakim dan pegawai.
b. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Mempertegas bahwa MA melakukan pengawasan teknis yudisial, sedangkan pengawasan etika dan perilaku hakim menjadi kewenangan KY.
3. Undang-Undang Komisi Yudisial (UU KY) :
a. UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. UU Nomor 18 Tahun 2011 (perubahan).
Merinci tugas dan wewenang KY, termasuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Dari kerangka hukum di atas, terlihat adanya pembagian peran: MA fokus pada aspek teknis yudisial dan disiplin internal, sedangkan KY berfokus pada aspek etika dan perilaku hakim sebagai personal.
III. Argumen: Dualisme Pengawasan Melemahkan Pengawasan Hakim.
Pihak yang berpendapat bahwa dualisme pengawasan justru melemahkan integritas hakim didasari oleh beberapa argumen kuat :
A. Saling Lempar Tanggung Jawab dan Tumpang Tindih Kewenangan.
Dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih antara pelanggaran kode etik dan pelanggaran disipliner atau teknis yudisial. Ketika ada laporan masyarakat, MA dan KY kerap berdebat mengenai siapa yang lebih berwenang menindaklanjuti. Ini menyebabkan “bola panas” dan penundaan penanganan kasus.
Kesenjangan kewenangan ini menciptakan “zona abu-abu” yang dapat dimanfaatkan oleh hakim nakal untuk menghindari pertanggungjawaban. Laporan masyarakat seringkali tidak ditindaklanjuti secara optimal karena adanya tarik-menarik antar lembaga, atau bahkan saling menyalahkan ketika kasus tidak terselesaikan. Ini adalah bentuk “pemadulan” de facto terhadap pengawasan.
B. Keterbatasan Kewenangan KY yang Non-Eksekutorial.
Meskipun KY berwenang menerima laporan dan melakukan investigasi dugaan pelanggaran KEPPH, putusan atau rekomendasi KY bersifat non-eksekutorial. Artinya, KY tidak dapat menjatuhkan sanksi secara langsung kepada hakim. Rekomendasi KY harus disampaikan kepada MA untuk ditindaklanjuti, dan MA memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolak rekomendasi tersebut.
Kewenangan KY yang terbatas pada rekomendasi membuat lembaga ini “ompong” atau tidak memiliki “gigi” untuk menegakkan etika hakim. Ketika rekomendasi KY tidak ditindaklanjuti oleh MA atau ditindaklanjuti dengan sanksi yang ringan, hal ini merusak efek jera (deterrent effect) dari pengawasan. Hakim yang melanggar akan merasa aman karena tahu bahwa lembaga pengawas eksternal tidak memiliki kekuatan memaksa, dan pengawasan internal oleh MA pun cenderung tertutup atau kurang transparan. Ini menciptakan impunitas struktural.
C. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas MA.
Pengawasan internal yang dilakukan oleh MA seringkali kurang transparan bagi publik. Proses investigasi, hasil temuan, hingga sanksi yang dijatuhkan cenderung tidak diumumkan secara terbuka, berbeda dengan KY yang lebih transparan dalam melaporkan hasil investigasinya.
Kurangnya transparansi MA dalam penanganan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh hakimnya sendiri dapat menimbulkan kecurigaan publik adanya upaya “menutupi” atau “melindungi” oknum hakim. Ketiadaan akuntabilitas publik ini memperparah persepsi bahwa pengawasan internal MA tidak efektif atau bahkan terlibat dalam praktik korupsi. Ini juga menunjukkan adanya konflik kepentingan internal, di mana MA sebagai badan yudikatif juga harus mengawasi dirinya sendiri.
D. Budaya Esprit de Corps di Kalangan Hakim.
Adanya rasa solidaritas yang tinggi (esprit de corps) di kalangan hakim terkadang dapat menjadi penghambat pengawasan yang efektif. Ada kecenderungan untuk saling melindungi sesama “korps” atau menganggap masalah etik sebagai urusan internal yang tidak perlu dicampuri pihak luar.
Budaya ini dapat mempersulit KY dalam melakukan investigasi, karena akses terhadap informasi atau saksi internal mungkin terhambat. Jika MA, sebagai pemimpin “korps,” tidak proaktif dalam menegakkan disiplin dan etika, maka budaya ini akan semakin memperkuat kelemahan pengawasan.
IV. Implikasi Hukum dan Praktis dari Pelemahan Pengawasan.
1. Peningkatan Pelanggaran Kode Etik dan Korupsi.
Celah pengawasan dan impunitas yang tercipta dari dualisme ini dapat mendorong oknum hakim untuk lebih berani melanggar kode etik, bahkan terlibat dalam praktik korupsi, suap, dan mafia peradilan.
2. Erosi Kepercayaan Publik.
Ketika masyarakat melihat bahwa hakim, yang seharusnya menjadi penegak keadilan, justru kebal dari pengawasan yang efektif, maka kepercayaan terhadap sistem peradilan akan menurun drastis. Hal ini berbahaya bagi legitimasi hukum.
3. Hambatan dalam Pemberantasan Mafia Peradilan.
Kasus-kasus mafia peradilan seringkali melibatkan oknum hakim. Lemahnya pengawasan menyulitkan upaya pemberantasan jaringan kejahatan ini.
4. Ketidakpastian Hukum.
Keputusan yang dihasilkan oleh hakim yang tidak berintegritas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena putusan tersebut mungkin tidak didasarkan pada keadilan dan kebenaran substantif, melainkan pada kepentingan pribadi atau kelompok.
V. Rekomendasi untuk Penguatan Pengawasan Hakim.
Untuk mengatasi pelemahan pengawasan akibat dualisme ini, diperlukan reformasi komprehensif :
1. Penguatan Kewenangan KY yang Eksekutorial.
Amandemen UU KY dan/atau UU MA yang memberikan kewenangan final dan mengikat kepada KY untuk menjatuhkan sanksi disipliner tertentu (misalnya sanksi ringan hingga sedang) atau setidaknya membuat rekomendasi KY menjadi wajib ditindaklanjuti oleh MA dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibatalkan tanpa alasan yang sah dan transparan. Ini akan memberikan “taring” yang dibutuhkan KY.
2. Integrasi atau Sinkronisasi.
Perlu dibentuk mekanisme terpadu antara MA dan KY dalam menerima, memverifikasi, menginvestigasi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Bisa berupa “Majelis Kehormatan Hakim Bersama” yang permanen atau prosedur baku yang jelas untuk penyerahan kasus dari KY ke MA dan sebaliknya, dengan batas waktu yang ketat.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas MA.
MA harus lebih terbuka dalam mempublikasikan hasil pengawasan internalnya terhadap hakim, termasuk jenis pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan (dengan tetap memperhatikan perlindungan privasi yang relevan). Ini akan membangun kepercayaan publik dan menunjukkan keseriusan MA dalam menjaga integritas.
4. Peningkatan Kapasitas dan Integritas Pengawas.
Baik MA maupun KY perlu didukung dengan anggaran, sumber daya manusia yang berkualitas, dan pelatihan yang memadai. Penting juga untuk memastikan bahwa aparat pengawas itu sendiri memiliki integritas yang tinggi dan terbebas dari intervensi.
5. Revisi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
KEPPH perlu direvisi agar lebih spesifik, jelas, dan relevan dengan tantangan saat ini, serta mencakup sanksi yang berjenjang dan memberikan efek jera.
VI. Kesimpulan.
Argumen bahwa pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan oleh lembaga yang berbeda justru melemahkan pengawasan hakim memiliki dasar yang kuat dalam pengalaman praktik di Indonesia.
Dualisme kewenangan antara MA dan KY, terutama yang diperparah oleh keterbatasan kewenangan eksekutorial KY dan kurangnya transparansi MA, telah menciptakan celah impunitas yang memungkinkan pelanggaran etika dan praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Untuk mengembalikan marwah dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, integrasi, sinkronisasi, dan penguatan kewenangan, terutama pada Komisi Yudisial, menjadi keniscayaan. Hanya dengan sistem pengawasan yang kuat, transparan, akuntabel, dan memiliki efek jera, integritas hakim dan kemerdekaan peradilan yang sejati dapat diwujudkan di Indonesia.
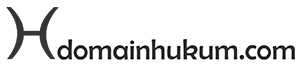



















Komentar