Tumpang Tindihnya Amicus Curiae dengan Keterangan Ahli dalam Perkara yang Melibatkan Notaris atau PPAT Dapat Merugikan Pihak Yang Berperkara
Dr. KRA. MJ. Widijatmoko SH Sp.N
Penulis & Peneliti MjWinstitute Jakarta
Dosen Universitas Djuanda Bogor.
Pendahuluan.
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah landasan konstitusional yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Ayat tersebut menyatakan: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Yang dimaksud dengan “bumi” adalah permukaan bumi (tanah) dan isi serta dalam bumi (kekayaan sumber daya alam dalam bumi). Pengertian “air” disini termasuk sungai, danau, rawa, pantai, laut dan air yang terdapat dalam bumi.
Secara literal, pasal ini menyebutkan “dikuasai oleh negara”, yang seringkali disalahartikan sebagai kepemilikan mutlak negara. Namun, interpretasi hukum yang benar dan mendalam, terutama jika dihubungkan dengan semangat kemerdekaan dan tujuan pendirian negara, menunjukkan adanya perbedaan fundamental antara “milik bangsa” dan “milik negara”. Oleh karena itu perlu diketahui dan dipahami perbedaan mendasar tersebut berdasarkan landasan hukum, filosofi, dan implikasinya dalam praktik hukum agraria Indonesia.
- Landasan Filosofis dan Konstitusional. 1.Hakikat Kepemilikan Bangsa.
Konsep “milik bangsa” mengacu pada kepemilikan kolektif seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah hak yang bersifat abstrak, abadi, dan tidak dapat dipindahtangankan. Bangsa, sebagai entitas kolektif, adalah subjek hukum yang memiliki hak ulayat tertinggi atas seluruh sumber daya alam Indonesia. Kepemilikan ini tidak hanya mencakup rakyat yang hidup saat ini, tetapi juga mencakup generasi-generasi mendatang.
- Kedudukan Negara sebagai Mandataris Bangsa.
Di sisi lain, negara adalah organisasi kekuasaan yang didirikan oleh bangsa. Dalam konteks ini, negara tidak memiliki hak kepemilikan substantif. Sebaliknya, negara bertindak sebagai mandataris atau kuasa dari bangsa.
Tugas utama negara adalah menguasai sumber daya alam tersebut, yang berarti:
- Mengatur: Membuat peraturan dan kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam.
- Mengelola: Mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan.
- Mengawasi: Memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai hukum dan tidak merugikan kepentingan rakyat.
- Melindungi: Menjaga sumber daya alam dari eksploitasi berlebihan atau kerusakan lingkungan.
Fungsi penguasaan oleh negara ini tidak boleh disamakan dengan hak kepemilikan pribadi yang bisa diperjualbelikan atau digadaikan.
Negara hanya memiliki wewenang untuk mengatur, bukan untuk memiliki secara mutlak.
III. Perbedaan dalam Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 2 UUPA secara tegas menyatakan:
“(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”
Frasa “sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat” dalam pasal ini memperjelas kedudukan negara sebagai pemegang amanah. Ini adalah penegasan hukum bahwa penguasaan negara bukanlah kepemilikan, melainkan wewenang untuk mengatur dan mengelola demi kepentingan bangsa.
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Konstitusi (MK) telah berulang kali menegaskan perbedaan ini melalui putusan-putusannya. Dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 terkait Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, MK menjelaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam mengandung makna:
- Pengaturan: Negara berhak membuat regulasi untuk mengontrol sektor sumber daya alam.
- Pengurusan: Negara berhak mengelola langsung sumber daya alam tersebut.
- Pengawasan: Negara berhak mengawasi operasional dan kegiatan usaha terkait sumber daya alam.
Putusan ini secara eksplisit menolak penafsiran bahwa negara memiliki hak kepemilikan privat. MK menekankan bahwa kewenangan negara hanyalah untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai amanat konstitusi, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Implikasi Hukum dan Praktis. 1.Pembatasan Hak Individu.
Konsekuensi dari asas ini adalah tidak adanya hak kepemilikan pribadi yang bersifat mutlak atas tanah dan sumber daya alam. Setiap hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), atau Hak Guna Bangunan (HGB), selalu memiliki fungsi sosial. Artinya, pemanfaatannya tidak boleh merugikan kepentingan umum dan harus tetap memperhatikan keberlanjutan.
- Pengakuan Hak Ulayat.
Perbedaan antara kepemilikan bangsa dan penguasaan negara juga menjadi dasar hukum untuk mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat. Hak ulayat adalah hak kepemilikan kolektif masyarakat adat atas wilayahnya, yang merupakan perwujudan dari kepemilikan bangsa yang lebih spesifik. Negara wajib menghormati hak ini, dan tidak boleh serta-merta memberikan izin konsesi kepada pihak lain tanpa persetujuan masyarakat adat.
- Sektor Strategis dan Monopoli Negara.
Dalam bidang energi dan air, asas ini memberikan landasan bagi negara untuk melakukan monopoli atau penguasaan penuh atas sektor-sektor strategis, seperti listrik, minyak, dan air bersih. Hal ini bertujuan untuk mencegah penguasaan oleh segelintir pihak swasta dan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
Penutup.
Berdasarkan analisis hukum dan filosofis, jelas bahwa kepemilikan atas sumber daya alam Indonesia adalah milik bangsa secara kolektif, sementara negara hanya memiliki wewenang untuk menguasai dan mengelola sebagai mandataris.
Penafsiran yang keliru atas hal ini sering kali menjadi akar dari berbagai masalah agraria, seperti konflik tanah, perusakan lingkungan, dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.
Memahami dan mengimplementasikan perbedaan ini secara konsisten adalah kunci untuk mewujudkan keadilan agraria, melindungi hak-hak masyarakat adat, dan memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. []
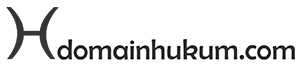



















Komentar